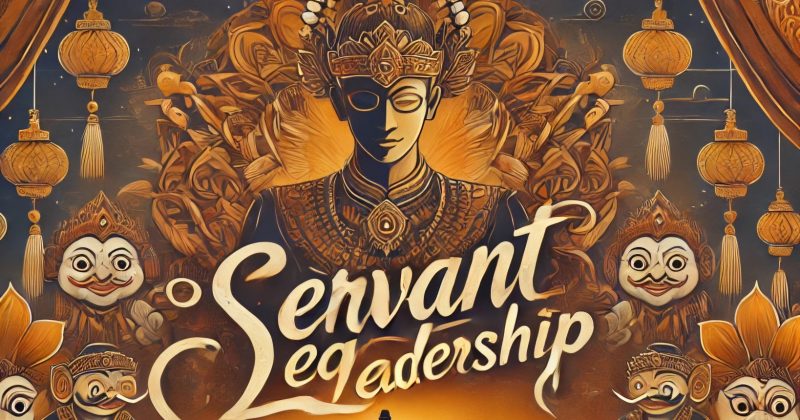Surat yang Tidak Pernah Sampai
“Kadang yang paling berani bukan yang maju bertempur, melainkan yang memilih berhenti mengejar—lalu pulang dan merapikan dirinya sendiri.”
“Jika kau kehilangan seseorang, jangan biarkan dirimu ikut hilang.”
“Ada luka yang tidak perlu diumumkan. Cukup dipeluk sampai tenang.”
.
Baca dulu Part 1 dari Trilogi ini: Sepotong Langit di Meja Kopi
.
“Ada surat yang tidak dikirim, bukan karena tidak penting, tapi karena akhirnya kita sadar—kita menulisnya bukan untuk dia, tapi untuk diri sendiri.” — Sepucuk Surat, Sebuah Perpisahan
.
Zea tidak menghapus foto itu dari dompetnya. Ia tidak membuang kenangan. Tapi sore itu, ia menulis. Bukan status. Bukan pesan. Melainkan surat—surat panjang yang tidak pernah ia kirim.
Di luar, Jakarta seperti biasa saja: langit menampung awan berat; lalu lintas menderu; pejalan kaki saling menghindar di trotoar yang baru dirapikan. Di dalam kedai kecil dekat perempatan Sudirman-Dukuh Atas, waktu memanjang seperti bus TransJakarta yang berhenti terlalu lama. Jam dinding melangkah hati-hati. Musik akustik pelan. Aroma kopi menyergap, tajam dan jujur.
Meja nomor tujuh. Meja yang pernah menyelamatkannya dari kebisingan; meja yang sama tempat ia dan Arka pernah tertawa tanpa suara, hanya saling menunjuk kalimat dalam buku—seolah sesuatu akan selalu bisa diselamatkan jika disepakati bersama.
Sore itu, Zea kembali ke meja nomor tujuh. Kali ini tanpa polaroid, tanpa kopi, tanpa alasan. Ia hanya membawa satu hal: selembar kertas kosong dan pena.
Barista—pemuda berambut sebahu bernama Jayeng—melirik sesaat dan tak menyapa. Mereka sudah paham: jika Zea datang dan tidak segera memesan, berarti ia sedang berada dalam misi penting—menyusun kembali hatinya. Di meja kasir, gantungan nama kecil bertuliskan “Jayeng” sering disangka nama panggilan dari “Jaya.” Hanya Zea yang pernah bertanya, “Nama itu dari mana?” dan Jayeng menjawab ringan, “Dari cerita lama yang sering almarhum kakek bacakan. Katanya, dulu ada Jayeng yang berkelana mencari yang dicintainya. Tapi akhirnya ia menemukan dirinya sendiri.”
Zea menatap lembar kosongnya. Angin dari ventilasi menepis rambutnya, sementara jendela besar memantulkan wajah pejalan yang lewat. Ada sesuatu di dalam dadanya—bukan sesak, bukan juga lega. Lebih mirip ruang baru yang belum dipasangi perabot.
Ia mulai menulis.
,
Meja yang Sama, Perasaan yang Berbeda
Dua minggu setelah pertemuan singkat itu—pertemuan yang anehnya tidak terasa sebagai pertemuan—Zea kembali. Waktu itu Arka muncul tiba-tiba, menanyakan kabar yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, lalu bercerita tentang proyek barunya di Bandung. Ia datang berkemeja abu-abu, jaket kulit disampirkan di kursi, kamera analog tergantung di leher: semua properti lama yang dahulu ia banggakan, kini terasa seperti kostum.
Percakapan mereka seperti hujan yang malu-malu—jatuh sebentar, reda, lalu ragu untuk turun lagi. Tak ada yang diucapkan, tapi banyak yang dipahami. Mereka berpisah tanpa jabat tangan, tanpa janji “ketemu lagi.” Seolah kota sudah mengajari keduanya: perpisahan yang sungguh-sungguh tak membutuhkan seremoni.
Sejak itu, Zea belajar hal-hal kecil yang tidak diajarkan buku: menyetel mesin cuci pada malam paling sepi; merendam sayur agar tetap renyah; menghitung ulang belanjaan di minimarket karena gaji kadang terlambat masuk; mencatat mimpi yang datang jam tiga pagi agar tidak lupa mengapa ia harus tetap bangun.
Dan ia juga belajar cara menata memori: tidak menghapus foto lama, hanya memindahkannya ke folder bernama “Sementara.” Menyimpan tiket bioskop di kotak sepatu bersama secarik kertas yang masih menyimpan bau parfum lawas. Kadang-kadang di MRT, ia membuka galeri dan membiarkan jarinya meluncur. Setelah beberapa detik, ia menutupnya lagi. Tidak ada yang perlu dibuang; cukup dibiarkan tenang pada tempatnya.
Sore ini, ia menuliskan yang selama ini tertahan.
.
Isi Surat
Arka,
Aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu. Mungkin tidak. Dan aku rasa, itu bukan hal yang penting lagi.
Aku menulis ini bukan karena aku berharap kau kembali. Aku juga tidak sedang merindukanmu. Aku hanya ingin mengeluarkan sesuatu yang tertahan terlalu lama.
Waktu kita pernah indah, dan aku bersyukur untuk itu. Tapi kepergianmu—caramu menghilang, caramu memilih diam tanpa kejelasan—itu mengajarkan aku sesuatu: bahwa seseorang bisa sangat mencintai, tapi tetap tidak bisa memiliki.
Aku pernah bertanya-tanya, di mana letak kesalahannya? Di aku? Di kamu? Atau di semesta? Tapi sekarang, aku tidak lagi mencari siapa yang salah. Aku hanya ingin belajar menerima bahwa memang tidak semua hal harus dimiliki untuk bisa dikenang.
Setelah kamu pergi, aku belajar menyeduh kopi dengan takaran yang pas. Aku belajar bangun pagi tanpa berharap ada notifikasi dari namamu. Aku belajar menyembuhkan luka tanpa meminta penjelasan dari orang yang melukai.
Dan kini, aku baik-baik saja.
Terima kasih karena pernah membuat hatiku penuh. Dan terima kasih juga, karena pernah membuatnya hancur. Tanpa itu, aku tidak akan pernah tahu, betapa kuatnya aku bisa bertahan.
Jika nanti kita bertemu lagi di tempat yang berbeda, dalam hidup yang berbeda, aku harap kita bisa saling tersenyum—bukan karena ingin kembali, tapi karena kita pernah saling memilih… meski tidak sampai akhir.
—Zea
Zea berhenti. Ia mengembuskan napas pelan, menatap kertas itu lama-lama, seperti menatap telapak tangan sendiri. Di luar, lampu-lampu kendaraan menyalah satu-satu, membentuk sungai cahaya. Jakarta berpindah dari siang ke petang seperti tirai panggung yang turun perlahan.
“Teh chamomile?” suara Jayeng menawar dengan sopan. Zea mengangguk. Ia tak memesan sedari tadi. Cangkir diletakkan tanpa bunyi. “Hati-hati panas,” kata Jayeng, lalu pergi.
Di balik gelas yang berembun tipis, Zea melihat bayangannya sendiri—lebih tegas dari kemarin, lebih jernih dari minggu lalu.
.
Mengirim atau Menyimpan?
Ia melipat surat itu rapi, menaruhnya dalam amplop. Menulis nama Arka di sudut kiri. Ia menatapnya cukup lama untuk mengizinkan perpisahan terjadi sekali lagi, kali ini tanpa saksi dan tanpa perdebatan.
Di depan pintu kedai, kotak pos kecil tergantung seperti mulut yang selalu siap menerima. Zea berdiri beberapa langkah, menimbang-nimbang. Jarak antara dirinya dan kotak itu hanya tiga tapak, tapi rasanya seperti menyeberangi jembatan rapuh yang pernah ia lewatkan.
Kemudian ia tertawa kecil. Ada yang berubah. Surat ini bukan lagi isyarat untuk orang lain; ia adalah cermin. Dan apa gunanya mengirim cermin?
Zea kembali ke meja, menyelipkan amplop ke dalam buku hariannya. Ia tahu: ini bukan tentang Arka. Ini tentang dirinya. Tentang membereskan ruang yang pernah berantakan, dan tidak harus diberitahukan siapa pun bahwa ia telah berhasil membereskannya. Surat itu ia simpan di laci, bersama pulpen, bersama damai.
.
Hujan di Luar Jendela
Rintik pertama jatuh. Lalu rapat. Jakarta, seperti kebiasaan lamanya, menampung hujan sambil memuntahkan klakson. Zea menempelkan dahi ke kaca jendela, merasakan dingin yang wajar. Tidak ada rasa sesak. Tidak ada air mata. Ia tahu, kali ini tidak akan ada yang masuk lewat pintu dengan jaket kulit dan kamera di leher. Dan itu tidak apa-apa. Ia sudah tidak menunggu.
Kadang, menunggu yang paling menyakitkan bukanlah menanti seseorang kembali. Tapi menanti keberanian untuk berdamai dengan apa yang tidak akan pernah kembali. Zea merasakan kalimat itu jatuh, pas, seperti koin yang menutup celengan terakhir.
Ia menyelesaikan tehnya, membayar, dan menepi di halte. Lampu-lampu kota berpendar seperti bintik pada foto analog yang belum dicuci sempurna.
“MRT arah Lebak Bulus tiba sebentar lagi,” suara perempuan dari pengeras terdengar. Zea menarik napas. Ia naik, berdiri dekat pintu, memandang rel yang memanjang, menyisakan garis-garis yang entah menuju mana. Di kaca pintu, pantulan wajahnya bersisian dengan pantulan penumpang lain: seorang perempuan muda memeluk map lamaran kerja; seorang bapak menutup mata pura-pura tidur; sepasang anak SMA tertawa lirih.
Jakarta selalu punya cerita di setiap gerbong. Malam itu, cerita Zea sederhana: ia baru saja menolak mengirim surat.
.
Kota, Nama-Nama, dan Cerita yang Menyeberang
Keesokan harinya, di kantor rintisan tempat Zea bekerja sebagai penulis naskah, bosnya—perempuan tangkas bernama Retna—memintanya menyiapkan konten kampanye untuk peluncuran komunitas literasi. “Kita pakai tema surat,” kata Retna. “Surat kepada diri sendiri. Biar orang ingat, menulis kadang bukan untuk dilihat orang lain.”
Zea menelan ludah. Dunia kadang punya cara mengembalikan kita pada sesuatu yang baru saja kita putuskan.
“Bisa?” tanya Retna.
“Bisa,” jawab Zea.
Di meja sebelah, rekan kerjanya—Adaninggar—menyodorkan draft. “Aku pakai tokoh anak magang yang menulis untuk ibunya. Boleh pinjam matamu?” Zea membaca. Ada kalimat yang terlalu manis, ada yang terlalu benar. Ia mengedit dengan sabar, memotong kata “selamanya” menjadi “untuk saat ini,” menghapus “takdir” lalu menggantinya dengan “pilihan.” Adaninggar mengangguk, “Terima kasih. Kau selalu tahu cara menaruh kata di tempatnya.”
Sebelum pulang, Zea melewati lampu neon di lorong kantor yang sering berkedip. Ia teringat tokoh-tokoh yang dibacakan kakeknya waktu kecil—kisah Menak yang penuh perjalanan: Jayeng yang pergi, Retna yang menunggu, Adaninggar yang beradu alasan, Kelaswara yang memahami terlalu cepat. Nama-nama itu kini hidup sekitar Zea, hadir sebagai rekan kerja, barista, penjual nasi uduk di bawah jembatan. Kota menyimpan kisah-kisah lama dalam wujud baru, pikirnya. Tidak ada yang benar-benar hilang; semuanya beralih rupa.
.
Kilas Balik: Hari-Hari yang Mengajarkan
Di kamar kontrakannya di Setiabudi, Zea membuka laci dan mengeluarkan kotak sepatu. Di sana, tersimpan tiket konser lama, kertas parkir, seuntai tali kamera milik Arka yang pernah tertinggal dan tak pernah diambil. Dulu, barang-barang itu seperti pancingan untuk marah. Sekarang, semuanya seperti batu-batu kecil penanda jalan: “Kau pernah lewat sini, dan kau selamat.”
Ia menyalakan lampu meja, menulis satu lembar lagi. Bukan untuk Arka. Untuk dirinya di masa silam—Zea yang menunggu di halte hujan sambil memeriksa ponsel berkali-kali.
Untuk Zea yang dulu,
kalau kau membaca ini di malam yang sunyi, percayalah: kelak kau akan berhasil tersenyum pada hal-hal yang dulu menghancurkanmu. Bukan karena kau lupa, melainkan karena kau telah merapikan yang berserakan. Kau akan bangun pagi dan menyalakan kompor tanpa menengok notifikasi. Kau akan pulang malam dan mematikan lampu tanpa merasa ada yang kurang.
Kau akan sampai.
—Zea yang sekarang.
Ia menutup buku. Di halaman terakhir, ia menempelkan kutipan yang ia temukan dari catatan di ponsel: “Bahagia itu bukan tentang tidak pernah kehilangan. Bahagia itu tentang tidak kehilangan dirimu saat kehilangan.”
.
Pertemuan yang Bukan Kebetulan
Beberapa hari kemudian, komunitas literasi tempat Zea bekerja mengadakan lokakarya di sebuah ruang perpustakaan kota. Di sana, ia bertemu seseorang yang menyodorkan formulir pendaftaran dengan tangan gemetar. “Namaku Kelaswara,” katanya. “Aku ingin menulis, tapi setiap mulai, aku takut menyinggung diriku sendiri.”
“Menulis tidak selalu tentang berani terhadap orang lain,” jawab Zea. “Kadang tentang berani kepada diri sendiri.”
Kelaswara menunduk, tertawa pendek, lalu duduk paling depan. Di sesi akhir, peserta diminta menulis “surat yang tidak harus dikirim.” Ruangan senyap. Dari sudut kaca, hujan memantul. Ada yang menulis untuk ayahnya yang sudah tiada; ada yang menulis untuk anaknya yang belum lahir; ada yang menulis untuk dirinya lima tahun lagi. Kertas-kertas itu dilipat, dimasukkan ke amplop, lalu disimpan di tas masing-masing. Tak ada yang mengunggah ke mana-mana. Tidak ada tepuk tangan. Hanya napas yang terasa lebih ringan.
Seusai acara, Retna menepuk bahu Zea. “Bagus,” katanya. “Kampanye seperti ini tak viral memang, tapi tumbuh.”
Zea tersenyum. Ia paham: tidak semua yang baik perlu terlihat. Ada kebaikan yang tugasnya hanya mengembalikan seseorang kepada dirinya.
.
Kota yang Melupakan Lalu Mengingat Kembali
Jakarta kadang tampak seperti mesin yang tidak pernah lelah: jam terus bergerak, proyek terus dibangunkan, reklame baru mengganti yang lama sebelum yang lama sempat menjadi akrab. Namun di sela-sela itu, Zea menemukan ruang-ruang kecil tempat manusia diam-diam menambal hidupnya: warung bubur pinggir jalan yang selalu hafal porsi pelanggan; masjid kecil di pelataran parkir yang lampunya temaram; taman kota di mana seorang bapak tua memberi makan kucing liar. Di tempat-tempat itulah, kota melupakan, lalu mengingat kembali.
Suatu malam, Zea turun di stasiun MRT yang berbeda dari biasanya. Ia berjalan kaki melewati deretan ruko yang sebagian tutup, sebagian bertahan. Di tikungan, ada studio foto kecil dengan papan kayu kusam. Di kaca, tertempel ijazah kursus fotografi jadul. Di dalam, lampu kuning menyala. Seorang lelaki memotret pasangan yang tersipu malu. Zea berhenti, tertarik oleh wajah fotografernya. Bukan Arka. Tentu bukan. Tapi cara lelaki itu menyetel fokus seperti seseorang yang menghormati momen—menyentuh dulu sebelum merekam.
Untuk sesaat, sesuatu dalam dada Zea bergerak. Lalu ia tertawa pelan pada dirinya sendiri. “Sabar,” katanya, entah pada siapa. “Kita tidak buru-buru.”
Ia melanjutkan langkah.
.
Pesan yang Tiba di Waktu yang Tepat
Beberapa pekan berselang, sebuah pesan singkat muncul di ponselnya, dari nomor yang tidak ia simpan. “Zea, ini Arka. Boleh bicara?” Zea menatap layar lama, seperti menatap hujan dari balik jendela. Ia menaruh ponsel, menuang air, lalu kembali duduk. Setelah hati tak tergesa, ia membuka pesan lagi.
“Boleh,” balasnya.
Arka menelpon. Suaranya lebih rendah dari yang Zea ingat. “Aku minta maaf,” katanya, tanpa pengantar. “Untuk caraku pergi. Untuk diamku.”
Zea mendengarkan. Ada jeda-jeda canggung. Arka bercerita singkat tentang kecemasannya, tentang proyek yang gagal, tentang caranya menghindar karena tak ingin terlihat kecil. “Aku pengecut,” katanya.
“Kalau kau mau jujur pada dirimu, itu sudah langkah besar,” jawab Zea. “Tapi kau tidak sedang bicara dengan hakim.”
“Lalu kau?” tanya Arka. “Bagaimana kabarmu?”
“Aku baik,” kata Zea, dan kali ini benar.
“Bisa bertemu?”
Zea menatap meja, menimbang. Di laci, ada amplop yang tidak jadi dikirim. Di dirinya, ada ruang yang baru dibereskan. “Aku rasa tidak perlu,” jawabnya akhirnya. “Tapi terima kasih sudah meminta maaf.”
Di ujung telepon, Arka diam. Kemudian ia menarik napas. “Kau benar. Jaga dirimu, Zea.”
“Kau juga,” kata Zea.
Mereka menutup telepon. Tidak ada yang berat tertinggal. Surat yang tidak pernah ia kirim sudah bekerja tanpa perlu dikirimkan.
.
Hati yang Memilih Tumbuh
Musim hujan belum usai ketika Zea mulai rutin berlari pagi di taman dekat rumah. Ia suka jam enam lewat sedikit: saat matahari masih malu-malu, dan udara membawa bau tanah basah. Kadang ia bertemu Jayeng—ya, barista itu—yang rupanya gemar memotret dedaunan dengan kamera butut. “Aku suka yang hijau-hijau,” kata Jayeng. “Hidupku terlalu cokelat kalau di kedai.”
Mereka pernah duduk lama di bangku taman, membahas hal-hal ringan: lagu yang tiba-tiba relevan, jemuran yang tak kunjung kering, resep sup sayur murah meriah. Jayeng bercerita tentang kakeknya yang selalu menyebut nama-nama dari cerita lama: Jayeng, Retna, Adaninggar, Kelaswara; tokoh-tokoh yang mencari, menunggu, berdebat, memahami. “Lucu ya,” kata Jayeng, “di kota yang sangat modern ini, nama-nama itu muncul lagi, tapi dengan pekerjaan biasa-biasa saja.”
“Biasa bukan berarti tidak penting,” sahut Zea. “Sering kali justru di yang biasa-biasa, hidup bertahan.”
Suatu pagi, Jayeng menyodorkan sesuatu: sebuah foto polaroid. Di dalamnya, ada punggung seorang perempuan yang sedang menulis di meja dekat jendela. “Aku motret ini diam-diam beberapa bulan lalu,” kata Jayeng kikuk. “Kau menatap kertas seperti orang yang sedang memegang dunia. Maaf ya, aku tidak minta izin. Aku simpan karena takut mengganggumu. Tapi kupikir, ini milikmu.”
Zea menatap polaroid itu. Bukan soal gambarnya. Soal momen ketika ia memutuskan menulis sebuah surat yang ia tahu tak akan ia kirim. Polaroid itu seperti cermin lain—yang kali ini tidak ia buat sendiri.
“Terima kasih,” kata Zea, tulus.
“Kalau suatu hari kau butuh model untuk difoto balik,” tanya Jayeng, “boleh aku minta tolong?”
Zea tertawa. “Kau kan suka yang hijau-hijau. Aku bukan daun.”
“Daun juga bernafas karena ada cahaya,” jawab Jayeng. “Manusia pun begitu.”
Mereka tertawa. Bukan tawa dua orang yang saling mengejar, melainkan dua orang yang sedang baik-baik saja dengan tempatnya masing-masing.
.
Surat Itu Tetap di Sana
Surat itu tidak pernah dikirim. Tapi Zea membacanya sesekali—bukan karena masih mencintai Arka, melainkan karena ia ingin terus mencintai dirinya sendiri. Ia ingin mengingat momen saat ia memilih tenang alih-alih membalas; saat ia memilih tumbuh alih-alih menuntut; saat ia menutup pintu tanpa mengunci jendela—sebab hidup selalu perlu udara segar.
Pada suatu malam yang sepi, listrik di rumah padam. Zea menyalakan lilin, lalu membuka laci, menarik amplop yang sudutnya sudah agak tumpul. Ia membukanya, membaca kembali. Di luar, kota mendesis karena gerimis. Di dalam, ia merasa ditemani oleh dirinya yang lain—yang pernah rapuh, tapi tidak menyerah.
Ia menambahkan satu kalimat di bagian bawah:
“Terima kasih sudah pulang tepat waktu, meski tidak membawa siapa-siapa selain dirimu sendiri.”
Lilin menyusut. Hujan berhenti. Jakarta tidur sebentar. Zea memejam, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mimpinya tidak diisi oleh wajah siapa pun selain dirinya berjalan di trotoar panjang, menghirup udara, menyeberang pada lampu hijau, tiba di seberang tanpa terburu-buru.
.
Hal-Hal yang Tinggal
Di meja nomor tujuh, suatu sore, seorang perempuan muda duduk memegang amplop kosong. Zea yang kebetulan lewat menatapnya dan memberi senyum. Perempuan itu membalas canggung. “Kak,” katanya, “menurutmu, lebih baik dikirim atau disimpan?”
Zea menatap amplop itu, lalu menatap mata perempuan itu. “Kau boleh mengirimnya,” jawab Zea, pelan, “tapi pastikan kau sudah mengirim surat yang sama ke dirimu lebih dulu.”
Perempuan itu mengangguk. Jayeng muncul membawa teh, meletakkannya tanpa bunyi. Di dinding, jam terus melangkah. Di luar, langit mendung. Di dalam, seseorang akan menulis. Dan kota akan terus menjadi panggung bagi mereka yang belajar pulang kepada dirinya.
Zea berjalan keluar, melintasi trotoar yang baru dipoles hujan, melewati kios majalah, penjual pisang goreng, dan seorang bocah yang tertawa dikejar air. Ia merogoh dompet, menyentuh foto lama yang tak pernah ia buang. Bukan untuk menghidupkan lagi, melainkan untuk mengucapkan terima kasih karena sudah pernah ada. Di kepalanya, tiga kalimat berbaris rapi seperti judul film:
Berhenti mengejar.
Rapikan dirimu.
Lalu berjalan lagi.
Dan ia pun berjalan.
.
.
.
Lanjut Baca Part 3: Saat Kita Tak Lagi Bicara
.
.
.
Jember, 4 Juni 2025
#CerpenIndonesia #CerpenKota #SuratUntukDiri #HealingLewatMenulis #NarasiFilmis #KompasMingguVibes #MenakMadura #EmotionalWriting