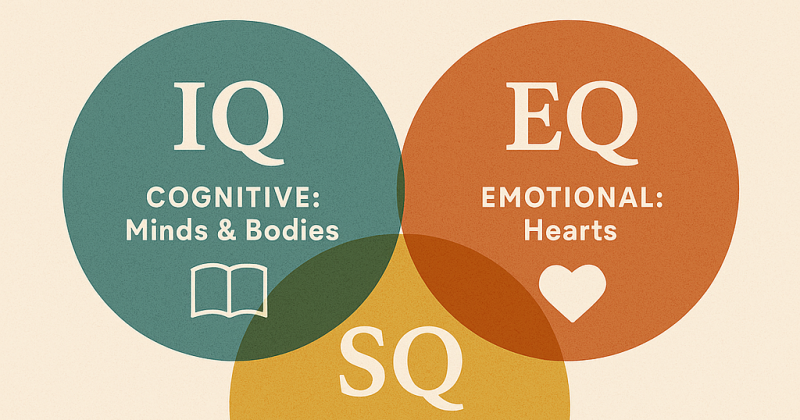Saat Semua Salah Bernama Istri
“Di balik foto keluarga sempurna yang kau lihat di media sosial, sering tersembunyi istri yang lelah menangis di kamar mandi dan suami yang lupa bagaimana cara pulang ke rumah.”
.
Foto yang Retak
Di feed Instagram, keluarga itu seperti potongan iklan yang jatuh dari langit.
Lingga—nama resminya Jaya Linggajati, sehari-hari dipanggil Jaya—baru saja masuk daftar 40 Under 40 majalah bisnis.
Lumpang—nama kecilnya Sora, julukan dari mendiang nenek yang gemar mendongeng kisah Menak—mantan marketing manager yang memilih fokus di rumah dan dunia digitalnya.
Dua anak mereka, Kayan dan Lara, selalu tampak rapi mengenakan seragam rancangan desainer lokal yang sedang naik daun.
Rumah tiga lantai di BSD itu sering jadi latar endorsement: dapur marmer dengan lampu gantung bundar, rak buku warna walnut, tangga minimalis menghadap jendela besar yang meminjamkan langit.
Tak satu pun dari 250 ribu pengikut Sora tahu retakan yang makin lebar.
Malam itu, seperti biasa, jam makan malam sudah lewat. Jam di dinding—hadiah pernikahan tahun ketiga—berdetik pelan. Jaya pulang lewat tengah malam, sisa aroma wine menempel di kerah jas.
“Maaf, meeting dadakan,” katanya. Tas ia lempar ke sofa, HP tetap menyalakan notifikasi.
Sora menahan napas. Bukan soal jam pulang. Bukan soal meeting.
Ini tentang rasa yang tak lagi bertaut, tentang rumah yang tak lagi terasa rumah.
Lampu gantung memantulkan wajah Sora di permukaan marmer: mata yang bengkak, bibir yang seperti menahan kalimat panjang namun menguap jadi “tidak apa.” Padahal ada banyak apa.
.
Saat Semua Salah Bernama Sora
Esok pagi, komentar baru masuk di postingan:
“Wah keluarga impian banget, Mbak.”
“Pengen deh jadi kayak Mbak, suami sukses, anak terurus.”
Sora membaca sambil tersenyum getir. Mereka tak tahu: anak-anak lebih sering ditemani Mbok Minah dan pengasuh bergantian; rumah rapi karena fotografer butuh latar, bukan karena hati tertata. Jaya dulu partner diskusi; kini ia lebih banyak bicara dalam angka—ROI, NPV, IRR—singkatan yang tak pernah memeluk.
Dan pada akhirnya, yang paling membuat dada sesak: di balik semua ini, Sora selalu jadi yang salah.
Anak mogok makan? “Ibu harusnya sabar ngajari.”
Anak tantrum? “Coba kalau ibu gak sibuk endorse.”
Rumah sedikit berantakan? “Katanya resign biar fokus, kok begini?”
Jaya pulang dengan kening berlipat? “Jangan bikin suasana makin gak enak.”
Ketika Sora kelelahan sampai lupa menyisir rambut, suara lain menambah luka:
“Lah, kamu aja gak bisa ngurus diri sendiri, gimana ngurus rumah?”
Sora memandangi wajahnya di cermin kamar mandi. Lampu white daylight menyusun jerawat bekas stres seperti rasi bintang yang ia tak hafal namanya. Air mengalir. Sunyi menebal.
“Perempuan bukan pabrik kesabaran. Ia manusia yang juga berhak disabari.”
.
Cinta yang Bergeser
Suatu malam di SCBD, bertahun lalu, saat Sora masih bekerja sebagai marketing manager, Jaya menggenggam tangannya di bawah lampu-lampu kota.
“Resign, Ra. Supaya kita punya quality time. Aku support. Kamu tinggal fokus rumah, konten, apa pun yang kamu suka,” kata Jaya.
Sora percaya. Ia melompat—meninggalkan rapat, laporan Q4, teater jam pulang malam—demi bayangan pagi berkumpul, siang bercerita, malam tertawa.
Setelah resign, dunianya mengecil. Bukan hanya ruang fisik, tetapi ruang batin.
Jaya makin sibuk. Kalau pun ada, percakapan mereka hanya seputar penutupan proyek, investor, properti baru.
Ketika Sora bilang lelah, Jaya menatapnya seperti menatap grafik yang tak sesuai target.
“Kamu tuh beruntung gak pusing uang. Aku kerja keras, kamu tinggal nikmatin,” kata Jaya sambil menghela.
Kalimat itu menabrak Sora seperti truk kontainer di tol JORR—terduga, tapi tetap mematahkan.
Di rumah berlantai tiga, Sora merasa jadi penumpang yang tidak pernah ditanya mau turun di mana.
“Rumah bukan sekadar alamat, ia adalah hak untuk merasa pulang.”
.
Suara yang Dipendam
Di grup arisan, Sora mulai jarang muncul. Kalau pun datang, ia sibuk mengaduk es kopi sampai esnya tinggal garis tipis di bibir gelas.
Di ruang-ruang daring, ia jadi pengamat. Setiap ingin mengeluh, ada suara menyambar: “Malu, ah. Udah enak hidupnya kok ngeluh.”
Sora mulai membaca artikel tentang pernikahan yang dingin, tentang pengabaian emosi yang tak memar tetapi mematikan. Ia temukan kata: emotional neglect.
Ia baru sadar, luka paling sepi adalah yang tidak diucapkan karena takut dianggap mengada-ada.
Malam-malam, Sora menangis sendirian di kamar mandi. Air shower menutupi suaranya. Dari balik pintu, Kayan kadang mengetuk, “Bu?”
Sora menjawab, “Iya, Nak,” seperti doa pendek.
“Ada tangis yang sengaja dinyalakan di bawah shower, agar dunia mengira kita hanya mandi.”
.
Titik Balik
Ulang tahun pernikahan ke-9. Sora membeli kue kecil stroberi. Lilin dua—satu untuk ia, satu untuk Jaya—ditempel serong seperti doa yang miring. Di meja makan, serbet katun disetrika rapi. Lara menulis kartu dengan huruf-huruf menari: Selamat ulang tahun, Ayah Ibu. Semoga sayang terus.
Jaya tak pulang. Jam 23.45, kue mulai meleleh. Sora duduk di ujung meja; sendoknya memantulkan tatapannya sendiri.
Pukul 02.03. Pintu berderit. Aroma wine menyelinap lebih dulu. Jaya berdiri di ambang, topi basecap menutup mata.
“Kamu tahu jam berapa?” Sora bertanya tanpa nada.
“Jangan mulai. Meeting tadi—”
“Meeting yang butuh bar?”
Jaya menarik napas. “Klien pengin di sana.”
Sora menunjuk kue yang mengantuk di meja. “Hari ini ulang tahun pernikahan kita.”
Sunyi sepadat karpet tebal.
“Aku capek, Jaya. Aku gak mau lagi jadi boneka di rumah ini. Aku istri, bukan bayangan di sudut ruangan,” kata Sora, suara bergetar setipis kaca.
Jaya terdiam lama, seperti baru sadar rumah itu punya suara lain selain notifikasi.
Esoknya, atas desakan adik Sora—Maya, yang orang rumah memanggilnya Umarmaya karena selalu jadi penengah—mereka ke konselor pernikahan di bilangan Kemang. Ruangan itu wangi kayu dan lavender, ada lukisan perempuan menatap laut.
Konselor—orangnya dipanggil Tal, singkatan dari Maktal, nama panggung di komunitas psikologi seni—mendengar cerita mereka dengan telinga yang seperti teluk.
“Mas Jaya,” kata Tal pelan, “ketika uang jadi indikator utama, pasangan sering berubah jadi departemen: satu produksi, satu pemeliharaan. Cinta tak lagi ruang, melainkan divisi.
Kalau suami miskin, istri dianggap beban. Saat suami kaya, istri dianggap menumpang. Maka, jangan ukur harga diri lewat harta, ukur dengan penghargaan yang tak lekang waktu.”
Jaya menunduk. Kata-kata itu seperti menukar sandi di kepalanya.
Tal menatap Sora. “Mbak Sora, lelahmu valid. Boleh marah. Boleh letih. Tapi izinkan lelahmu bicara tanpa menyalahkan dirimu sendiri.”
“Cinta adalah kerja dua orang yang saling menjaga martabat masing-masing.”
.
Mencari Ruang Baru
Perubahan tidak meledak. Ia menetes.
Jaya mulai pulang lebih cepat pada Selasa dan Kamis. Ia belajar menulis pesan “Terima kasih,” bukan hanya “Kamu harus.”
Malam-malam, ia mematikan HP sampai Kayan tertidur. Ia belajar kembali menyimak cerita Lara tentang lomba menggambar, bukan sekadar bertanya “Juara berapa?”
Ada jeda canggung. Ada diam panjang. Ada luka yang belum sembuh.
Terkadang Jaya tergelincir, pulang telat lagi karena pitch deck molor; Terkadang Sora tersulut oleh piring yang tak dirapikan.
Mereka kembali ke Tal. Tidak setiap minggu, tapi cukup untuk mengingat arah.
Jaya mengajak Sora makan malam di warung madura pinggir jalan—mengingatkan pada cerita nenek yang sering berkumandang di masa kecil Sora tentang Kelaswara dan Jayengrana; tentang perjalanan panjang yang tak melulu gagah, kadang hanya soal duduk berdampingan sambil menunggu hujan reda.
“Kalau kita bukan raja dan permaisuri, kita cukup jadi Jaya dan Sora yang pulang,” kata Jaya, separuh bercanda.
Sora tertawa pelan. Sudah lama tawa itu tidak singgah di bibirnya.
.
Kota yang Terus Berlari
Kota tetap berlari dengan sepatu kets.
Di jalan layang non-tol, spanduk properti baru berderet: Rumah Berkelas, Hidup Bermakna. Di halte Transjakarta, iklan skincare menyala: Kulit Glowing, Hati Tenang.
Sora tahu kota akan selalu menawar definisi bahagia. Ia menulis di catatan HP: bahagia adalah tidak lagi takut pulang.
Suatu sore, Sora membuat konten baru. Bukan sekadar tata ruang rumah, tetapi tata rasa. Ia memotret tangan Jaya yang memegang piring kotor dan caption: Tidak mewah, tapi ini romantis. Karena cinta adalah hal-hal yang memudahkan sehari-hari.
DM-nya meledak.
“Mbak, aku juga ngalamin.”
“Mbak, suami saya seperti Mas Jaya dulu.”
“Mbak, terima kasih udah jujur.”
Sora menatap layar yang berkilat seperti permukaan air. Ia tak sendirian.
Di balik jutaan rumah dengan pintu otomatis, ada istri yang menangis di kamar mandi. Ada perempuan yang dipersempit lalu disuruh tersenyum. Ada “maaf” yang dipakai seperti perban, padahal lukanya perlu dijahit.
“Jangan biarkan rasa bersalah yang bukan milikmu menagih cicilan dari jiwamu.”
.
Benda-Benda yang Mengingat
Di rumah itu, ada benda-benda yang mengingat.
Kursi rotan warisan Ibu Sora, yang dulu jadi tempat menyusui Kayan, kini retaknya menyimpan napas bayi dan gelisah ibu muda.
Gelas kertas bekas kopi larut lembur Jaya tersembunyi di balik komputer, mengingatkan pada malam-malam panjang yang membesarkan rekening dan mengecilkan ruang bertemu.
Kartu kecil bertuliskan Selamat ulang tahun pernikahan ke-9 diselipkan Sora di balik buku—disana, tinta Lara dan Kayan tidak luntur.
Malam lain, Jaya berdiri lama di depan kaca. Ia mengingat ayahnya yang keras, kata-kata yang dingin, meja makan yang penuh piring tapi miskin percakapan.
“Aku tidak mau jadi suara ayah,” gumamnya.
Ia memeluk Sora dari belakang—pelan, hati-hati, seperti memeluk kucing yang pernah takut air. “Maaf,” katanya. Tidak untuk menutup percakapan, tetapi untuk membuka.
.
Kata yang Tumbuh
Perkataan tumbuh seperti rambat.
“Terima kasih sudah nunggu,” kata Jaya.
“Aku lelah, boleh istirahat?” kata Sora.
“Aku dengar,” kata Jaya.
“Aku percaya kamu berusaha,” kata Sora.
Ada hari-hari buruk—Sora kembali menangis di kamar mandi; ada hari-hari baik—Jaya menjemput anak-anak tanpa diminta.
Tal mengirim pesan: Setiap hubungan adalah dua orang yang mengakui manusia di depan mereka. Bukan mitos, bukan ekspektasi, bukan cermin orang tua masa lalu. Hanya manusia yang sedang belajar.
Sora menempel satu kalimat di kulkas, dengan magnet berbentuk bintang:
“Cinta bukan siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling berani membenahi.”
.
Yang Tersisa dari Pesta
Undangan pernikahan sepupu Sora membawa mereka ke gedung di Senayan. Lampu-lampu gantung, bunga mawar, pelaminan bak kerajaan.
Di foto booth, Jaya memeluk pundak Sora. “Kita dulu begini,” katanya.
“Dulu kita percaya foto adalah kesimpulan,” jawab Sora. “Padahal ia hanya cuplikan—kadang baik, kadang bohong.”
Mereka pulang naik taksi online. Sopirnya memutar lagu dangdut koplo yang sedang viral di TikTok.
“Mas mbak pengantin juga?” tanya sopir.
“Bukan,” jawab Jaya. “Kami tamu yang sedang belajar jadi rumah.”
Sopir tertawa. “Semoga rumahnya awet ya.”
Jaya menatap Sora. “Amin.”
.
Pulang
Suatu Sabtu sore, hujan turun rapi seperti garis-garis di buku tulis.
Di dapur, Sora memasak rawon dari resep Ibu. Jaya mengiris bawang merah, bukan dalam pose foto, melainkan betulan. Kayan menyiapkan piring; Lara menyusun sendok.
Radio penyiar independen memutar talkshow tentang kesehatan mental di keluarga urban.
Mereka makan. Ada tawa kecil ketika Kayan salah mengucap “kluwek” jadi “kluwuk”. Ada momen ketika Jaya menatap Sora lama-lama, seperti mengeja wajah yang sudah lama tidak dibaca.
“Terima kasih masak,” kata Jaya.
“Terima kasih pulang,” jawab Sora.
Malamnya, Sora menulis di Instagram—tanpa filter yang memutihkan kulit, tanpa sudut kamera yang menipiskan perut:
Pernikahan bukan soal pesta dan rumah indah. Ia ruang untuk terus belajar menghargai. Aku masih belajar. Kami masih belajar.
DM kembali penuh:
“Mbak, terima kasih sudah jujur.”
“Mas, ajarin suami saya baca caption ini dong,” disertai emoji tawa menangis.
Sora tersenyum. Ia membalas beberapa, menandai sebagian. Ia lalu meletakkan ponsel.
Di luar, sisa hujan samar-samar menabur bau tanah. Di dalam, anak-anak telah tertidur.
Jaya duduk di ujung ranjang. “Besok, kita ke taman kota?”
Sora mengangguk. “Besok, kita ulang cara pulang.”
“Pernikahan yang sehat bukan yang tak retak, melainkan yang berani mengakui retak dan menambalnya bersama.”
.
Nama-Nama yang Diingat Kota
Di dinding kamar kerja kecil Sora, ada foto hitam putih neneknya: perempuan dengan kain panjang dan senyum tak tergesa. Nenek yang mengajarinya nama-nama dari kisah Menak: Jayengrana yang gagah, Kelaswara yang setia, Umarmaya yang bijak, Umarmadi yang teguh, Maktal yang keras tapi akhirnya lunak. Bukan untuk menempelkan gelar, melainkan untuk mengingat manusia di balik cerita.
Sora menulis catatan terakhir di malam-malam yang ingin cepat berlalu:
Jika kisah lama bisa menghibur, biarlah namanya menuntun. Di kota modern ini, kita tetap manusia yang mencari cara pulang ke satu sama lain.
Ia menutup buku. Mematikan lampu. Menarik selimut.
Di gelap yang tidak lagi mengancam, Jaya berbisik, “Selamat tidur.”
Sora membalas, “Selamat pulang.”
Dan kota, dengan lampu-lampu yang tak pernah padam, akhirnya mengizinkan mereka terlelap—bukan sebagai pemenang, bukan sebagai korban—melainkan sebagai dua orang yang bersedia terus tumbuh di bawah atap yang sama.
.
.
.
Jember, 10 Juni 2025
.
.
#CerpenMinggu #CerpenUrban #RumahTangga #EmotionalNeglect #Perempuan #KesehatanMental #Jakarta #BSD #Cinta #PulihBersama #KompasStyle #Storytelling #NamakuBrandku
.
Kutipan-kutipan dari cerita
-
“Perempuan bukan pabrik kesabaran. Ia manusia yang juga berhak disabari.”
-
“Rumah bukan sekadar alamat, ia adalah hak untuk merasa pulang.”
-
“Ada tangis yang sengaja dinyalakan di bawah shower, agar dunia mengira kita hanya mandi.”
-
“Jangan biarkan rasa bersalah yang bukan milikmu menagih cicilan dari jiwamu.”
-
“Cinta bukan siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling berani membenahi.”
-
“Pernikahan yang sehat bukan yang tak retak, melainkan yang berani mengakui retak dan menambalnya bersama.”