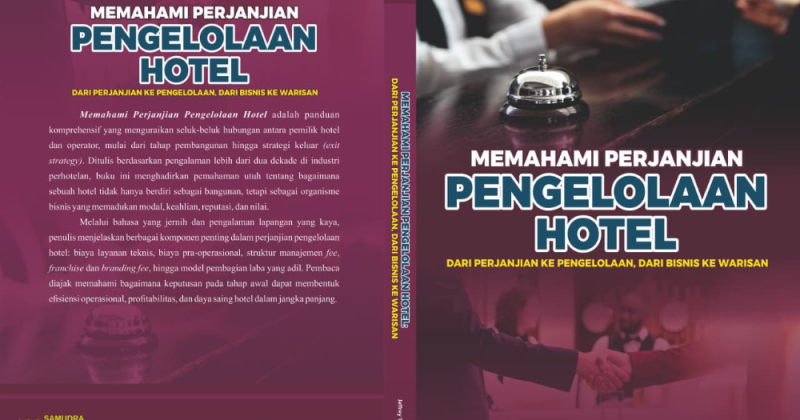Di Balik Punggung Waktu
“Jangan cari tepuk tangan; cari detak jantung yang tenang. Hidup bukan panggung, melainkan perjalanan pulang ke diri sendiri.”
.
“Hidup itu seperti meja kerja yang tak pernah rapi—ada beban yang bisa dibersihkan, ada yang harus diselesaikan, dan ada yang harus diikhlaskan. Tapi yang membuatmu tetap kuat adalah saat kamu berhenti mengeluh dan mulai menyentuh hati orang lain.”
Suara notifikasi pagi itu memecah sunyi apartemen lantai delapan belas—menghadap arah Sudirman yang sudah menyalakan denyut sejak subuh.
Drrt. Ting. Ping.
Dayinta—dipanggil Dayin—mengeser kursor ke ikon email: tiga puluh dua belum dibuka. Enam file revisi. Dua belas tab menganga. Grup WhatsApp kantor bersamaan riuh oleh status ambigu atasan: “Kinerja bukan tentang sibuk, tapi hasil.”
Ia menyeruput kopi dingin, menatap sticky notes warna-warni: “Deck jam 10”, “PAID ADS—approval”, “Retargeting: pending KPI”. Tak satu pun memberi rasa hidup. Semuanya seperti film hitam-putih yang tak lagi menaruh suara.
Di balik kaca, langit Jakarta menipiskan oranye, membelah gedung-gedung setinggi ambisi. Ada helikopter kecil melintas, ada lampu-lampu lift bergerak. Dunia sibuk. Hari ramai. Hatinya… kosong.
.
Dayinta Kusumawardhani, 34 tahun, project officer di perusahaan teknologi digital campaign—CV-nya bersih, portofolionya membanggakan, results-driven katanya. Di kantor, ia “si pemadam kebakaran”. Di keluarga, anak sulung yang bisa diandalkan. Di dalam diri, anak kecil yang tak menuntut apa pun selain pelukan, tanpa syarat prestasi.
Ia pernah berbisik di balkon yang berangin malam: “Kalau aku tiba-tiba hilang, siapa yang sungguh-sungguh mencari?” Pertanyaan itu melayang, menyentuh bintang, lalu jatuh lagi ke lantai beton. Tidak ada jawaban. Hanya lampu kota yang berkedip seperti mata yang menahan kantuk.
Hari itu, manajernya—Sarka—meminta lembur. Bukan sekali dua. Namun kali ini tubuhnya menolak. Bukan semata capek, melainkan kosong. Seperti seseorang yang pulang, menemukan rumahnya ada, tapi jiwanya entah di mana.
Ia memandang cermin di toilet kantor; lampu putih menyayat garis-garis halus di sudut mata. “Dayin, kamu masih ada di situ?” tanyanya, pelan. Yang kembali hanya bayangan lelah.
Ponsel bergetar. Panggilan tak terjawab dari “Ibu Rumah”. Lalu sebuah pesan pendek, terbuka seperti luka:
“Dayin, ayah masuk RS. Serangan jantung. ICU. Pulang, ya, Nak.”
Dunia ambruk dalam sekejap. Semua rapat mendadak tak penting. KPI menjadi huruf-huruf dingin. Ia memesan tiket kereta malam tanpa izin, tanpa menoleh, tanpa final check. Jakarta—Stasiun Tugu—rumah. Segalanya menipis menjadi satu garis tujuan: Ayah.
.
Rumah kecil itu menyambut dengan bau tanah basah; hujan malam menyisakan daun jambu yang memantulkan cahaya. Di ICU, ia menggenggam tangan ayah—kulitnya pucat, napasnya didorong selang, monitor berdenyut seperti metronom kesabaran.
“Aku Dayin, Pak,” katanya, suaranya pecah.
Mata ayahnya perlahan terbuka, menyusupkan cahaya yang tak ada di lampu neon. “Kamu… kurusan, Nak.”
Dayin menangis. Bukan karena takut kehilangan, melainkan karena rasa bersalah. Tiba-tiba, semua huruf “target” menjadi tumpukan kertas yang terbakar; semua rapat terasa seperti menginjak lantai kosong. Siapa yang ia buktikan, selama ini?
Malam-malam berikutnya, ia tidur di kursi tunggu—bahunya merapat pada dingin AC rumah sakit. Sesekali menulis di buku kecil: satu kalimat, satu nafas. “Kalau hidup adalah meja kerja, aku ingin menata ulang laci yang berisi ketakutanku.” Hening membuatnya berani mengakui: ada bagian dari dirinya yang ia tinggalkan terlalu lama.
Ayah akhirnya diizinkan pulang. Dayin memutuskan tinggal lebih lama. Pagi-pagi ia menyapu halaman, mencuci baju hingga punggung gemetar, menjemur pakaian yang berderet seperti doa. Siang menanam cabai bersama ibu, memeriksa ujung-ujung tunas yang rewel. Sore, beranda menjadi surau kecil tempat pembicaraan pelan.
“Hidup ini bukan tentang cepat-cepat sampai,” ujar ayah, menyeruput teh jahe. “Tapi tentang siapa yang masih kita genggam tangannya di tengah jalan.”
Kata-kata itu menetes pelan, seperti hujan kecil di sela kemarau panjang di hati Dayin. Ia menoleh pada ibu—yang mengangguk sambil tersenyum samar. Dunia, untuk pertama kali dalam waktu lama, terasa kembali berwarna.
Malam, Dayin menulis. Bukan laporan. Ia menulis kisah kecil: kehilangan, sunyi, sembuh. Ia merekam suaranya membaca satu per satu halaman itu, memotong napas saat perlu, memberi ruang pada jeda. Menyimpannya ke sebuah kanal pada platform audio. Ia menamai podcast itu “Hening Penuh Makna.” Ia tidak memasang target pendengar; ia hanya menaruh suara untuk beresonansi dengan suara lain di luar sana.
.
Dua bulan kemudian, ia pulang ke Jakarta. Kali ini bukan untuk berkejaran. Ia menatap gedung-gedung itu seperti menatap sobat lama yang tak perlu lagi dikalahkan. Begitu masuk kantor, tembok putih dingin menyambutnya. Sarka mengangkat alis, menyelipkan geram di balik formalitas.
“Kamu cuti tanpa izin dua bulan. Ada proyek terbengkalai.”
“Ada yang lebih penting,” kata Dayin. Ia tidak berteriak. Sederhana, seperti orang menyebutkan nama jalan. “Hidup.”
Sarka tertawa hambar. “Di sini kita profesional. Kalau tidak sanggup, kamu tahu pintu keluar.”
Dayin mengangguk. “Aku tahu. Dan aku memilih keluar—dengan hormat.”
Kartu akses diletakkan di meja. Semua sticker KPI dicabut satu-satu dari laptopnya. Ia memasukkan mouse ke tas, menepuk bersih permukaan meja. “Terima kasih, meja,” bisiknya. “Terima kasih sudah menampung kegelisahan. Aku pulang.”
Jakarta, tanpa gaji bulanan, terasa seperti labirin baru. Ia mengambil proyek lepas: menulis naskah copy untuk kedai kopi, memandu workshop kecil brand storytelling di co-working space Kuningan, mengedit video untuk UMKM di Rawamangun. Pendapatan tak setebal dulu, tapi harinya lebih bernapas.
Pada malam-malam sepi, ponsel bergetar oleh pesan dari pendengar Hening Penuh Makna.
“Mbak, suaramu menumbuhkan keberanian untuk tidur tanpa menangis.”
“Aku berhenti marah hari ini. Terima kasih, Mbak Dayin.”
Satu pesan membuatnya terpaku lama: “Aku batal melompat dari balkon kos. Aku memilih mendengarkan lagi episode ‘Mengikat Diri dengan Ikhlas’. Terima kasih, Mbak, karena meminjamkan tenangmu.” Dayin menutup mata. Di tengah sunyi, ia menatap punggung waktu—yang dulu ia kejar, kini ia peluk.
Suatu siang, di coffee shop kecil di Setiabudi, ia bertemu Retna—teman lama yang dulu satu organisasi sosial dengannya. Retna menatap Dayin seperti seseorang yang menemukan foto lawas dan menyimpannya di dompet.
“Kamu berubah,” kata Retna.
“Lebih ringan,” jawab Dayin.
Retna menghela napas. “Di grup itu, Umar lagi berkoar—katanya kamu dulu memanfaatkan organisasi untuk citra kantormu.”
Nama itu—Umar—memantul di kepala Dayin. Umar. Nama yang ia kenal sejak dulu: pandai berbicara, tajam berargumen, suka memimpin tanpa benar-benar memeluk. Di kisah-kisah lama yang diceritakan kakek tentang Menak Madura, Umar Maya adalah tokoh gagah yang sering salah langkah karena merasa paling benar. Kakek selalu menutup kisah itu dengan kalimat, “Kebenaran tanpa rendah hati hanyalah panggung.” Dayin tersenyum—panggung memang sering menyilaukan.
“Biar saja,” kata Dayin. “Kalau pun citra itu terjaga, mestinya bukan karena aku. Karena kita sungguh-sungguh membantu.”
Retna memandang lama. “Kepercayaan itu seperti mata uang lama; di pasar yang ribut nilainya jatuh duluan.”
Dayin mengangguk. “Tapi hati yang tenang tak mengenal inflasi.”
Mereka tertawa kecil. Jakarta sore itu seperti mengizinkan sejenak dua perempuan untuk berhenti berlomba.
.
Di sebuah co-working space di Kuningan, Dayin memandu kelas “Narasi untuk UMKM”. Di baris depan, duduk seorang pria berkacamata, wajahnya teduh, memperkenalkan diri sebagai Jayeng—freelance fotografer yang sedang belajar merangkai cerita. Di sebelahnya, Mardi, satpam kantor yang mendaftar diam-diam karena ingin menulis pengalaman jaga malamnya. Nama-nama itu akrab, seperti potongan nyala dari kisah lama—Jayengrana, Umarmadi—yang dipendekkan oleh kota agar muat di lanyard.
“Kalian tak perlu kalimat cantik,” ujar Dayin saat kelas usai. “Kalian butuh keberanian untuk jujur.”
Jayeng mendekat, menunjukkan foto-foto trotoar basah, lampu merah yang dipantulkan genangan, jemari penjual cilok yang kapalan. “Saya ingin orang bisa merasakan dingin dari foto-foto ini.”
“Dingin yang tak membuat beku, ya?” canda Dayin.
“Dingin yang mengingatkan untuk pulang,” Jayeng membalas.
Mardi tertawa kecil, memeluk buku catatan. “Saya mau menulis tentang suara lift yang sendirian. Saya kira, hanya saya yang mendengar.”
“Kamu tidak sendirian,” kata Dayin. “Kadang, lift pun butuh teman.”
Mereka tertawa. Untuk pertama kali, Dayin merasa kelas itu bukan tentang content, melainkan tentang hati-hati yang ingin diizinkan bicara.
.
Sebuah malam, Retna mengirim pesan: “Ada pertemuan organisasi. Datang, ya? Biar sekaligus jawab gosip.”
Dayin menimbang. Ia tidak ingin kembali ke gelanggang yang memutar retorika. Tapi menolak berarti membiarkan suaranya didefinisikan oleh orang lain. Ia memilih datang—bukan untuk membela diri, melainkan untuk menyapa.
Ruang rapat itu berpendingin terlalu dingin. Poster kegiatan lama masih ditempel, warnanya pudar. Umar berdiri, berpidato tentang transparansi. Kata-kata meluncur lancar, penuh istilah, tapi kosong di pelukan. Ketika giliran berbicara, Dayin melangkah seperti orang yang masuk ke ruang tamu sendiri—tenang.
“Aku tak lagi bekerja di kantor lama,” katanya. “Kalau dulu ada yang terlihat seperti memanfaatkan organisasi untuk citra, aku minta maaf. Tapi aku tahu kami bekerja—bukan untuk citra, melainkan untuk manusia. Dan hari-hari ini aku belajar, citra paling jujur adalah cara kita memegang tangan orang lain saat lemah. Boleh aku cerita sebentar?”
Mata orang-orang menatap. Dayin bercerita tentang ayah, kursi tunggu rumah sakit, cabai yang ditanam, teh jahe, podcast yang menyelamatkan satu balkon kos-kosan pada satu malam. Rapat itu berubah menjadi ruang dengar.
Seorang ibu menangis. Seorang remaja menghapus air mata dengan punggung tangan. Umar menatap meja. Di sudut, Retna mengangguk pelan.
“Hidup ini bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling sabar menunggu orang lain selesai ketakutan.”
Ruang rapat yang biasanya menutup pertemuan dengan tepuk tangan kini menutupnya dengan hening panjang—jenis hening yang lebih fasih daripada pidato mana pun.
.
Minggu berikutnya, Dayin mendapat undangan berbagi di sebuah community space di Tebet. Tema: “Di Balik Punggung Waktu—Memilih Tenang di Kota yang Selalu Berlari.” Ia menyiapkan slide sederhana: foto balkon, kursi tunggu RS, halaman dengan jemuran, secangkir teh yang mengepul.
Sebelum naik panggung, ponsel bergetar—pesan dari Sarka.
“Dengar-dengar kamu ngomongin mental health. Ingat, hidup ini kejam. Tenang itu ilusi. Uang tetap nomor satu.”
Dayin menatap layar itu lama. Jemarinya menulis: “Tenang bukan ilusi. Tenang adalah otot yang dilatih. Uang penting, manusia lebih penting. Semoga kamu bahagia, Sar.” Ia tekan send, lalu mematikan ponsel—bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memeluk fokus.
Di baris kedua, Dayin melihat Jayeng mengangkat kamera. Mardi berada di ujung, senyumnya tanggung. Retna duduk paling belakang, tangan di dada, seolah menahan sesuatu.
Dayin membuka dengan kalimat yang tak ia hafal, tapi sepertinya sudah lama menunggu bibirnya: “Kita tumbuh di kota yang mengajarkan bersuara lantang. Tapi sering lupa—yang tak kalah penting adalah kemampuan mendengar bisik paling samar di dalam dada.”
Ia bercerita. Tentang deadline yang meremas leher. Tentang meja kerja yang tak pernah rapi. Tentang ayah yang berkata tangan siapa yang kita genggam lebih penting daripada garis finish. Tentang podcast yang membuat orang membatalkan lompatan. Tentang gosip yang dibiarkan tumbang oleh kebenaran yang berjalan pelan. Tentang kebaikan yang tak perlu lampu panggung.
Ketika sesi tanya jawab, seorang pemuda mengangkat tangan. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi mata. “Mbak… aku Umar.”
Ruangan spontan menahan napas.
“Aku bukan Umar yang itu,” pria itu buru-buru menambahkan, sedikit gugup. “Namaku hanya Umar. Aku kerja di bagian customer service—tugasnya mendengar marah-marah orang. Aku capek. Aku tadi datang untuk nyari alasan berhenti. Tapi pas Mbak cerita, aku pengin bertahan… bukan buat perusahaan, tapi buat diriku. Biar suatu hari aku bisa bilang: aku pernah menenangkan orang lain tanpa kehilangan diriku.”
Dayin tersenyum. “Kamu tidak sendiri.”
Di belakang, Retna menoleh keluar jendela kaca yang dihujani rintik. Jakarta seperti menurunkan volume untuk beberapa menit.
.
Malam itu, saat pulang, hujan menutup aspal dengan rahasia kecilnya. Dayin menyeberang di depan halte TransJakarta. Lampu merah mengembun di kamera Jayeng—ia memotret dari sisi lain jalan, mengangkat tangan memberi isyarat. Mardi menutup gerbang community space; ia melambaikan buku catatan, seolah mengacungkan bendera kecil di ujung lomba yang tidak perlu lagi diikuti.
Di apartemen, Dayin menggambar meja kerja di buku tulisnya. Di dalamnya ia menggambar tiga laci. Di laci pertama, ia menulis: “Bersihkan.” Di laci kedua: “Selesaikan.” Di laci ketiga: “Ikhlaskan.” Ia menutup bukunya rapat-rapat—bukan untuk mengakhiri, melainkan untuk mengawali.
Ponselnya berbunyi pelan—pesan suara dari Ayah.
“Nak, ayah tak pandai berpanjang kata. Tapi hidup ayah seperti sawah; yang paling indah bukan panennya, melainkan saat tanah basah dipijak keluarga sendiri. Teruslah pulang ke dirimu.”
Air mata Dayin jatuh, menimpa gambar meja. Tinta melebar, membentuk sungai kecil yang mengalir ke pinggir halaman.
Ia membuka jendela. Suara kota masuk, pelan. Jakarta, untuk pertama kali sejak lama, terdengar seperti ibu yang meninabobokan anaknya. Dayin mematikan lampu, mengizinkan gelap memeluknya, lalu tidur—tanpa mimpi buruk.
.
Pagi-pagi ia memutuskan rekaman episode baru. Mikrofon kecil, lampu meja, secangkir teh. Ia menekan tombol record.
“Selamat pagi, teman-teman heningku. Hari ini kita bicara tentang punggung waktu—bagian dari hari yang tak pernah kita lihat karena kita selalu berjalan ke depan. Kalau sempat, tolehkan kepala. Di belakang sana, ada jejak yang perlu dipeluk, ada luka yang ternyata cuma butuh diberi nama, ada diri yang menunggu diajak pulang…”
Ia berhenti sejenak, menarik napas.
“Dan kalau kalian sedang berdiri di tepi, ingat: ‘Jangan cari tepuk tangan; cari detak jantung yang tenang.’ Tak ada yang perlu kalian buktikan hari ini, selain bahwa kalian masih di sini—bernapas, dan pelan-pelan berani jujur.”
Send.
Episode itu mengalir ke kota, ke kos-kosan sempit, ke ruang jaga malam, ke ponsel retak, ke telinga yang nyaris menyerah. Menyusuri gang-gang yang tak tersentuh baliho besar. Menyentuh, lalu tinggal. Bukan gemuruh. Melainkan pelukan kecil.
.
Beberapa bulan lewat. Di sebuah pagi cerah, Dayin berdiri di balkon, menatap langit yang mengelupas birunya. Ia teringat awal kisah—kopi dingin, notifikasi, sticky notes. Ia tak benci masa lalu; ia menaruhnya rapi di laci ketiga: Ikhlaskan. Di meja barunya, tak ada lagi lomba, tak ada lagi panggung, tak ada lagi rasa perlu mengungguli siapa pun. Ada kerja yang manusiawi. Ada uang yang cukup. Ada waktu untuk menjenguk ayah. Ada kelas kecil bersama Jayeng dan Mardi; ada Retna yang kadang datang membawa roti pisang dan kabar-kabar kecil yang hangat.
Di bawah sana, Jakarta tetap berlari. Tak apa. Dayin sudah menemukan kecepatan hatinya.
Ia berdiri, menggenggam gagang pintu, melangkah ke ruang kerja—yang kini tak selalu rapi, tapi selalu jujur. Di depan mikrofon, sebelum merekam, ia menulis satu kalimat dan menaruhnya di atas meja:
“Kadang, kita baru benar-benar hidup saat berhenti berlomba dan mulai mendengarkan napas sendiri.”
Dayin tersenyum. Ia menyentuh kertas itu—bukan untuk menghafal, melainkan untuk mengingat. Lalu ia menekan tombol record.
Suara pertama yang keluar bukan kata, melainkan hembusan pelan. Seperti orang yang baru saja tiba di rumah, melepas sepatu, mengucap: “Terima kasih, sudah sampai.”
Dan waktu, untuk sekali ini, menoleh dari punggungnya, tersenyum—sebelum terus berjalan.
.
.
.
Jember 18 Juni 2025
.
.
#Cerpen #KompasMingguVibes #KotaDanHening #SelfHealing #Jakarta #NarasiFilmis #MenakMadura #PodcastHening #KisahKeluarga #LiterasiEmosional
.
Kutipan-kutipan dari cerita
-
“Hidup ini bukan tentang cepat-cepat sampai, tapi tentang siapa yang masih kita genggam tangannya di tengah jalan.”
-
“Kepercayaan itu seperti mata uang lama; di pasar yang ribut nilainya jatuh duluan.”
-
“Tenang bukan ilusi. Tenang adalah otot yang dilatih.”
-
“Citra paling jujur adalah cara kita memegang tangan orang lain saat lemah.”
-
“Jangan cari tepuk tangan; cari detak jantung yang tenang.”