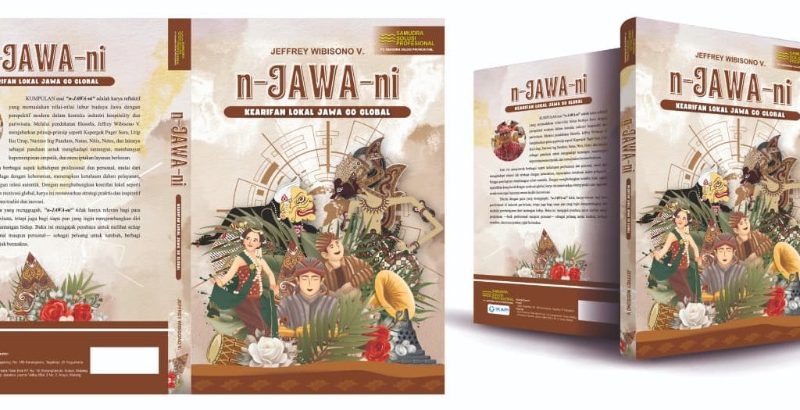Di Balik Wajah yang Kita Tunjukkan
“Setiap orang punya cerita yang tak kita tahu. Kadang di balik tawa ada air mata, di balik amarah ada luka yang lama menganga.”
.
Kota ini selalu menyala, bahkan ketika hujan memadamkan sebagian lampu jalan. Sirine memantul di genangan, menyalakan garis-garis cahaya yang patah. Malam menyiapkan panggungnya: selapis uap dari aspal basah, aroma mi instan dari warung tenda, percakapan yang dipotong klakson. Dan di antara semua itu, Alun berjalan cepat sambil memeluk tas ransel, menjaga laptop dari cipratan air, menjaga hatinya dari apa pun yang tak semestinya jatuh malam itu.
Namanya Alun. Dua puluh sembilan tahun. Desainer grafis lepas yang tahu persis kapan harus memasang senyum untuk klien, kapan harus mengunggah foto kopi cantik dan kucing Persia berbulu putih miliknya, yang diberi nama Purnama. Dari layar ponsel, hidupnya terlihat rapi: portofolio bersih, testimoni menggembirakan, dan undangan komunitas kreatif yang tak pernah sepi. Namun setiap malam, ketika notifikasi padam dan kucingnya tidur menyamping seperti sabit, ia duduk menatap tembok putih dengan pertanyaan yang selalu sama: kenapa semua ini terasa kosong?
Sunyi bisa menjadi kota dalam kota—tersendiri, utuh, hanya dihuni satu orang.
.
Sabtu sore itu, komunitas kreatif berkumpul di sebuah ruko tiga lantai di sudut kota. Di lantai dua, lampu gantung bergaya industrial memantulkan kilau pada cangkir-cangkir kertas. Musik jazz merambat pelan, seperti seseorang yang masuk ruangan tanpa ingin mengganggu. Alun datang terlambat. Ia merapikan rambutnya, menyusuri poster-poster risograph di dinding, merasakan detak ruangan yang terlalu antusias untuk seorang yang tengah bernegosiasi dengan sepinya sendiri.
Di sudut ruangan ada seorang lelaki, sekitar awal tiga puluhan, duduk menyendiri. Tidak sibuk merekam, tidak buru-buru menyapa. Kopinya dibiarkan mendingin, ia hanya memerhatikannya seperti memerhatikan hujan dari balik jendela. Ketika mata mereka beradu, hanya sedetik, sesuatu yang lama dan tertahan dalam dada Alun seperti disentuh.
“Aku suka pantai,” kata Alun kemudian, entah kepada siapa, entah kenapa. Kalimat itu lolos begitu saja saat sesi diskusi berakhir dan semua orang bergerak, bertukar kartu nama dan rencana janji temu.
Lelaki itu menoleh, senyum tipis. “Aku suka gunung. Diam kadang lebih menyembuhkan daripada kata-kata.”
Kata-kata yang terdengar biasa kadang berfungsi seperti kunci cadangan—membuka pintu yang kita kira sudah lama terkunci.
.
Namanya Jagir. Di kartu namanya tertulis “fotografer dokumenter.” Di matanya tertulis sesuatu yang lain: kelelahan yang dipoles sabar, malas berdebat, luka yang dirapihkan sampai tak lagi kelihatan. Mereka berjalan bersama menuju parkiran, suara jazz tersisa seperti hening yang masih hangat.
“Aku suka pantai,” ulang Alun, kali ini lirih. “Karena di sana aku bebas menangis. Ada kenangan yang tak bisa kulupakan.”
Jagir menatap lurus ke jalan basah. “Aku ke gunung untuk menghindari kebisingan. Dulu aku mudah marah. Sekarang aku memilih diam. Kalau aku bicara panjang lebar, mungkin aku malah sedang membohongi diri.”
Hujan sempat reda, lalu menitik lagi. Ada jeda yang tidak canggung. Dua orang berdiri di bawah pinggiran atap ruko, sama-sama menyelamatkan diri dari cuaca dan dari hal-hal yang lebih besar dari cuaca.
.
Mereka mulai bertemu rutin. Bukan pacaran, bukan juga pertemanan yang harus diumumkan dengan foto berdua. Ada sore di mana mereka hanya duduk dekat jendela, menatap lampu kendaraan yang bergerak seperti ikan-ikan kecil di akuarium. Ada malam di mana mereka terjebak hujan di kedai kecil, mendengarkan denting cangkir dan bunyi rintik seperti alfabet lain yang menulis kalimat-kalimat tak terbaca.
Di antara obrolan tentang film dan pekerjaan, terselip nama-nama yang bagi orang lain tidak berarti apa-apa, tetapi bagi mereka semacam sandi: Maya, Madi, Ninggar, dan Tal. Adaptasi nama-nama yang pernah Alun temukan dalam kisah lama, di buku saku pasar loak: tokoh-tokoh dari cerita Menak yang ia baca sambil menunggu klien di kafe, tanpa gelar, hanya nama, seperti kita semua di bawah lampu neon.
Maya—teman lama Alun di komunitas. Sering tersenyum, sering juga menghilang. Kalau datang, datang dengan suara yang lebih keras dari biasanya, seakan sesuatu di dalamnya perlu diyakinkan terus-menerus.
Madi—rekan proyek Jagir. Pekerja keras. Jika tertawa, menutup mulut dengan punggung tangan. Selalu mengaku baik-baik saja, bahkan ketika sepatunya basah dan matanya merah.
Ninggar—seseorang dari masa lalu Alun. Nama yang tak lagi diucapkan, tetapi setiap hurufnya masih punya kamar khusus di jantung.
Tal—bos salah satu klien besar. Profesional, logis, tajam. Orang seperti baja tahan karat, yang kadang kita butuhkan untuk menyusun ulang hidup, kadang juga membuat kita retak.
Tokoh-tokoh itu berjalan keluar dari buku, memasuki kota, lalu berbaur dengan warga lain: tukang parkir yang tahu siapa yang baru patah hati, barista yang hafal selera kopi pelanggan tanpa perlu ditanya, sopir ojek yang lebih mengerti arah pulang kita daripada diri kita sendiri.
.
Di sebuah warung kopi pinggir kota, di mana dindingnya masih bau cat baru dan kursinya berbeda-beda karena dibeli dari pasar loak, Alun akhirnya mengeluarkan cerita yang disimpannya rapat.
“Dulu,” katanya, “aku dekat sekali dengan seseorang.” Ia berhenti, menatap permukaan latte yang mulai dingin. “Kami ke pantai itu. Ombak sedang bagus, katanya. Kita duduk, katanya. Kau tahu, Jagir, kadang-kadang langit begitu biru sampai kita lupa menakar jarak. Ia berenang terlalu jauh. Aku menunggu di bibir pasir, memotret kaki kami yang saling bersisian. Dan setelah itu… aku tak bisa lagi memotret air.”
Tak ada violin di udara. Tak ada adegan slow-motion. Hanya meja kayu, dua cangkir, suara kendaraan lewat. Namun Alun merasakan sesuatu mengalir keluar dari dadanya dalam cara yang paling sederhana: ia sanggup menyebut kata “tenggelam” tanpa dadanya meletup.
“Kita semua punya pantai masing-masing,” ucap Jagir, pelan. “Tempat di mana kita membiarkan air mata jatuh tanpa malu.”
Sejak saat itu, Alun tidak lagi berbohong kepada diri sendiri dengan cara-cara kecil yang terlihat normal: ia tidak lagi menjanjikan revisi desain “besok pagi” jika malam itu waktunya duduk diam bersama sepi. Ia mulai menata ritme: dua klien besar dalam sebulan sudah cukup, selebihnya untuk membaca, berjalan, atau sekadar menatap kucingnya menendang-nendang udara saat bermimpi.
.
Di komunitas, suara manusia kadang lebih lantang daripada musik. Orang-orang berkumpul untuk saling mempresentasikan karya, tetapi juga, tanpa disadari, saling mempresentasikan topeng. Ada yang menertawakan selera orang lain untuk menutupi ketakutan pada seleranya sendiri. Ada yang berpidato panjang agar tak ada yang sempat bertanya, “Kau sebenarnya sedih tentang apa?”
“Lihat mereka,” bisik Alun pada Jagir suatu kali. “Ramai sekali bicara tentang orang lain.”
“Mereka mungkin kesepian,” jawab Jagir.
Jawaban itu sederhana. Namun di kepala Alun, sesuatu bergerak. Ia ingat Maya yang datang dengan suara yang lebih keras dari biasa. Ia ingat Madi yang selalu tertawa menutup mulut. Ia ingat Tal yang tajam dan Nol-Persen-Kompromi sampai-sampai semua orang takut menghubunginya di luar jam kerja, padahal ada kemungkinan besar Tal hanya ingin memastikan semuanya tetap berjalan, karena kalau macet ia tak tahu harus bicara dengan siapa.
Alun membeli buku catatan bergaris, menuliskan kalimat-kalimat yang ingin ia ingat:
— “Orang yang marah sering sembunyikan ketakberdayaan.”
— “Orang yang cerewet sering sembunyikan cemas.”
— “Orang yang diam bisa jadi sedang menahan banjir.”
Ia tak lagi mudah ikut tertawa saat teman jadi bahan lelucon. Ia mendengar lebih lama dari biasanya, membalas lebih pelan dari biasanya. Dalam diamnya, ia menemukan ruang untuk orang lain bernapas.
“Kita semua pejuang dalam senyap,” tulisnya pada halaman berikutnya. “Jangan iri pada tawa orang lain, sebab kita tak tahu air mata yang pernah mereka telan.”
.
Di luar jendela, kota menulis dirinya dengan tanda baca: tanda tanya pada tikungan-tikungan yang belum dihafal, tanda seru pada pengumuman diskon di mal, tanda titik pada lampu merah yang membiarkan kita berhenti sejenak. Alun mulai menyukai berhenti. Ia tak lagi takut terlambat datang ke pameran jika itu berarti sempat memotret langit jingga dari jembatan penyeberangan.
Pada sebuah sore yang keemas-emasan, ia mengantar file desain ke kantor Tal. Lift kaca naik perlahan, memperlihatkan kota seperti peta yang ditelentangkan. Tal menunggu di ruang meeting. Rapih. Dingin. Efisien.
“Logo ini…” Tal mulai menguji. “Kau yakin bentuk tajamnya tidak terlalu agresif?”
Alun tak gentar. “Saya ingin merek ini bicara terus terang, tidak menipu. Tajam tidak selalu berarti menyerang, bisa juga berarti jujur.”
Tal menatapnya lama-lama, lalu menunduk melihat cetakan. “Jujur,” ulangnya. Ada sesuatu yang melunak di suaranya. Mungkin, pikir Alun, orang seperti Tal juga ingin dipercaya mampu luluh.
Sebelum keluar ruangan, Tal memanggilnya. “Alun.”
“Ya?”
“Terima kasih sudah tidak mengiyakan semua hal yang saya katakan.”
Itu pujian paling aneh dan paling tulus yang pernah Alun terima sepanjang kariernya.
.
Malam itu hujan turun lagi. Kota memantul di genangan, terlihat lebih cantik daripada biasanya. Alun dan Jagir terjebak di kedai kecil—kedai yang sama, mungkin meja yang sama. Purnama menunggu di apartemen; Alun membayangkan kucingnya melingkar di kursi, tidak peduli dunia di luar sana remuk redam oleh ambisi dan deadline.
“Aku ingin belajar setia pada diriku sendiri,” kata Alun, memandangi hujan yang tampak seperti ribuan garis tipis menyusun layar kabut. “Bukan sekadar pada orang lain.”
“Aku ingin belajar membuka hati,” jawab Jagir, menatap uap yang naik dari cangkir. “Tidak semua orang datang untuk melukai.”
Keduanya tidak saling menatap ketika mengucapkan itu. Mereka menatap hujan, lalu menatap tangan masing-masing. Keduanya paham: kalimat-kalimat itu seperti paku, tidak akan berguna kalau tidak mengetuknya pelan-pelan berhari-hari sampai tertanam.
.
Di pertemuan akhir tahun komunitas, di aula kecil yang disulap jadi ruang pertunjukan, nama-nama dipanggil untuk presentasi. Maya tampil lebih tenang dari biasanya. Presentasinya pendek, lugas, dan untuk pertama kalinya ia menutup dengan kalimat, “Aku sedang belajar minta tolong.” Tepuk tangan berdiri bukan untuk karyanya—meski bagus—melainkan untuk kalimat itu yang terasa seperti perayaan kecil bagi semua orang yang selama ini pura-pura kuat.
Madi mengunggah foto karyanya di dinding belakang, lalu duduk di lantai, tertawa tanpa menutup mulut. Barangkali ia telah menyetujui kenyataan bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada kelihatan sempurna.
Tal datang belakangan, duduk di baris belakang, dan sesekali mengangguk. Saat sesi usai, Tal menepuk bahu Alun pelan, seperti seseorang yang ingin belajar cara baru untuk mengatakan “terima kasih.”
Alun memandang sekeliling: mereka yang ramai bicara tentang orang lain mungkin hanya butuh didengar. Mereka yang suka pantai mungkin sedang berdamai dengan kenangan. Mereka yang suka gunung mungkin sedang belajar berdamai dengan sunyi. Mereka yang marah, mungkin tak tahu cara menyampaikan luka. Mereka yang diam, mungkin lelah secara psikologis.
Di balik wajah yang ditunjukkan, semua orang membawa cerita masing-masing—dan semua cerita, jika diberi tempat, akan menemukan kalimat penutupnya sendiri.
.
Suatu malam, Alun pergi ke pantai. Tidak sejauh dulu, cukup ke bibir kota, di mana kapal nelayan dirangkai lampu mengapung seperti kalimat yang tidak ingin tidur. Ia duduk di pasir lembab, membuka jurnal.
“Aku suka pantai,” tulisnya. “Karena di sini aku diizinkan jujur. Aku tak perlu tersenyum palsu. Aku tak perlu berbelit. Aku hanya perlu menjadi manusia biasa yang pernah terluka dan sedang belajar sembuh.”
Air mata jatuh. Kali ini tidak dilarang. Ombak datang, pergi, datang lagi, seakan-akan sedang memberi ilustrasi paling sederhana tentang ketekunan.
“Tak apa,” desahnya, entah kepada siapa. “Aku akan baik-baik saja.”
Di kejauhan, kilat memecah langit dengan elegan. Hujan sebentar lagi tiba. Alun menarik napas panjang dan bangkit, merapikan ransel. Ada pekerjaan menunggu esok, ada orang-orang yang akan ditemuinya, ada kota yang, suka atau tidak, akan memeluknya dengan caranya sendiri: riuh, bau, tulus, dan kadang kasar.
Ia menulis satu kalimat terakhir sebelum menutup jurnal, kalimat yang tak ingin kehilangan tempatnya:
“Memahami lebih penting daripada sekadar tahu.”
.
Beberapa minggu kemudian, ia memutuskan mengunggah sesuatu di media sosial—bukan desain, bukan foto kucing, bukan kopi. Hanya teks putih di latar hitam:
“Setiap orang menyimpan sesuatu yang tak kita tahu. Jangan cepat menilai. Lebih baik hadir, mendengar, dan memeluk dengan empati.”
Pesan masuk dari Jagir beberapa menit kemudian:
“Di dunia yang ramai, kita semua butuh tempat untuk diam dan dimengerti. Terima kasih sudah jadi teman perjalanan.”
Alun menatap layar ponsel. Di kaca jendela, wajahnya memantul di antara lampu-lampu kota. Ia tersenyum—bukan senyum untuk kamera, bukan senyum untuk menyenangkan orang lain, melainkan senyum kepada seseorang yang akhirnya dikenalnya dengan cukup baik: dirinya sendiri.
Kota melanjutkan geraknya. Pagi dibunyikan oleh tukang roti, siang oleh pedagang bakso, petang oleh adzan magrib. Di perempatan, dua pelajar saling berebut payung. Di halte bus, seorang ibu menyelipkan biskuit ke tas anaknya. Di apartemen kecil di lantai delapan, Purnama berguling di karpet, menaruh wajahnya di telapak tangan Alun, dan dunia tiba-tiba sederhana.
Suatu sore, Alun menerima pesan dari Maya: “Boleh pinjam telingamu? Aku ingin bercerita.”
Ia tersenyum dan membalas: “Sini. Aku bawa payung.”
Di lain waktu, Tal mengirim email singkat: “Rapat besok. Tidak formal.” Lalu menambahkan, dengan cara yang membuat Alun tertawa kecil: “Aku sedang belajar tidak selalu benar.”
Madi memotret jarinya yang kotor cat, menulis: “Selesai satu karya. Aku tidur dulu.”
Jagir mengirimkan foto gunung dari kejauhan: warna biru yang berlapis-lapis seperti lipatan kain. “Ada ruang kosong di punggung bukit,” tulisnya. “Mari kita isi dengan diam.”
Alun menyimpan semua itu seperti menyimpan uang kecil: tidak bernilai besar satu per satu, tetapi jika dikumpulkan, menyelamatkan hari-hari.
.
Tidak ada perayaan. Tidak ada konfeti. Hanya perubahan kecil yang konsisten—dan itu cukup. Kadang-kadang luka tidak sembuh menjadi kulit baru yang tak berbekas; kadang ia menjadi peta samar yang mengingatkan kita ke mana saja pernah tersesat dan bagaimana cara kembali.
Pada suatu malam ketika hujan turun persis saat lampu-lampu kota dinyalakan, Alun berdiri di balkon kecil, menatap jalanan yang berkilat. Dalam dengung mesin dan seret ban, ia mendengar sesuatu yang dulu tak terdengar: suaranya sendiri, pelan, tapi jelas.
“Aku tidak perlu membuat semua orang menyukaiku,” katanya pada dirinya sendiri. “Aku hanya perlu setia pada yang benar di hatiku, dan pada orang-orang yang berjalan beriringan, meski tak selalu searah.”
Di balik wajah yang kita tunjukkan, semestinya ada wajah yang lebih jujur menatap balik. Jika kita beruntung, kita akan berjumpa dengannya sebelum kota memadamkan lampu. Jika kita tidak beruntung, kita tetap bisa belajar mengetuk pintunya, perlahan, dengan sabar.
Dan ketika pintu itu terbuka—sedikit saja—udara yang masuk akan mengajarkan hal yang Alun tulis malam itu, sederhana dan tak bermaksud puitis:
“Yang kita cari sering bukan tepuk tangan, melainkan tempat duduk yang tenang untuk menata napas.”
.
.
.
Jember, 11 Juni 2025
.
.
#Cerpen #KompasMingguVibes #UrbanStory #Empati #Kesepian #LukaBatin #SelfHealing #CeritaIndonesia #NamakuBrandkuStyle
.
Quotes yang relate dengan isi cerita:
-
“Kesepian bukan ketiadaan orang, tetapi ketiadaan tempat untuk menjadi diri sendiri.”
-
“Luka tidak selalu minta obat; kadang hanya minta ruang.”
-
“Diam adalah bahasa kedua bagi yang pernah disalahpahami.”
-
“Empati adalah rumah singgah bagi cerita yang tak sempat selesai.”