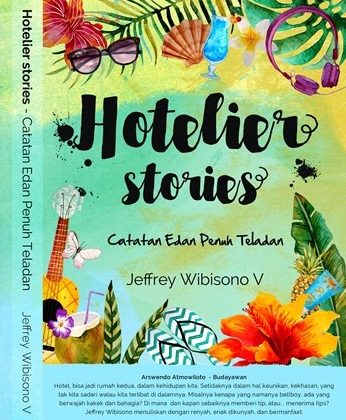Luruskan Jalanmu, Seratkan Langkahmu
“Kadang yang paling bising bukan jalan raya, melainkan hati yang lama kita biarkan menunggu jawaban.”
“Keberanian tidak selalu berteriak. Sering kali ia hanya berkata pelan: hari ini, lanjut lagi.”
“Jangan lelah jadi baik, hanya karena kebaikanmu belum diberi panggung.”
“Tegakkan niat, luruskan jalan, seratkan langkah—selebihnya, biarkan waktu membuktikan.”
.
Surat untuk Minggu Pagi
Senin pagi di Jakarta tidak pernah bernegosiasi. Jalur layang Kuningan merangkak, halte bus Transjakarta penuh setumpuk napas yang disetrika tipis-tipis oleh kewajiban. Ardan—nama lengkapnya Ardaningrat—menyisipkan tubuh dalam arus manusia kantor yang terbiasa menyebut ambisi dengan istilah KPI, dan kepenatan dengan istilah “alignment”. Udara menyengat, tapi bukan polusi yang menyiat dadanya melainkan kalimat yang dilemparkan sepekan lalu oleh Mahesa, direktur utama yang tatapannya seperti penggaris besi: dingin, lurus, tak bisa ditawar.
“Kalau kamu serius mau naik jabatan, Ardan, buktikan. Take the reins. Tunjukkan kamu bisa jadi garda terdepan.”
Kalimat itu berputar di kepala Ardan seperti jam dinding ruang rapat: setia, tak kenal lelah. Bertahun-tahun ia berjalan rapi di dalam pagar prosedur, menyalakan lampu-lampu kecil yang membuat orang lain bisa membaca peta. Namun pagi itu ia sadar, peta yang lama tidak lagi memadai untuk menempuh musim baru. Ia menyiapkan presentasi, bukan tentang “lebih banyak”, melainkan “lebih bermakna”: integrasi digital antar divisi, pembibitan talenta muda lintas kota, dan cara kerja yang membolehkan empati duduk sejajar dengan efisiensi.
Tangannya berkeringat, tetapi pikirannya jernih. Ia mengulang satu doa ringkas yang diajarkan mendiang kakeknya—orang Jember keturunan Menak yang menyebut “tirakat” bukan sebagai puasa lapar, tetapi puasa pada hal-hal yang tak perlu.
Ojo kesel dadi wong becik, meski sepi saksi.
Ia masuk gedung kaca yang menyalin langit Jakarta seperti menyalin mimpi. Lift melesat tanpa percakapan; di lobi lantai dua puluh, jam sudah tepat pukul sembilan.
.
Rapat Penentuan Takdir
Ruang rapat direksi dingin seperti ironi. Layar LED membentang, menyisakan meja panjang dengan botol air berjejer rapi. Komite strategis duduk—ada komisaris yang selalu menimbang biaya sebelum manfaat, ada kepala keuangan yang menyukai angka lebih daripada kata, ada Mahesa yang jarang mengangguk.
Ardan membuka dengan fakta yang tak bisa dibantah: pasar bergerak ke arah layanan yang luwes, konsumen menuntut pengalaman menyeluruh, dan tim-tim internal butuh “jembatan”, bukan “tembok”. Ia memaparkan peta jalan tiga fase: pilot kecil di Jakarta, replikasi di Surabaya dan Medan, lalu skala nasional. Ia menunjukkan data, risiko, mitigasi; tapi ia sengaja menambahkan satu halaman yang tidak biasa di presentasi korporat: “Ukuran Manusia”.
“Kalau kita tidak keluar dari pola lama yang stagnan,” ucap Ardan, menatap ke arah komisaris yang sejak awal mengerutkan dahi, “kita akan jadi perusahaan besar yang lambat. Kompetitor lebih kecil bisa menang bukan karena ukuran, tetapi karena keberanian berubah. Dan perubahan hanya mungkin kalau manusia di dalamnya merasa dilihat.”
Sunyi. Mahesa menyender, mengetuk meja sekali, dua kali. “Anggaran?”
Ardan menjawab pelan, “Kita shift, bukan tambah. Kita pangkas seremonial, kita alihkan ke pelatihan dan coaching. Kita invest di tool yang benar-benar dipakai, bukan yang hanya cantik di deck. Kita pasang target bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas relasi dengan klien.”
Komisaris menukas, “Ambisius.”
Ardan menahan diri agar tidak tersenyum. “Iya, Pak. Tapi ambisius yang bertujuan itu menyehatkan.”
Hening berubah jadi hening yang lain: hening yang mengakui. Tidak ada tepuk tangan. Hanya napas panjang—dan halaman baru yang diam-diam dibalikkan oleh semua orang di ruangan itu.
.
Dari Jember ke Jakarta
Sore hari, Ardan menepi di warung pecel lele Tebet. Minyak panas mendesis di kuali; aroma kemangi mengingatkannya pada halaman rumah di Jember, di mana ibunya pernah menjemur biji kakao sambil bernyanyi lirih. Kakeknya, Rengganis, bekas abdi dalem yang suka menyelipkan pitutur Jawa dalam cerita Menak Madura: tentang Wiraraja yang pandai membaca musim, tentang Jokotole yang setia pada kebenaran meski harus menempuh jalan memutar.
“Urip iku kudu nglakoni. Ojo mung mikir kepenakmu dewe,” begitu suara kakeknya seperti kaset usang yang tetap jernih.
Ardan merogoh ponsel. Ada pesan dari ibu: Le, aku bangga. Terus nglakoni sing bener yo. Ada air yang mengetuk mata. Bukan sedih. Semacam kelegaan yang lama menunggu pintu.
Ia menulis catatan di aplikasi notes: “Kita lahir bukan hanya untuk mengikuti alur, tetapi menciptakan arus. Arus butuh arah. Arah butuh keberanian. Keberanian lahir dari diam yang jujur.”
Ia menutup ponsel. Pecel lele datang. Nasi hangat, sambal tomat yang sederhana, lauk yang tidak menuntut dipuji. Ia makan perlahan, merasakan sesuatu yang menegakkan tulang punggungnya dari dalam.
.
Mentoring yang Mengubah Arah
Rabu, sesi mentoring internal. Ardan biasanya kaku, kalimatnya singkat, slide-nya tak pernah lebih dari sepuluh lembar. Tapi hari itu ia membuka dengan kalimat yang membuat ruang rapat seketika menjadi ruang tamu.
“Kalau kita hanya bekerja demi gaji, maka kita akan selalu merasa kurang. Kalau kita bekerja untuk nilai, kita sedang menciptakan warisan.”
Ia bercerita tentang seorang junior di Surabaya, Salsabila, yang hampir mengundurkan diri karena merasa tak terlihat. Ia meminta Salsabila memimpin proyek uji coba kecil, memberi ruang gagal yang aman, lalu merayakan pembelajaran bukan sekadar keberhasilan. Di layar, muncul dashboard sederhana—bukan angka penjualan, melainkan indikator kepercayaan diri tim.
Di ujung sesi, seorang staf IT yang sehari-hari dipanggil “Joko” (nama lengkapnya Tole, oleh teman-temannya dijuluki Jokotole karena selalu menemukan jalan ketika sistem macet) mendekat. “Mas Ardan, terima kasih. Saya sempat mikir mau keluar. Tapi mungkin saya perlu mencoba lagi—dengan cara yang lebih benar.”
Ardan menyahut ringan, “Yang penting, jangan hilang arah.”
Ia tidak tahu, kalimat ringkas itu akan menyelamatkan lebih dari satu orang dalam minggu-minggu berikutnya.
.
Kota yang Mengajar Pelan-Pelan
Minggu sore, koper kabin ditutup. Ardan akan ke Yogyakarta mengikuti short course strategic change management. Biaya sendiri, cuti sendiri. Teman sekantor mengangkat alis—di kota yang menilai “naik jabatan” dari daftar rapat yang dihadiri, Ardan memilih membesarkan kapasitas pribadi.
“Orang-orang besar tidak menunggu pintu terbuka,” gumamnya sendiri. “Mereka memahat kusen, memasang engsel, lalu mengetuk dengan sopan.”
Kereta melaju. Di kursi yang menghadap jendela, Ardan membaca e-book Leadership and Local Wisdom: A Javanese Perspective. Ia menandai paragraf tentang “ngeli tanpa keli”: menyatu dengan arus tanpa kehilangan jati diri. Di sela halaman, ia menulis: “Korporasi sering salah paham terhadap kecepatan. Kita kira cepat itu selalu progres. Padahal, kadang cepat adalah cara halus kabur dari ketakutan menghadapi sunyi.”
Di Malioboro malam hari, ia berjalan sendirian. Lampu-lampu memantul di aspal basah; pedagang batik menawar harga dengan setengah tertawa. Seorang bapak tua menjual serat kecil dengan judul yang membangunkan: Serat Ngudhari Paseduluran—panduan ringkas tentang mengurai simpul persaudaraan yang kusut. “Untuk bekal, Nak,” kata si bapak. Ardan membelinya, bukan karena ia butuh, tetapi karena buku itu seperti cermin kecil yang disodorkan kota.
Ia membaca halaman pertama di bangku trotoar. Ada kalimat begini: Aja gumunan karo sinar padhang, mergo kadhangkala pepadhang mung nyilauke, ora nuntun. Jangan mudah terpukau cahaya, sebab kadang cahaya hanya menyilaukan, bukan menuntun.
Ardan menutup buku. Di kejauhan, suara kereta kembali terdengar. Ia menatap langit yang mendung, merasakan sesuatu dirapikan di dalam dadanya.
.
Benturan di Persimpangan
Kembali ke Jakarta, minggu berjalan kencang. Pilot integrasi berjalan; Yogyakarta menanamkan kebiasaan singkat: menanyakan “apa kabar kerja hatimu?” sebelum “apa kabar timeline proyekmu?” Ia membagi metode check-in dua menit setiap rapat—dua menit yang tidak bisa dinegosiasi, di mana setiap orang menyebutkan satu hal yang disyukuri dan satu hal yang sedang mereka perjuangkan. Di hari ketiga, hasilnya mengejutkan: rapat lebih singkat, keberatan muncul lebih jujur, solusi ditemukan lebih tepat.
Tetapi perubahan tidak datang tanpa biaya sosial. Seseorang di middle management yang merasa wilayahnya terpotong mulai mengirim pesan-pesan halus ke komisaris, mempertanyakan “kelayakan” Ardan memimpin program. Di ruang kopi, ada bisik-bisik tentang “pencitraan”. Di group chat, ada sindiran yang dibungkus humor.
Suatu sore, Ardan dipanggil Mahesa.
“Ada yang mempertanyakan pendekatanmu, Dan.” Mahesa menatap tanpa tepi. “Kamu tahu siapa. Saya tidak peduli gosip, tapi saya ingin kamu paham: perubahan itu bukan hanya soal apa dan bagaimana, tetapi siapa yang merasa kehilangan.”
Ardan menahan napas. “Saya paham, Pak. Boleh saya yang bicara langsung?”
Mahesa mengangguk. “Boleh. Tapi ingat, kamu sedang membangun jembatan. Jembatan tidak boleh balas dendam pada sungai.”
Ardan menemuinya—Praba, kepala operations yang selama ini seperti tiang penyangga tua: kuat, tapi capek. Percakapan itu panjang, lebih banyak hening daripada kata. Pada akhirnya, Praba tidak setuju pada semuanya, tetapi ia setuju pada satu hal: mencoba satu langkah. Kadang, satu langkah adalah semua yang dibutuhkan agar kaki lain berani menyusul.
Malam itu, di apartemen yang sempit tapi bersih, Ardan kehabisan suara. Ia menyalakan kompor listrik, merebus mie instan, menambahkan sawi dan telur. Ia mengirim pesan ke Salsabila: Bagaimana tim? Ada yang butuh ditambal?
Balasan cepat: Ada yang patah semangat, tapi tidak patah arah. Kita pelan-pelan, Mas.
Ia tersenyum. Ada jenis lelah yang justru menyuburkan.
.
Kabar dari Rumah
Sabtu pagi, telepon dari Jember. Ibu cekakak cekikik menceritakan panen kecil-kecilan di kebun, betapa hujan datang tepat waktu seperti tamu yang tahu sopan santun. Di sela cerita, ibu menyelipkan kalimat yang tak pernah gagal mematri: Sing penting atimu resik, Le. Yen resik, Gusti gampang nglantarake.
Ardan teringat masa kecil: berlari di antara jemuran biji kakao, menyarung kain bermotif sederhana, mendengar kakek berkisah tentang Wiraraja yang cerdas membaca gelagat. “Madura itu angin,” kata kakeknya, “ia seperti tanjung yang berani menantang ombak tapi tahu kapan harus meluruh jadi pasir.” Ardan mengangguk, meski dulu tak paham. Kini ia mengerti: kekuatan bukan selalu menahan, tetapi juga melepaskan yang tidak lagi perlu.
Setelah telepon berakhir, ia menulis di jurnal: “Tiap langkah kecil yang tulus akan mengantarkan pada takdir besar yang tak disangka.” Lalu menambahkan satu kalimat lagi: “Dan takdir itu tidak datang sambil menepuk pundak; ia datang sebagai konsekuensi pilihan yang diulang.”
.
Saat Segala Sesuatu Retak
Dua minggu kemudian, pilot integrasi meraih tonggak bagus: onboarding lebih cepat 32%, handover proyek lintas divisi turun dari 10 hari menjadi 4 hari. Tetapi perayaan diganggu masalah yang turun tanpa mengetuk: data breach kecil akibat kelengahan vendor. Tidak ada kebocoran sensitif, tapi cukup membuat compliance mengetukkan palu darurat. Media belum tahu, namun internal gegas.
Di ruang krisis, layar menampilkan kronologi. Wajah-wajah tegang. Mahesa mempersilakan Ardan bicara. Ia tidak defensif; ia akui celahnya, ia jelaskan langkah perbaikan. Yang berbeda, ia memulai dengan permintaan maaf—bukan karena suruhan, tetapi karena ia merasa memegang kendali atas arah.
Praba menatapnya lama-lama. Di akhir rapat, ia menepuk bahu Ardan, pelan sekali, hampir seperti memindahkan beban yang selama ini dipegangnya sendiri. “Kamu tidak lari,” katanya singkat.
“Kalau lari,” Ardan membalas, setengah bercanda, “saya capek sendiri, Pak.”
Ruang krisis pecah jadi tawa kecil yang tidak dibuat-buat. Di luar gedung, awan Jakarta merapat, seolah kota ikut memendam lega.
.
Surat yang Belum Pernah Dikirim
Malam Minggu berikutnya, Ardan menulis surat—bukan untuk dikirim, melainkan untuk dibaca ulang di Minggu pagi.
Ayah dan Ibu yang baik,
Aku tahu kalian tak meminta apa-apa selain anak yang pulang dengan hati utuh. Di kota ini, aku belajar bahwa kejujuran tidak selalu disambut; sering kali ia diminta menunggu di lorong. Tapi aku tidak akan menyuruhnya pulang. Biarlah ia duduk, meskipun sendirian, sampai ada ruang untuknya.
Aku sekarang memimpin tim kecil yang sedang belajar berjalan. Kami belum berlari. Sesekali kami jatuh. Tapi kami belajar mengulurkan tangan satu sama lain. Aku percaya, begitulah warisan dibangun: bukan dari logo besar di gedung, melainkan dari cara kita memperlakukan orang yang bekerja bersama kita.
Sehat selalu, Ibu. Doa Ibu terasa seperti daun jati yang melindungi biji kakao dari hujan terlalu deras.
Salam,
Ardan
Ia menyelipkan surat itu di dalam buku Serat Ngudhari Paseduluran. Di halaman sampul, ia menulis dengan tinta yang cepat mengering: “Jangan berhenti jadi manusia pada saat dunia mendorongmu jadi mesin.”
.
Panen Kecil Bernama Kepercayaan
Bulan berganti. Angka-angka memperlihatkan tren yang stabil; bukan kurva menanjak semu, melainkan garis yang tegas karena ditempa kebiasaan baru. Ardan mengajukan satu langkah tambahan: coaching lintas kota via daring, kelas-kelas mini di mana satu orang bercerita tentang kesalahan yang sedang mereka perbaiki. “Kita rayakan yang jujur,” katanya, “agar orang-orang berani jujur sebelum terlambat.”
Suatu sesi, Joko—si Jokotole—mengaku bahwa ia pernah menunda pembaruan patch karena takut rapat dimarahi. “Saya pikir semuanya harus sempurna,” katanya. “Ternyata yang dibutuhkan tim adalah kejujuran lebih cepat.” Tidak ada cemooh. Hanya catatan perbaikan. Setelah sesi, orang-orang menulis di chat: terima kasih sudah membuka jalan. Panen kecil bernama kepercayaan mulai menebar bau tanah.
Mahesa, yang jarang memuji, memanggil Ardan. “Saya tidak mudah percaya pada wacana lembut. Tapi kamu menunjukkan bahwa kelembutan bisa jadi disiplin. Itu sulit.”
Ardan mengangguk. “Terima kasih, Pak.”
Mahesa menatap jam, lalu menatapnya lagi. “Kamu siap kalau saya minta kamu memimpin unit baru ini secara resmi?”
Ardan tidak langsung menjawab. Ia ingat short course di Yogyakarta, buku kecil dari bapak penjual serat, doa ibu, dan surai halus kelelahan yang berubah jadi kekuatan. “Saya siap, Pak. Dengan satu syarat.”
Mahesa menaikkan alis. “Apa?”
“Kita ukur juga ukuran manusia: trust index, psychological safety, indikator burnout. Kalau tidak, kita hanya mengganti spare part mesin, bukan merawat kendaraan.”
Mahesa terdiam sebentar. “Setuju.”
.
Jember, Jakarta, dan Jalan Pulang
Di akhir tahun, Ardan mengambil cuti. Ia pulang ke Jember. Udara di rumah punya jam tangan sendiri; waktu berjalan pelan, seolah setiap detik diseduh sebelum diminum. Ia menapak tanah kebun yang membuat telapak kakinya mengingat—dulu ia pernah jatuh di sini, lutut berdarah, dan kakeknya berkata: “Sakit itu guru.”
Di teras, ibu menyuguhkan kopi. “Kabar apa, Le?”
Ardan bercerita secukupnya; ia tidak pernah merasa perlu membingkai keberhasilan sebagai berita besar. Ibu mendengarkan, matanya menyipit diganggu sinar senja. “Koyo ngene iki sing tak karepke. Dudu pangkatmu, nanging awakmu sing tetep dadi omah sing penak kanggo wong liya.”
Ardan tertawa. “Berarti saya arsitek, Bu?”
Ibu menepuk punggung tangannya. “Yo, arsitek ati.”
Malam itu, di kamar yang ditempati sejak remaja, Ardan menatap langit-langit. Di kota, ambisi sering berlari tanpa alas kaki; di kampung, tujuan melangkah dengan sandal jepit. Ia tertidur dengan jauh lebih pulas daripada malam-malam di apartemen.
.
Kembali ke Jakarta, Bukan Orang yang Sama
Awal pekan, ia kembali ke Jakarta dengan koper yang isinya masih sama, tetapi langkah yang tidak lagi sama. Di ruang kerja barunya—lebih lega, ada jendela yang menatap pohon ketapang—ia menempelkan selembar kertas pada papan: “Luruskan jalanmu, seratkan langkahmu.” Kalimat itu ia pilih bukan karena puitik, melainkan karena praktis: meluruskan jalan menghindari sesat pikir; menyeratkan langkah memastikan pijakan tidak mudah putus.
Ia menata rapat perdana sebagai kepala unit. Tidak ada opening panjang, hanya tiga putaran kalimat: “Apa yang kita syukuri?”, “Apa yang membuat kita khawatir?”, “Pertolongan apa yang kita perlukan?” Di putaran ketiga, orang-orang mulai belajar meminta bantuan tanpa malu. Di akhir rapat, Ardan mengirim pesan ke semua: Ingat, kita tidak sedang mengejar kesempurnaan. Kita sedang belajar jadi versi terbaik diri sendiri. Tak apa pelan, asal benar arah.
.
Reflektif, Edukatif, Solutif: Catatan Ardan untuk Timnya
-
Kerja adalah perjalanan memaknai. Ukur bukan hanya output, tetapi makna yang ditinggalkan pada orang yang bekerja bersama kita.
-
Kecepatan tidak mengalahkan kejujuran. Laporkan lebih cepat, bukan lebih sempurna.
-
Rapat adalah ruang aman. Dua menit check-in, dua menit check-out—disiplin kecil yang menyelamatkan banyak salah paham.
-
Data adalah sahabat empati. Ukur trust, burnout, psychological safety, agar tak ada yang menang sendirian dan kalah beramai-ramai.
-
Tumbuhkan suksesor. Sukses bukan saat semua bergantung pada kita, melainkan saat kita bisa pergi libur panjang tanpa sistem runtuh.
Ia menutup memo dengan kalimat yang dipinjam dari kakek: “Sing isih bisa dilakoni, dilakoni. Sing ora perlu, ditinggal.” Sederhana, tetapi di kota yang suka menumpuk segala sesuatu, kesederhanaan ini sering lebih revolusioner daripada rencana lima tahun.
.
Serat yang Menguatkan
Beberapa bulan kemudian, papan skor perusahaan menampilkan hal yang jarang muncul serentak: capaian komersial naik, retensi karyawan membaik, dan indeks kepercayaan tim menanjak. Media internal menulis tentang “budaya perawatan” yang menggantikan “budaya pemadaman kebakaran”. Di foto halaman depan, Ardan berdiri paling pinggir, bukan di tengah. Ia sengaja. Pemimpin yang baik tidak menempatkan diri sebagai monumen; ia memilih berdiri di tepi, agar matanya bisa melihat siapa saja yang hampir terjatuh.
Di meja kerjanya, buku kecil dari Malioboro masih terbuka, menahan kertas bertuliskan tangan: “Jangan berhenti menaruh manusia di tengah.” Di sudut catatan, ia menambahkan satu baris, warisan kepada siapa pun yang kelak menggantikannya:
Tentukan arah hidupmu dengan jujur dan benar, lalu jalani setiap langkahnya dengan nilai-nilai luhur yang layak dikenang dan diwariskan.
Dan Jakarta, yang tak pernah bernegosiasi, tiba-tiba terasa lebih sabar menunggu orang-orang yang memilih untuk memperlambat langkah demi meluruskan jalan.
.
.
.
Jember, Senin 7 Juli 2025
.
.
#LuruskanJalanmu #SeratkanLangkahmu #LeadershipWithHeart #MenakMadura #JakartaStories #BudayaKerja #Mentorship #NJawani #CareerGrowth #Storytelling