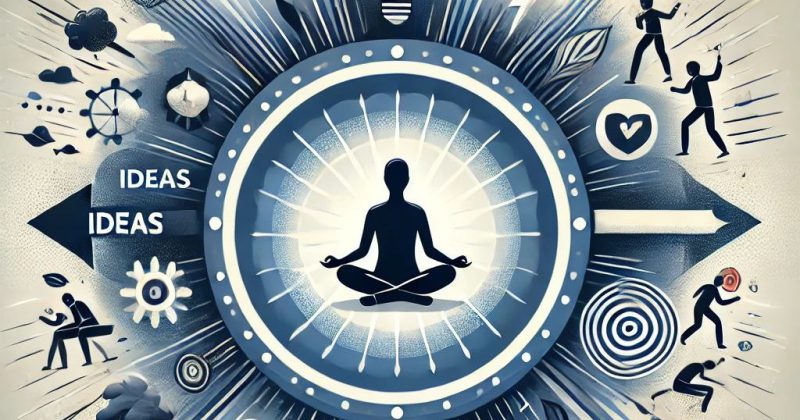Jejak Kebaikan yang Tak Terlihat
“Jadilah seperti matahari. Ia terus memberi hangat tanpa pernah menagih balasan. Yang penting, ia tahu sinarnya bermanfaat bagi banyak kehidupan.”
.
Hujan Jakarta hari itu turun seperti kalimat-kalimat yang tak sempat diselesaikan. Kaca gedung-gedung di Sudirman berembun, kolam-kolam kecil terbentuk di cekungan trotoar, lampu-lampu mobil memantul di permukaan aspal seperti bintang yang dipaksa turun ke bumi. Orang-orang menunduk di balik payung, menyelamatkan kemeja rapi, sepatu kulit, janji rapat, dan paket delivery yang harus tiba “sebelum makan siang”.
Di bawah lintasan MRT, di antara tiang-tiang beton yang menyimpan dengung listrik dan langkah ribuan penumpang, berdiri sebuah warung kecil beratap seng. Papan namanya sederhana: Warung Mundinglaya. Meja plastik berkilap oleh tetes hujan, kursi biru yang salah satu kakinya diganjal karet sandal. Aroma minyak panas, jahe, dan gula merah bercampur naik seperti doa yang memanaskan dada.
Adipati Mundinglaya—orang-orang memanggilnya Pak Munding—menyeka uap di kaca termos, menata pisang goreng, membiarkan tangan yang mulai berurat menuntun kebiasaan: menuang teh, mengangkat tempe mendoan pada detik sebelum terlalu cokelat. Usianya mendekati lima puluh. Rambutnya yang memutih tak buru-buru disemir. Senyumnya bukan senyum yang hendak menaklukkan pasar; melainkan senyum orang yang sudah lama berdamai dengan konsep rezeki: ada yang datang, ada yang pergi, ada yang disyukuri.
“Panasin lagi, Pak?” tanya seorang pelanggan tetap, kurir paket yang jaket hijaunya sudah penuh tambalan.
“Panasin hatinya dulu,” jawab Mundinglaya, setengah bercanda, setengah serius. Ia meniup secangkir teh, menggeserkannya. “Yang ini, gak usah bayar.”
Kurir itu mengangguk, menepuk dada seraya pamit. Namanya Arya Wiratmaja. Usianya baru lewat dua puluh lima, tubuhnya tangguh, matanya menyimpan garis-garis lelah yang tak pernah benar-benar hilang. Di layar ponsel Arya, notifikasi berdentang: tujuh alamat, dua belas menit jeda, “tolong cepat ya mas, ini urgent.” Ia mendongak sebentar memeriksa langit—seolah-olah cuaca punya ruang untuk kompromi—lalu memasang helm lagi. “Terima kasih, Pak.”
Sementara itu, di seberang kota, di sebuah lobi marmer apartemen mewah di Senopati, Nyi Ratnasari menekan tombol lift sambil menenteng tote bag rami berisi sayur-mayur segar dari pasar Blok A. Blazernya rapi, kuku-kukunya bersih tanpa cat. Ia manajer komunikasi sebuah perusahaan pengembang yang sedang mengincar tanah di koridor transit. Agenda harinya rapat, menyusun siaran pers, dan menenangkan warganet. Namun setiap Sabtu pagi, ia membungkus pekerjaan itu, menggantinya dengan kebiasaan kecil: belanja di pasar, menyapa pedagang, mengantar bungkusan sayur untuk seorang nenek yang tinggal sendirian di lantai 17.
Nama nenek itu Nini Rahyang Dewi. Wajahnya putih keriput seperti kertas yang penuh puisi. Cincin-cincin emas tipis melingkari jarinya—bukan untuk memamerkan, tapi untuk mengikat kenangan pada suami yang lebih dulu berpulang. Di ruang tamunya, tergantung foto hitam putih seorang lelaki muda berkacamata bundar, satunya lagi foto warna warni cucu-cucu yang kini tersebar di luar negeri. Kesepian di apartemen seperti hotel bintang lima: semua ada, tak ada yang benar-benar tinggal.
Ketika hujan mengeras pada pukul sembilan, ketika para satpam di bawah kanopi sibuk mengatur taksi online dan sopir antar-jemput, Ratnasari melihat Nini Rahyang di tepi tangga darurat. Tangan tuanya gemetar. Tumit sepatu datar itu terlalu licin untuk ubin basah.
“Bu, biar saya bantu,” seru Ratnasari.
“Duh, Nak Sari… maaf merepotkan,” gumam Nini.
“Tidak merepotkan. Pelan-pelan ya, Bu.”
Ratnasari memayungi, menggandeng. Hujan mengetuk permukaan payung seperti mengetuk pintu kenangan. Di anak tangga terakhir, Nini menatap mata Ratnasari, ada genangan yang tak berasal dari langit.
“Kadang Ibu pikir,” katanya pelan, “Tuhan mengirim anak perempuan baru setiap Sabtu pagi.”
Ratnasari menertawakan haru yang menetes. “Kalau begitu, Ibu tinggal pesan: ‘anak perempuan, antar bumbu rawon dan bahu untuk bersandar’.”
Mereka tertawa. Ada sesuatu dari tawa yang menghangatkan seperti teh jahe: tak menyelesaikan persoalan, tapi membuat perjalanan mungkin.
.
Siang memanjangkan jarak antara kantor-kantor dan jam makan. Arya menerobos banjir tipis, mengangkat motor melewati trotoar yang terlalu tinggi. Paket bertuliskan “Dokumen Penting” basah di pinggirannya. Ia berhenti mendadak ketika melihat seorang anak kecil terpeleset. Seorang ibu muda berpayung merah berlari-lari, wajahnya cemas menembus kerumunan.
“Mas, tolong!” teriaknya.
Arya meletakkan standar motor, mengangkat si bocah, memeriksa lututnya. “Gak apa-apa, cuma lecet.” Ia merobek plastik bubble wrap yang seharusnya melindungi “Dokumen Penting”, membalut lutut itu seadanya.
Ibu itu berterima kasih berulang-ulang. Arya mengangguk, mengusap rambut anak itu, lalu kembali menunggang motor. Dalam hati ia menertawakan diri: dua ribu rupiah plastik bubble wrap menghapus potensi marah bos. Tapi entah mengapa, dadanya terasa lebih lapang dari lajur busway.
Malamnya, ketika ujung hujan masih menetes dari kabel-kabel listrik, Arya menulis di forum kurir: “Ada warung di bawah jalur MRT, Warung Pak Munding. Tehnya hangat, omongannya hangat, dompetnya juga kadang-kadang hangat. Kalau kehujanan, mampir. Kalau hatimu kedinginan, lebih wajib mampir.” Unggahan itu mendapat puluhan komentar. Teman-teman kurir saling tag lokasi, mengunggah foto tempe mendoan, memuji sambal kecap yang seimbang antara asin dan manis, seperti hidup yang pasrah—bukan pasif.
Esoknya, Warung Mundinglaya penuh. Jaket-jaket pengantar paket digantung di paku, helm-helm ditata acak di sudut. Mereka bergantian menghangatkan tangan di atas panci rebusan jahe. Ada yang memberi review bintang lima di map, ada yang sekadar meninggalkan uang lebih di kaleng kopi.
“Lho, kok ramai?” tanya Sulastri, istri Munding, sambil tersenyum heran. “Berkah hujan?”
“Berkah saling cerita,” jawab Munding, menatap kaleng uang seperti menatap bayi yang baru belajar tersenyum. Di sudut warung, selembar kertas ditempel: “Kalau kamu kepepet, makan dulu. Bayar nanti. Kalau gak punya nanti, cukup doakan kami panjang sabar.”
.
Ada hari-hari ketika satu kota terasa seperti keluarga besar yang tidak saling kenal. Pagi itu, Ratnasari mengantarkan press release proyek transit oriented development di dekat stasiun. Di dalam dokumen itu, ada kata-kata yang ia susun rapi: “memberdayakan pedagang kecil”, “ruang publik inklusif”, “ekosistem UMKM”. Tetapi di luar kaca ruang rapat, ia tahu ada warung-warung yang akan tergusur oleh konsep yang sama-sama mulia: penataan.
Sore hari, setumpuk percakapan masuk ke DM Instagram-nya. Salah satunya dari akun “@kurir_nafasjaksel”: foto Warung Mundinglaya, caption panjang tentang tempat berteduh, tentang bapak yang menolak uang teh, tentang tulisan di dinding. Ada ratusan like, belasan komentar bertanda paku payung: “tolong jangan gusur warung ini”.
Ratnasari menghela napas. Nama “Mundinglaya” terdengar seperti legenda dari buku Bahasa Indonesia kelas tiga: pahlawan misterius yang menolong tanpa menunjuk dirinya. Sekarang legenda itu memanggilnya masuk ke medan yang nyata: rapat tim pengadaan lahan, tim keamanan, timeline progres.
Malam itu, Sari naik ojek online ke bawah lintasan MRT. Mendung seperti kain gelap yang digantung terlalu rendah. Ia mendapati warung kecil, secuil hangat dalam kota yang sibuk mencari efisiensi.
“Pak Munding?” Ia memperkenalkan diri. “Saya Ratnasari. Saya sering lewat, tapi baru sekarang sempat mampir.”
Mundinglaya mengangguk, menatap tanpa curiga. “Mampir itu rezeki, Mbak. Mau teh apa kopi?”
“Teh jahe… dua. Satu untuk saya, satu untuk Pak.”
“Kok jadi saya yang dibayarin?” gurau Munding.
Mereka tertawa. Lalu Ratnasari membuka obrolan yang berat di akhir cangkir: penataan, relokasi, kompensasi. Kata-kata itu terdengar kaku dibanding wangi jahe. Di seberang meja, wajah-wajah kurir ikut menoleh: “Warung ini digusur, Pak?”
“Bukan digusur,” ratap Sari, “ditata. Akan ada tempat relokasi. Tapi saya tahu… tempat baru tak selalu memindahkan kenangan.”
Kata “kenangan” berpendar di ruangan kecil itu. Seseorang berdehem. Arya masuk, menyeka hujan dari jaketnya, berdiri di pintu warung seperti anak yang baru pulang.
“Kalau ditata,” kata Arya hati-hati, “bisakah ditata tanpa menghilangkan hati?”
Ratnasari menatapnya. Suara mobil di atas kepala berubah seperti ombak yang memukul pantai. Dalam satu detik, ia menyadari: jabatannya bukan cuma penyusun kalimat rilis. Ia manusia yang kebetulan diberi akses ke ruang rapat.
“Ayo kita cari cara,” katanya. Kalimat itu pelan, tapi hatinya merasa seperti menandatangani sesuatu yang jauh lebih pribadi dari kontrak kerja.
.
Beberapa hari kemudian, di ruang rapat dengan proyektor yang suka nyalanya terlambat, Ratnasari mempresentasikan ide: “Zona Warung Transit”—sebuah klaster kecil di bawah lintasan yang tertata rapi, tersambung drainase, kios-kios modular yang bisa dipindahkan, papan nama seragam, dan—ini poinnya—seleksi prioritas untuk warung yang sudah duluan menghidupi area itu. Ia menyisipkan foto Warung Mundinglaya, testimoni para kurir, tautan thread cuitan yang viral, juga data sederhana tentang perputaran ekonomi mikro yang tak sepele.
Seseorang dari tim legal merengut. “SOP kita tidak memuat historis ‘siapa duluan’. Itu rawan konflik.”
“Kalau semua hanya angka,” jawab Sari, “kita nanti bangun kota yang rapi, tapi dingin. Dan dingin bukan cita-cita.”
Direktur proyek memutar kursi, kedua jarinya saling mengunci. “Kamu siap menanggung backlash kalau netizen bilang ‘kompromi dengan kumuh’?”
“Siap,” kata Sari. “Kumuh atau tidak, itu bisa ditata. Tapi mematikan sendi-sendi kecil yang selama ini menopang manusia—itu dosa yang tak bisa dicuci oleh foto peresmian.”
Keheningan. Di layar, wajah Munding seperti mengintip: tenang, tak menuntut.
“Baik,” kata sang direktur akhirnya. “Uji coba tiga bulan. Tapi… kamu yang fronting.”
“Baik.”
Di perjalanan pulang, hujan turun lagi. Ratnasari melambatkan langkah. Ada rasa takut yang rapi. Saya manajer komunikasi, pikirnya, tapi hari ini saya menandatangani komitmen pada makna kata “kota”: tempat berjumpa, bukan sekadar tempat melintas.
.
Kabar “Zona Warung Transit” menyebar. Arya membuat poster digital sederhana, mengajak komunitas kurir menyumbang untuk membantu renovasi kios Pak Munding. Donasi datang kecil-kecil: lima ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu. Di daftar donatur, ada nama yang membuat Arya berhenti lama: “Rahyang D.” Donasinya besar, meninggalkan catatan: “Hangatkan yang kedinginan. Bukan hanya dengan jahe, tapi dengan perhatian.”
Arya mengenal nama itu dari cerita-cerita di forum warga: perempuan tua yang saban Sabtu pagi ditemani “anak perempuan” yang suka membagi waktu antara kerja dan pasar. Arya tersenyum. Benang-benang tak terlihat itu ternyata berat sekaligus ringan.
Sabtu berikutnya, Arya memboncengkan Ratnasari menuju sebuah toko bahan bangunan kecil di Mampang. Mereka memilih seng anti berisik, lampu LED hemat energi, papan nama akrilik. Arya menawar seperti menawar nasib. Ratnasari membayar seperti membayar hutang pada cerita yang belum sempat ia tulis.
“Mas Arya,” kata Sari di atas motor, “kenapa kamu repot-repot mengurus ini semua?”
Arya tertawa tanpa suara. “Karena di hari hujan paling dingin hidup saya, ada pria yang menolak uang teh. Dan saya mau dunia ingat bahwa ada jenis bisnis yang laba utamanya bukan rupiah.”
Sari mengangguk. Jalan-jalan kota melintas seperti potongan film: anak-anak sekolah berlarian, ibu menggendong bayi, bapak tukang parkir tersenyum tanpa gigi. Sejak kapan kota menjadi sekedar rute? Sejak kita lupa menghafal wajah.
.
Di sisi lain, Nini Rahyang menatap hujan dari jendela apartemen. Kenangan tentang suaminya yang dulu aktivis mahasiswa kembali menepuk bahu. Ia ingat suara lelaki itu: “Kelak kalau kita mapan, kita mesti ingat, kenyang itu untuk berbagi.” Rahyang mengangkat telepon, menanyakan keponakannya yang bekerja di dinas UMKM. Ia mengajukan ide: kelas literasi keuangan untuk pemilik warung kecil.
“Biar saya yang biayai,” kata Nini. “Saya tidak punya anak kecil lagi untuk dibekali. Biar saya membekali usaha kecil.”
Keponakannya sempat menahan tawa haru. “Bu Nini, kalau semua orang pensiun berpikir seperti Ibu, pekerjaan negara jadi terasa manusiawi.”
Rahyang menutup telepon, menghela napas, lalu menatap ponsel lagi. Ia menulis pesan untuk Ratnasari—yang ia simpan kontaknya di bawah nama “Anak Perempuan Sabtu”: “Kalau kios sudah rapi, kabari. Ibu mau mampir.”
.
Peresmian kecil itu terjadi pada sore yang cerah setelah serangkaian hari basah. Papan nama Warung Mundinglaya kini berpendar lembut, lantainya disemen halus, talang air baru mencegah genangan. Ada pita merah muda, ada balon dua buah ditiup anak-anak, ada dua puluh porsi pisang goreng yang panasnya seperti karakter utama pesta.
Hadir para kurir dengan jaket yang kali ini tak terlalu basah. Ada Ratnasari, menenteng bundel manual brand untuk kios transit (yang entah sejak kapan diimpikannya), ada Nini Rahyang dengan kebaya sederhana dan selendang yang harum kapur barus.
“Lho,” kata Mundinglaya, menunduk setengah membungkuk, “Yang tua kok repot-repot datang?”
“Karena yang muda sudah terlalu sibuk menjadi penting,” canda Rahyang. Mereka tertawa.
Pembukaan tak muluk. Tidak ada pejabat, tidak ada spanduk sponsor. Hanya seorang kurir yang memimpin doa singkat: mengucap syukur atas hujan yang mengajarkan pertemuan. Setelah doa, Munding memecah balon—bukan, ia memotong seuntai pita—mengundang semua orang makan bersama.
Di tengah suasana itu, seorang pria bermobil mewah berhenti. Kemeja linen, jam tangan besar, kening yang menandakan kepemilikan beberapa lembar saham lebih banyak dari rata-rata orang. Ia menoleh, melihat kerumunan, dan—ini momen yang jarang—mendekat tanpa merasa lebih tinggi.
“Saya pemilik lahan seberang,” katanya kepada Munding. “Saya dengar tempat ini mau ditata. Terus terang, tadinya saya berpikir ini mengganggu pandangan. Tapi hari ini saya paham… pandangan saya yang harus ditata.”
Ia mengeluarkan kartu nama. “Kita bikin program bersama. Warung transit ini bisa jadi contoh integrasi. Saya bantu lampu-lampu tambahan, asalkan pakai listrik aman. Saya tidak ingin membantu setengah-setengah.”
Munding menatapnya lama. “Bapak… orang kaya?”
Pria itu tertawa. “Saya ingin jadi orang benar dulu. Kalau itu berhasil, kaya atau tidak, biarlah jadi status sampingan.”
Arya berdiri di belakang, menahan tepuk tangan yang ingin meledak. Ratnasari mencatat nama pria itu, sudah membayangkan siaran pers yang—kali ini—tidak terdengar seperti jargon.
.
Kota pelan-pelan mengingat cara memeluk. Para kurir menjadikan Warung Munding titik kumpul. Karyawan kantoran membawa bekal meeting ke sana: lontong sayur yang rasanya mengingatkan pada Lebaran, teh tarik yang menghibur putus asa. Di sudut dinding, Ratnasari menempel stiker kecil: “Bila kamu kepepet, makan dulu. Bayar nanti.” Di sebelahnya, stiker lain: “Bila kamu longgar, bayarkan satu porsi untuk yang belum sempat.” Sistemnya sederhana: papan paku dengan kartu-kartu kecil bertuliskan “1 porsi tempe mendoan—sudah dibayar untukmu oleh orang baik yang tidak mau disebut.” Orang yang butuh cukup mengambil selembar.
Sore menjelang, Nini Rahyang duduk memandang lalu lintas. “Anak-anak kurir ini seperti laron,” katanya pada Sari, “datang pada cahaya.”
“Kalau begitu,” balas Sari, “tugas kita memastikan cahaya ini tidak padam.”
“Dan memastikan ia tidak menyakiti mata,” sambung Nini, setengah bersenda. “Terang yang sopan.”
Mereka tertawa. Di kejauhan, mentari terbenam, meninggalkan merah di sela-sela gedung. Kota seperti mengambil napas panjang.
.
Namun, hidup tidak selalu akrab dengan garis lurus. Suatu malam, banjir kiriman datang dari selatan. Air meluap dari saluran yang tak cukup besar memeluk derasnya hujan. Warung Munding terendam sebetis, panci dan kompor mengapung seperti perahu kecil. Arya membantu mengamankan barang, Sari menelepon dinas kebersihan, Nini Rahyang mengirim sepuluh termos jahe hangat dari apartemen—ditumpangkan ke mobil tetangganya.
Mundinglaya, yang sepanjang hari mengatur kompor dan selang, duduk di peti kayu, kakinya menggigil. “Maaf ya,” katanya pelan, “warung ini bikin merepotkan.”
“Pak,” potong Arya, suaranya retak karena tercekat, “gak ada kata repot untuk rumah kedua.”
Kata “rumah” menyalakan api kecil di dada yang basah. Di titik paling lelah, justru banyak tangan terulur. Karyawan kantor berdasi muncul membawa palu. Anak-anak SMA datang dengan sepatu kets kotor, memindahkan barang, mengepel lantai. Seorang barista dari kedai kopi seberang menyumbang mesin espresso portabel. “Biar ada minuman yang bunyinya mewah,” katanya, “pahitnya sama, tapi bunyinya menenangkan.”
Tiga hari kemudian, warung kembali berdiri. Lebih rapi, lebih tinggi. Di balok baru tepat di atas tinggi banjir, Ratnasari menempel tulisan tangan: “Kita tidak bisa menahan hujan, tapi kita bisa berjanji untuk saling menjemput.”
.
Hidup sering menyembunyikan jawaban di balik pintu yang tidak kita duga. Minggu itu, perusahaan pengembang tempat Ratnasari bekerja menerima penghargaan: “Inovasi Desain Inklusif.” Di panggung, direktur menyebut namanya, memintanya maju. Lampu panggung menerpa, tepuk tangan menebal. Sari tersenyum. Dalam hati, ia memikirkan Warung Munding, banjir, tangan-tangan yang datang, mesin espresso portabel, pita yang dipotong tanpa pejabat, dan kalimat yang ia tempel di balok.
Selesai acara, di lobi, seorang perempuan menyalaminya. “Saya wartawan. Cerita tentang warung itu, boleh saya tulis?”
“Silakan,” kata Sari, “asalkan tak ada nama saya. Cantumkan saja nama-nama yang berhak disebut: Mundinglaya, Arya, dan… kota.”
Wartawan itu tertawa, menautkan jari-jari di belakang clipboard. “Ini kali pertama saya bertemu humas yang tidak ingin namanya ditulis.”
“Nama saya ditulis setiap akhir bulan di slip gaji,” jawab Sari, ringan. “Nama orang baik tulislah di hati orang lain.”
.
Di suatu Sabtu tanpa hujan, Nini Rahyang datang membawa sebuah bingkisan kecil. “Buat Pak Munding,” katanya. Isinya sebuah jam dinding putih dengan jarum berwarna jingga seperti matahari sore. Pada bagian bawah, ada tulisan kecil yang nyaris tak terlihat: “Waktu yang baik adalah waktu yang dibagi.”
“Wah, Bu,” Mundinglaya menatap jam itu seperti menatap bayi lagi. “Kalau begini, saya gak boleh lagi menutup warung tepat waktu.”
“Boleh,” senyum Rahyang. “Menutup itu perlu. Biar besok ada alasan untuk membuka.”
Mereka memandang jam itu menggantungi paku di dinding. Jarum detik berputar seperti napas yang diatur. Waktu, ternyata, bisa dilihat tenang kalau kita berdiri di ruang yang membuat hati tenang.
.
Pada suatu malam, setelah mengantar paket terakhir, Arya duduk di bangku trotoar. Ia menatap lampu-lampu kota dan tiba-tiba, tanpa alasan jelas, air mata tumpah. Ia ingat ayahnya yang bekerja sebagai sopir bus antarkota, pulang membawa cerita tentang penumpang yang tak punya cukup uang untuk tiket penuh—tetapi tetap diantar sampai depan rumah. “Karena pulang itu hak,” kata ayahnya dulu.
Ia membuka ponsel, menulis: “Kalau kamu capek, istirahat di Warung Munding. Kalau kamu bingung, ajak ngobrol Pak Munding. Kalau kamu takut, minum teh jahe. Kalau kamu sendiri, kamu tidak sendiri di sini.”
Postingan itu dibaca ribuan orang. Ada yang datang besoknya, ada yang menyimpan di hati untuk hari “kalau-kalau”.
Ratnasari, membaca itu di sofa apartemennya, menoleh ke jendela yang memperlihatkan lampu-lampu kota seperti gugus bintang modern. Ia menulis catatan kecil di buku hariannya:
“Kebaikan adalah bahasa resmi sebuah kota yang layak ditinggali.”
.
Setahun berlalu. Warung Munding menjadi ikon kecil yang bukannya menyerap perhatian, melainkan mengembalikannya pada orang-orang kecil yang selama ini menjaga kota tetap bergerak. Ada turis domestik yang sengaja mampir karena membaca tentangnya; ada karyawan bank yang datang diam-diam setelah gagal promosi; ada tukang ojek yang menukar kartu “porsi ditraktir” milik orang yang tak ia kenal; ada pasangan yang bertunangan diam-diam di bangku plastik karena “bagi kami, ini tempat paling jujur di kota.”
Mundinglaya bertambah keriput; senyumnya tetap. Arya membeli motor baru dari tabungan sedikit demi sedikit, tapi ia tetap menyimpan jaket hijau yang tambalannya kini menjadi lencana. Ratnasari dipromosikan menjadi kepala divisi, namun ia tetap menjaga kebiasaan Sabtu paginya dengan Nini Rahyang. Nini, di ulang tahunnya yang ke delapan puluh, meniup lilin sambil berbisik: “Terima kasih, Tuhan, karena memberi saya cukup usia untuk melihat kota belajar menunduk.”
Malam itu, mereka berkumpul di warung: kue bolu sederhana, lilin kecil, tawa yang tidak dibuat-buat. Warung sempit itu mendadak seperti ruang keluarga yang diperbesar. Setelah lagu usai, Nini berucap kata-kata yang pelan tetapi meresap:
“Kalau satu hari terasa gelap,” katanya, “jadilah jendela bagi orang lain.”
Mundinglaya mengangguk, tangannya yang bau minyak mengepal pelan. Arya menatap jam hadiah Rahyang, jarum jingganya menuding angka delapan seperti mengingatkan bentuk tak terputus. Ratnasari menatap satu per satu wajah, menyadari bahwa mungkin inilah definisi sukses: ketika namamu menjadi jembatan, bukan rintangan.
Hujan yang jatuh kemudian terasa berbeda. Ia tidak lagi sekadar air dari langit. Ia adalah pengingat akan pagi-pagi dingin ketika secangkir teh jahe menyelamatkan kewarasan. Ia adalah applause yang halus: “Kalian masih di sini. Kalian masih bertahan. Kalian masih saling menghangatkan.”
Dan jika ada yang bertanya kapan tepatnya semua ini mulai, mungkin tak ada yang bisa menunjuk tanggal. Mungkin jawabannya adalah: saat seorang lelaki menolak uang teh pada hari paling dingin. Atau saat seorang perempuan mengulurkan payung di tangga yang licin. Atau saat seorang nenek memutuskan bahwa pensiun bukan berhenti berguna.
Atau mungkin—dan ini lebih tepat—kebaikan memang tidak pernah mulai atau selesai. Ia hanya berpindah dari satu tangan ke tangan lain, dari satu wajah ke wajah lain, dari satu hujan ke hujan lain.
.
Di dinding warung, tepat di bawah jam hadiah Rahyang, kini ada tulisan baru, ditempel rapi oleh Ratnasari, hurufnya tegas:
“Teruslah mempermudah urusan orang lain, urusanmu biarlah Tuhan yang mempermudah. Teruslah membuat orang lain tersenyum dan bahagia, kebahagiaanmu biarlah Tuhan yang beri.”
Orang-orang membacanya sambil menyesap teh, sambil menunggu hujan reda, sambil menata keberanian sebelum kembali ke jalan. Mereka membawa pulang selembar hangat yang tak bisa dicetak struk, tak bisa diverifikasi lewat OTP, tak bisa diklaim asuransi—tetapi bisa menyelamatkan hari.
Dan di atas sana, matahari—saat ada—tetap melaksanakan tugasnya: memberi hangat tanpa menagih balasan. Bila tertutup awan, ia menitipkan tugas itu kepada kita.
.
.
.
Jember, 13 Juli 2025
.
.
#JejakKebaikan #CerpenUrban #Jakarta #Solidaritas #Empati #WarungMundinglaya #CerpenIndonesia #KompasMingguVibe #Humanity
.
Quotes dalam naskah dan relevan
-
“Nama orang baik tulislah di hati orang lain.”
-
“Kita tidak bisa menahan hujan, tapi kita bisa berjanji untuk saling menjemput.”
-
“Waktu yang baik adalah waktu yang dibagi.”
-
“Kebaikan adalah bahasa resmi sebuah kota yang layak ditinggali.”
-
“Ketika namamu menjadi jembatan, bukan rintangan.”