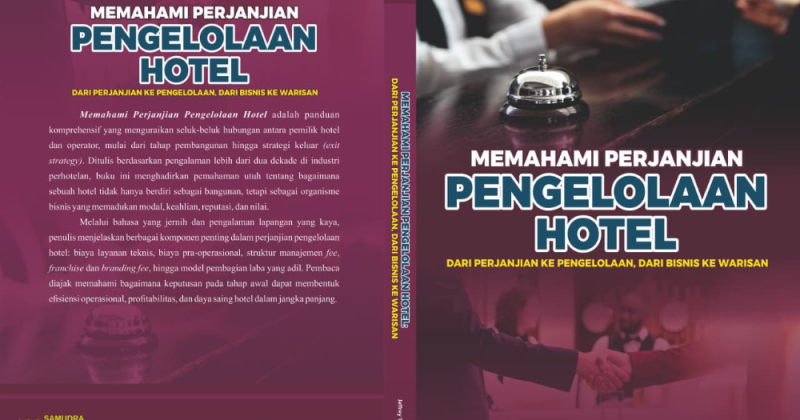Sayap untuk Pulang
“Kesetiaan bukan hanya soal tinggal, tapi tentang berani datang kembali ke diri sendiri—meski kota, karier, dan masa lalu mencoba menahannya.”
Malam itu, di atap sebuah hotel di pusat kota, lampu-lampu dari gedung berkaca memantul pada gelas-gelas tanpa sisa. Angin mengantar suara lalu lintas dari jalan layang—riuh, tapi jauh, seperti memori yang enggan tidur. Jayeng berdiri di tepi, memandang kolam kecil yang memantulkan neon biru “Skyline 48”. Ia baru keluar dari rapat investor—rapat yang mengukur masa depan dengan presentasi tiga belas slide dan dua belas pertanyaan tentang “burn rate” dan “runway.”
Di layar ponselnya, ada pesan dari Sekar. “Kamu pulang kapan, Jayeng? Besok sekolah Aira pentas musik. Kamu janji, ingat?”
Janji itu sederhana, tapi terasa berat di bahunya seperti ransel yang basah.
“Besok, Sekar. Sore. Aku usahakan.”
Kata “usahakan” adalah doa yang sering kalah.
.
Jayeng—nama yang dipilih ayahnya dari kisah Menak Malangan, Jayengrana—dibesarkan di rumah yang merayakan buku dan keberangkatan. Ibunya, Ninggar, membuka kelas musik kecil di ruang tamu, sementara ayahnya, Hamzah, mengelola percetakan brosur hotel dan restoran. Dari dua orang itulah Jayeng belajar bahwa hidup orang kota bertingkat seperti gedung: ada lobi untuk menyambut, ada lift untuk memilih lantai, ada atap untuk merenungkan apa yang terbentang, dan ada ruang-ruang yang tak semua orang diundang masuk.
Kini, di usia tiga puluh lima, Jayeng memegang tiga kartu nama: cofounder platform logistik restoran, partner di usaha kopi waralaba, dan dosen tamu pada program studi kewirausahaan di kampus swasta ternama. Di bio Instagram-nya, baris terakhir: “Tumbuh pelan, tabu untuk tergesa.”
Sekar, pasangannya sejak tahun terakhir kuliah, kini menjalankan studio desain furnitur yang memadukan kayu jati, rotan, dan logam. Ia percaya bahwa rumah bukan sekadar alamat, tetapi juga komposisi bunyi: bunyi sendok, bunyi tawa, bunyi pintu yang ditutup pelan. Sekar belajar lewat kegagalan tender, protes pabrik, dan memo bank. Ia memahami betul, kursi harus tahan diduduki kesedihan dan kegembiraan sekaligus.
Mereka tinggal di apartemen sudut menghadap barat. Dari jendela, senja seperti gula merah yang diserut tipis—manis, cepat larut. Di meja makan, Aira menggambar dengan krayon, sering kali sebuah sayap.
“Kenapa sayap?” tanya Sekar.
“Supaya ayah bisa pulang kalau macet,” jawabnya.
.
Di sisi lain kota, di ruko tiga lantai yang mulai menua, tinggal Umara dan adiknya, Madi. Keduanya keturunan pemilik jaringan toko kain di Pasar Turi, Surabaya, yang merantau ke Jakarta setelah kebakaran memakan gudang besar mereka. Umara memilih jalan yang berbeda: ia mendirikan sekolah khusus persiapan beasiswa luar negeri bagi siswa sekolah negeri—kurikulum disusun rapi, ada kelas esai, kelas riset, dan konsultasi keuangan. Ia bermitra dengan yayasan kecil, bernegosiasi dengan sponsor, dan menahan duka ketika satu demi satu anak didiknya gagal di tikungan paling tak terduga: surat rekomendasi telat, akun portal error, paspor yang tertahan.
Madi, lebih tenang, menjaga toko kain terakhir yang tersisa di Mangga Dua. Ia tahu nama-nama kain seperti kenalan lama: organdi, tulle, brokat. Ia tahu orang kota membeli kain bukan hanya untuk acara, tetapi untuk menyusun citra diri: lulus, tunangan, sidang, promosi. Di punggungnya, hidup berjalan pelan dan berat, seperti gulungan kain yang diangkat sendirian ke lantai dua.
Umara dan Jayeng bertemu di acara panel “Edukasi dan Wirausaha Kota” yang diselenggarakan oleh sebuah bank. Di panggung, mereka berbagi kata-kata yang rapi dan bergigi. Di belakang panggung, mereka berbagi kelelahan yang sama: angka, target, dan malam-malam yang terlalu panjang. Sehabis acara, mereka duduk di warung bakso di gang sempit.
“Aku iri sama yang jualan bakso,” kata Jayeng, memecah baso dengan sendok kecil. “Ada antrian, ada uang tunai, ada pulang.”
“Antriannya juga naik turun,” jawab Umara. “Tapi aku paham maksudmu. Kita ini menukar kepastian dengan kemungkinan.”
“Kemungkinan yang kadang terlalu mahal,” sela Jayeng.
“Tetap saja ada anak yang lolos beasiswa. Dan ada restoran kecil yang buka cabang. Di sanalah kita membayar lunas semua gagal,” balas Umara.
Arah pembicaraan merapat ke kota: tentang rumah susun yang dibangun cepat, jalan layang yang mendahului pohon, anak-anak yang menyeberang trotoar seperti menyeberang tahun. Lalu tentang keluarga. Tentang Sekar yang terus percaya, Aira yang menggambar sayap, Madi yang menjaga kain seperti menjaga nama keluarga.
.
Malam menjelang subuh. Di apartemen, Sekar menunggu di meja kerja, lampu kuning menyinari sketsa lemari untuk klien baru—seorang konsultan properti yang ingin ruang kerja minimalis “yang bisa menenangkan pikiran di antara spreadsheet”. Aneh, pikir Sekar, betapa orang kota membeli furnitur untuk membeli juga ketenangan yang tidak datang dari barang.
Ia membuka e-mail dari Aira’s School: jadwal gladi resik dimajukan. Ia menulis “noted” di reply, lalu menutup laptop. Di dinding ada kalender kain yang ia jahit sendiri. Bulan ini padat: pameran furnitur, tender flat show units, dan rapat asosiasi desainer interior. Ia tersenyum tipis. Dunia memberinya pekerjaan; yang belum tentu dunia memberinya ruang untuk menangis.
“Kenapa kita harus selalu kuat?” tanyanya pada dirinya sendiri—pelan, seperti bertanya pada kursi.
Di sisi lain, Jayeng masih di atap hotel, bersama tiga pendiri startup lain yang bertahan. Kota di bawah seperti papan sirkuit: lampu-lampu yang saling tersambung, arus yang bergerak tak terlihat. Telepon berdering—Hamzah di rumah sakit.
“Bapakmu sesak,” kata Ninggar, suara di seberang pecah. “Dokter bilang perlu observasi. Jangan panik. Bapakmu keras kepala, tapi masih suka menyanyikan ‘Bengawan Solo’ pelan-pelan.”
“Bu, aku ke sana sekarang.”
“Tidak usah. Besok pagi saja. Ibuk kuat. Kamu bawa pulang janji, ya: Aira pentas.”
Kota seperti ikut menahan napas. Jayeng menutup telpon, menatap kolam neon. Ia tahu, ada skor yang tidak ada di presentasi: skor antara yang ia cintai dan yang ia genggam.
.
Pagi berikutnya. Aira berdiri di panggung kecil aula sekolah, rambutnya digelung, memegang biola. Sekar menoleh ke pintu berkali-kali. Umara datang mengantar siswanya mendaftarkan lomba sains. Jayeng belum muncul.
Lagu pembuka dimulai. Aira memainkan not pertama. Sekar menarik napas pendek. Lalu di pintu, Jayeng masuk tergesa, memeluk udara. Ia berdiri di belakang, mengangkat ponsel untuk merekam. Sekar menangkapnya, mengangkat alis: “Kamu datang.”
Jayeng mengangguk, bibirnya bergerak tanpa suara: maaf.
Setelah pentas, Aira memeluk biola—lebih lama dari biasanya. “Ayah, aku main agak fals di bagian tengah.”
“Kamu main paling jujur,” kata Jayeng. “Kota ini harus belajar dari kamu: berani fals sesekali, asal tidak berhenti.”
Sekar tertawa tipis. Tawa yang seperti benang yang tidak terputus.
.
Dua minggu setelah itu, dunia menempuh jarak yang berbeda. Investasi untuk platform logistik restoran cair, tapi dengan syarat pengurangan biaya operasional. “Kita harus menutup tiga kota,” kata Jayeng di pertemuan tim. “Fokus di Jakarta, Bandung, Surabaya. Medan, Makassar, Semarang—kita pamit dulu. Kita jaga tim inti. Kita ramping, bukan menyerah.”
Keputusan itu membuat obrolan Slack dingin. Ada yang paham, ada yang menyalahkan. Di rumah, Jayeng menatap Aira yang tertidur dengan biola di sampingnya. Ia menarik selimutnya pelan. Di dapur, Sekar membuat teh. “Aku juga mau bilang sesuatu,” kata Sekar. “Aku menolak tender flat show units. Fee-nya bagus, tapi kliennya ingin furnitur yang tampak bahagia, tapi dibuat dengan lembur tak berbayar untuk pengrajin. Aku tidak mau. Aku ingin studio kita memproduksi rasa bangga, bukan rasa bersalah.”
Jayeng memeluk Sekar dari belakang. “Kadang menolak adalah cara paling jujur untuk menerima diri,” katanya.
Malam itu mereka bicara tentang uang, rencana menabung untuk sekolah Aira, asuransi Hamzah, dan kemungkinan pindah ke rumah yang lebih kecil. Mereka berbicara seperti dua tukang kayu yang memeriksa papan: mana yang retak, mana yang bisa disambung.
.
Sementara itu, Umara menutup hari dengan kabar baik dan kabar biasa. Kabar baik: seorang muridnya, Dara, lolos beasiswa ke Jepang. Kabar biasa: tiga murid lain gagal karena hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika selain “sistem.” Ia mengirim pesan ke Madi: “Besok pulang malam. Beli nasi goreng di pojokan ya.”
Madi membalas, “Sudah. Tambah acar.”
“Acar itu detail kecil yang menyelamatkan,” balas Umara.
“Kamu seperti kain tulle: kelihatan halus, tapi kuat menahan bentuk,” tulis Madi.
Umara tersenyum. Adiknya lebih puitis dari siapa pun yang ia kenal.
Di sekolah, ia menulis pengumuman: “Kelas tambahan esai gratis hari Sabtu.” Ia tahu, keberhasilan bukan hanya milik yang pandai, tetapi juga milik yang beruntung. Tugasnya: menambah ruas jalan tempat keberuntungan lewat.
.
Suatu sore, hujan turun seperti seseorang yang akhirnya berani menangis. Jalanan banjir setinggi mata kaki, orang-orang berlarian berpayung, ojek berhenti di kolong jembatan. Di studio, Sekar menghentikan kerja. “Sudah, kita pulang,” katanya pada tim. “Besok kita lanjut. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari pulang.”
Anak-anak magang berkemas, satu di antaranya—Dumis—berbisik, “Kak, saya baru kali ini melihat kantor memulangkan kami di jam kerja. Biasanya kami disuruh lembur, bilangnya ‘kesempatan belajar’.”
Sekar menatapnya, pelan. “Belajar itu harus menyelamatkan, bukan menghabisi.”
Di apartemen, lampu sempat padam. Aira menyalakan lilin di meja. Mereka bermain bayangan tangan—avu-avu burung, kelinci, bangau.
“Bangau bisa pulang ke sarang meski badai,” kata Aira.
“Darimana kamu tahu?” tanya Jayeng.
“Dari gambar sayapku,” jawab Aira.
Jayeng menoleh ke Sekar. Dalam cahaya lilin, wajah Sekar terlihat seperti sesuatu yang lama dicari tapi selalu ada: rumah.
.
Beberapa bulan kemudian, angka-angka bergeser. Platform logistik restoran mulai mencatat keuntungan tipis. Waralaba kopi menutup dua gerai mall, tapi membuka satu gerai di rumah sakit swasta—tempat keluarga menunggu kabar, tempat kopi perlu lebih dari sekadar kafein. Studio Sekar merilis koleksi “Bangku Pulang”—kursi dengan sandaran yang sedikit melengkung ke depan, “agar punggung ingat istirahat.”
Hamzah semakin sering duduk di teras rumah, menyanyikan bait-bait “Bengawan Solo.” Tangannya kadang gemetar. Nadanya kadang goyah. Tapi wajahnya damai. “Kamu seperti sungai,” kata Ninggar suatu sore pada suaminya. “Kalau sedang pasang, sabar. Kalau sedang surut, tetap sabar.”
“Dan kamu seperti perahu,” balas Hamzah. “Tidak berisik, tapi tegas menuju.”
Jayeng datang membawa kabar—ia minta izin untuk menjual van tua percetakan. “Buat biaya obat. Bapak tidak usah memikirkan mesin,” katanya. Hamzah menatap mesin cetak yang masih mengilat di sudut. “Mesin ini sudah mencetak banyak menu restoran, undangan, dan brosur lowongan kerja. Ia tahu lebih banyak tentang orang kota daripada berita” —lalu ia tersenyum— “Tapi ia juga tahu kapan berhenti.”
Mereka menandatangani kertas penjualan. Hamzah memeluk mesin dengan pandangan, seolah itu saudara lama.
.
Kota bergerak cepat seperti lift yang tidak menunggu penumpang berlari. Umara mengajak Jayeng menjadi mentor tamu di kelas beasiswa. “Bicara tentang kegagalan yang melatih,” katanya.
Di kelas, Jayeng membuka dengan jujur. Ia menyebut presentasi yang ditolak, email yang tidak terbalas, rekrutmen yang salah, dan kota-kota yang ditinggalkan untuk fokus.
“Kita diajarkan menulis visi-misi,” katanya, “tapi jarang diajarkan menulis ulang. Padahal hidup orang kota adalah kumpulan draf revisi.”
Seorang siswa bertanya, “Kapan kita tahu harus mengubah jalan?”
“Ketika kita tidak lagi mengenali langkah sendiri,” jawab Jayeng.
Dara, yang baru mendapat kabar beasiswa, menunggu di ujung kelas. “Kak, aku takut,” katanya pelan.
“Takut itu lampu kuning,” jawab Umara. “Bukan larangan. Hanya pengingat: pelankan, lihat sekitar, tapi tetap jalan.”
.
Pada suatu pagi Minggu, apartemen mereka seperti panggung teater kecil. Sekar mengelap meja, Aira menempelkan kertas warna-warni di dinding: biru untuk laut, hijau untuk sawah, oranye untuk matahari. Jayeng membuat pancake, gagal di loyang pertama, berhasil di loyang kedua. Di ponselnya, ada notifikasi: investor baru tertarik masuk, dengan syarat akuisisi minoritas di waralaba kopi.
“Kalau diterima, kita bisa menyewa gudang yang lebih baik,” katanya.
“Kalau ditolak?” tanya Sekar.
“Kita tetap jualan kopi, tapi lebih kecil, lebih pas. Tidak semua pertumbuhan adalah naik angka; kadang itu turun hati,” jawab Jayeng.
Sekar mengangguk. “Pilih yang membuat kita pulang lebih sering.”
Mereka duduk bertiga di lantai. Aira membuka kotak krayon. “Ayah, Bunda, gambar sayap bareng, yuk.”
“Kenapa tiga sayap?” tanya Jayeng.
“Biar kita terbang saling menyeimbangkan. Kalau dua, jatuh. Kalau empat, ruwet. Tiga cukup. Aku di tengah,” jawab Aira mantap.
Di luar, kota bangun pelan. Gereja membunyikan lonceng. Masjid di blok sebelah mengaji. Toko roti membuka pintu. Penjual sayur mendorong gerobak. Pagi bergerak dengan kepastian kecil-kecil yang hangat.
.
Beberapa tahun ke depan, siapa yang tahu? Mungkin platform logistik restoran akan diakuisisi, mungkin tidak. Mungkin studio furnitur Sekar memenangkan penghargaan, mungkin tetap menjadi studio kecil yang dipercaya tetangga-tetangga baru. Mungkin Umara membuka cabang sekolah beasiswa di Bandung, Madi menikah dengan penjahit kebaya yang mengerti jatuhnya kain pada lutut. Mungkin Hamzah masih menyanyi, mungkin suara itu tinggal di pita rekaman lawas.
Tapi malam ini, di atap hotel yang dulu jadi tempat Jayeng melipat janji, mereka bertiga berdiri menatap kota. Lampu-lampu masih memantul di gelas, angin masih mengantar suara lalu lintas. Jayeng menggenggam tangan Sekar, Sekar menggenggam tangan Aira.
“Lihat,” kata Sekar, menunjuk langit. Pesawat melintas—lampunya berkedip.
“Aku ingin naik itu,” kata Aira.
“Kemana?” tanya Jayeng.
“Pulang,” jawab Aira, tersenyum. “Selalu pulang. Kemana pun kita terbang.”
Dan entah bagaimana, kata “pulang” malam itu terasa tidak menunjuk alamat. Ia menunjuk keberanian untuk jujur, untuk tidak memaksakan kebahagiaan, untuk memilih menjadi manusia di tengah kota yang menawar kita menjadi angka.
Angin membawa wangi kopi dari bawah, mungkin dari gerai rumah sakit yang kini buka dua puluh empat jam. Di kejauhan, crane pembangunan berhenti mengayun. Kota menutup matanya sebentar; besok ia akan bangun lagi.
“Kesetiaan bukan hanya soal tinggal,” gumam Sekar, mengulang kutipan yang pernah mereka pasang di dinding, “tapi tentang berani datang kembali ke diri sendiri.”
Jayeng mengangguk. Aira menggambar sayap di udara dengan telunjuk, seolah mengikat langit ke hati mereka bertiga.
Dan kita, para pembaca, tahu: di kota-kota yang berlari, pulang adalah ilmu. Ia diajarkan pelan-pelan, di meja makan, di studio kecil, di ruko tiga lantai, di atap hotel—di tempat-tempat yang membuat manusia tak gentar mencintai meski segala hal selalu berubah.
.
.
.
Malang, 23 Oktober 2025
.
.
#CerpenKota #KelasMenengah #KompasMingguStyle #MenakJawa #Wirausaha #Edukasi #Keluarga #FurniturDesain #LogistikRestoran #Reflektif
.
Kutipan Tambahan
-
“Kota adalah cermin: ia memantulkan siapa kita ketika lampu padam.”
-
“Menolak bukan berarti kalah; kadang itu cara paling sopan untuk menang.”
-
“Anak-anak menggambar sayap agar kita ingat: target bukan satu-satunya cara terbang.”
-
“Belajar yang benar adalah pulang dengan wajah yang masih kita kenal.”
-
“Pertumbuhan yang baik selalu menyisakan ruang untuk menaruh kepala di bahu orang yang kita sayang.”