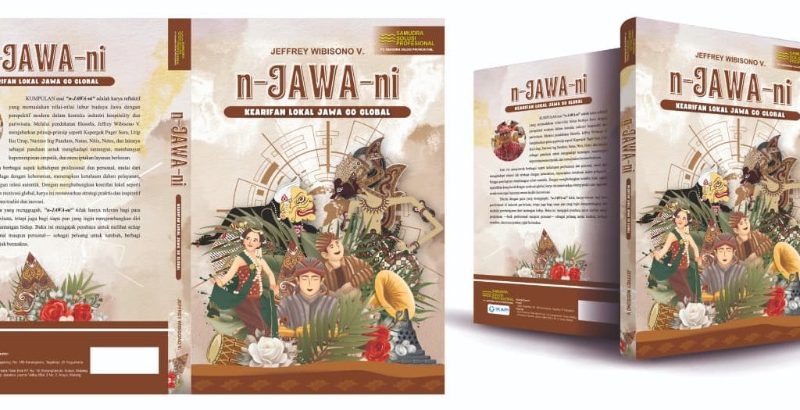Lampu-Lampu Kecil di Ruang Bersua
“Kadang-kadang, kepemimpinan tidak lahir dari panggung besar,
melainkan dari keputusan kecil yang menyelamatkan martabat orang lain.”
.
Bukan Lagi Soal Siapa Paling Hebat
Hujan baru saja reda ketika Jaya turun dari ojek daring di depan Hotel Samodra—gedung kaca sepuluh lantai di jantung kota pesisir yang bising. Jalan raya masih memantulkan lampu-lampu toko yang basah. Di lobi, aroma kopi dan hand sanitizer berkelindan, suara troli koper bersahutan dengan notifikasi aplikasi pemesanan kamar. Malam itu Jaya kembali setelah tiga tahun “mengembara” ke beberapa hotel di Jakarta dan Makassar. Ia menerima telepon dari Agung—teman lamanya yang kini memegang kendali operasional Samodra—dengan kalimat singkat: “Baliklah, Ya. Bantu aku menyalakan lagi lampu-lampu yang hampir padam.”
Jaya tersenyum hambar pada resepsionis yang tampak lelah. Nama di papan nama kecil: Retna. Matanya merah, namun ia tetap menunduk sopan saat menyerahkan kartu akses. “Selamat datang kembali, Kak Jaya,” ucapnya pelan. “Terima kasih,” jawab Jaya, menahan perasaan yang tidak bisa ia beri nama. Rasanya seperti pulang ke rumah yang pernah ia tinggalkan sebelum sempat menjelaskan apa-apa.
Lift melaju ke lantai tujuh. Jaya memandangi bayangannya sendiri di cermin: rambut mulai menipis di pelipis, garis-garis halus di bawah mata, tetapi sorotnya masih menyimpan tenaga yang sama—keyakinan bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi orang yang berani mengulurkan tangan lebih dulu. Ia menghela napas. “Urip iku urup,” gumamnya. Hidup harus memberi cahaya.
Kamar 712 menyambutnya dingin. Ia menaruh ransel, membuka gorden, dan menatap kota yang seperti bergerak sendiri. Samar-samar terdengar adzan Isya dari masjid dekat pasar, beradu dengan musik dari kafe di seberang. Di bawah sana, manusia menegosiasi nasib, satu per satu. Jaya mengambil ponsel dan mengetikkan pesan pada Agung: “Besok jam tujuh aku ke kantor. Tapi malam ini aku ingin berjalan-jalan.”
Ia turun lagi ke lobi, melangkah melewati meja concierge yang catnya mulai mengelupas. Di sudut ruangan, seorang pria bertopi pet menemani anaknya mengerjakan PR. Di sebelah kafe, seorang perempuan paruh baya menunggu jemputan, memeluk tas kain berisi oleh-oleh. Jaya merasakan sesuatu yang lama ia rindukan: suara manusia yang memercikkan cerita. Ia keluar ke teras, menghirup udara basah, dan mulai berjalan.
Kotanya sudah banyak berubah—gedung-gedung baru, mural-mural lebih berani, lampu jalan lebih putih. Tetapi sisa-sisa pandemi masih setia: kios-kios kosong yang tak pernah buka lagi, papan nama kusam, senyum orang-orang yang murah namun seolah menahan napas. Jaya melewati deretan warung soto dan penjual roti bakar, lalu berhenti di jembatan kecil di atas sungai yang airnya mengalir malas. Di sana, ia bertemu seorang laki-laki tua yang sedang menambal payung.
“Payung tak boleh menyerah pada hujan,” kata si tua sambil menyeringai. “Kami hanya menambal, biar ia kuat menghadapi musim.”
Jaya mengangguk, entah pada siapa. Kata-kata itu seperti memantul di dalam kepalanya. Payung, hotel, manusia—semuanya perlu ditambal sekali-kali.
.
Tamu Pertama yang Memberi Tanda
Pagi berikutnya, Jaya tiba lebih awal. Ruang staff masih setengah gelap. Ia menyalakan lampu satu per satu seperti menyalakan lilin di altar. Di meja operasi—begitu ia menyebut meja rapat panjang dengan bekas-bekas kopi dan legenda keputusan-keputusan sulit—ia menunggu tim inti: Retna dari front office, Umar dari engineering, Madi dari housekeeping, dan Kelas dari sales. Nama-nama itu seperti berdering di kepalanya. Mereka dulu anak-anak baru yang bergerak canggung di belakangnya; kini mereka berdiri sebagai tulang punggung yang menahan gedung ini tetap tegak.
Agung datang terakhir, napasnya pendek, telapak tangannya dingin ketika menyalami Jaya. “Terima kasih sudah kembali,” ucapnya. “Samodra butuh kau.”
Jaya hanya mengangguk. “Kita tunggu saja,” jawabnya. “Aku ingin dengar dari mereka dulu.”
Mereka duduk melingkar. Retna membuka buku catatan. Suaranya pelan, tapi mantap. “Okupansi kita bulan ini rata-rata 38 persen. Tamu korporat menurun karena proyek pemerintah ditunda. Review online campur aduk—ada yang memuji staf, tetapi mengeluh tentang kebersihan dan internet.”
Madi menimpali, “Staf kami tinggal separuh. Banyak yang pindah kerja. Kamar-kamar kosong lama, debu gampang menang. Kami butuh pelatihan ulang dan alat yang layak.”
Umar menggerak-gerakkan bolpoin, menatap daftar peralatan yang menua. “Chiller sering mogok. Beberapa lampu koridor rusak. Bahan perbaikan belum ada.”
Kelas membuka laptop, menunjukkan grafik turun-naik seperti detak jantung orang yang cemas. “Pasar berubah. Tamu mau cerita, bukan hanya kasur. Mereka tanya: apa yang membuat Samodra berbeda?”
Jaya mendengar semua tanpa memotong. Ia menandai kata-kata yang mengemuka: cerita, manusia, martabat, pelatihan, alat, internet. Setelah semuanya selesai berbicara, barulah ia mengangkat kepalanya.
“Aku dulu sering salah mengira,” katanya pelan, “kupikir pemimpin adalah orang yang tahu semua jawaban. Ternyata, pemimpin adalah orang yang bertanya cukup lama sampai yang lain menemukan jawaban untuk dirinya sendiri.”
Mereka tertawa kecil, kaku, lalu meleleh. Pagi itu, rencana disusun tanpa banyak jargon. Dalam tiga minggu, mereka akan menambal payung satu per satu: kanal pengaduan tamu dibuat lebih sederhana; kelas kilat kebersihan diadakan tiap sore; jaringan internet di-upgrade dengan kerja sama penyedia lokal; di lobi dipasang sudut “Ruang Bersua”—pojok dengan buku catatan, tanaman hias, dan kopi tubruk yang gratis bagi siapa saja yang ingin duduk sebentar.
“Kenapa ‘Ruang Bersua’?” tanya Agung.
“Karena tamu datang bukan hanya untuk tidur,” jawab Jaya. “Mereka datang untuk merasa dilihat. Kita sediakan ruang itu.”
Sore itu, seorang tamu asing—perempuan berambut keriting dan berkulit sawo matang—datang terburu-buru. Ia mengaku jurnalis lepas yang baru saja kehilangan jadwal penerbangan karena hujan besar. Namanya Wina. Ia tersenyum cemas saat Retna menawarkan minuman hangat di “Ruang Bersua”.
“Terima kasih,” katanya dalam bahasa Indonesia yang lancar. “Aku pikir aku akan tidur di bandara malam ini.”
Wina duduk di sofa abu-abu, membuka laptop, dan mulai mengetik. Retna menatapnya seperti menatap kawan lama. Jaya memperhatikan dari jauh. Ia tak tahu mengapa, tetapi kehadiran Wina memberi tanda: cerita di hotel ini akan bergerak.
.
Retna dan Sepotong Roti di Pagi Buta
Di malam hari, Jaya mengecek sendiri beberapa lantai. Di koridor lantai empat, ia mendapati Madi sedang memunguti tisu yang terselip di bawah karpet. Madi menatap Jaya dengan canggung. “Maaf, Kak,” katanya. “Kami kekurangan petugas shift malam.”
Jaya jongkok, membantu Madi mengangkat sedikit karpet. “Kalau kita angkat sama-sama, lebih cepat kan?” katanya. Madi terkekeh, kaget sekaligus lega. Bukan karena bosnya turun tangan, melainkan karena ia merasa diakui sebagai manusia yang sedang berusaha.
Sekitar pukul dua dini hari, Retna baru selesai mengurus tamu rombongan yang datang terlambat. Matanya lagi-lagi merah, tetapi senyum tak padam. Jaya memintanya duduk, lalu bertanya mengapa ia selalu pulang paling akhir.
“Di rumah ada adik yang sekolah malam,” katanya. “Aku tunggu ia pulang dulu, baru aku tidur.”
“Dari mana kau belajar bertahan seperti itu?”
Retna menatap jendela, menyeka ujung mata. “Dari ibuku. Ia tidak meninggalkan kami waktu ayah pergi. Ibuku bilang, ‘Hidup itu bukan memenangkan lomba, tapi menjaga orang lain tetap bisa berlari.’”
Esok paginya, ketika Jaya turun ke lobi pukul lima, ia mendapati Retna meletakkan sepotong roti mentega di atas meja “Ruang Bersua”. “Untuk satpam yang jaga malam,” kata Retna. “Ia sering lupa sarapan.” Jaya menelan ludah. Ia tahu di situlah inti kepemimpinan: tak ada pengumuman, tak ada foto seremonial, hanya sepotong roti yang diletakkan diam-diam agar orang lain kuat menjalani hari.
Ia menuliskan kalimat di buku catatan lobi: “Terima kasih telah bertahan. Ruang ini ada untukmu.”
.
Umar dan Mesin yang Merawat Manusia
Umar, teknisi yang wajahnya lebih akrab dengan ruang mesin daripada dengan cahaya matahari, menghabiskan tiga hari berturut-turut mengutak-atik jaringan internet bersama petugas provider. “Aku bukan ahli digital,” katanya sambil tertawa pendek, “tapi aku tahu, kalau sinyal macet, orang-orang jadi marah pada yang salah.”
Ketika jaringan akhirnya stabil, Jaya menemukan Umar duduk di tangga darurat, menatap layar ponselnya. Foto anaknya yang baru belajar membaca muncul sebagai wallpaper. “Kau tahu kenapa aku betah di ruang mesin?” tanya Umar tiba-tiba. “Karena mesin itu jujur. Kalau ia macet, ia bilang macet. Manusia… kadang-kadang macet, tapi pura-pura lancar.”
Jaya tertawa kecil. “Sebab itu kita perlu ruang bersua,” jawabnya. “Supaya manusia tidak perlu pura-pura.”
Umar mengangguk, menatap jauh. “Kalau begitu, tugasku memastikan mesin-mesin ini tak menghalangi manusia untuk bertemu.”
Malam itu, pada papan pengumuman staff, Jaya menempelkan kertas kecil: “Terima kasih, Umar. Kau membuat sinyal bukan sekadar bar, tapi jembatan.”
.
Kelas dan Tamu yang Menguji
Kelas, yang sejak awal terlihat paling gelisah, membawa kabar yang mengguncang. “Ada permintaan dari sebuah perusahaan rintisan,” katanya di ruang rapat. “Mereka ingin paket ‘workation’ tiga hari untuk tim inti. Dua puluh orang. Tapi, ada syarat tak biasa: mereka ingin sesi malam di rooftop untuk ‘refleksi hidup’.”
Agung mengernyit. “Rooftop belum siap untuk acara. Listrik tambahan belum ada.”
“Kita siapkan,” sahut Jaya. “Kita tidak hanya menjual kasur. Kita menjual ruang bagi manusia untuk bertanya pada dirinya sendiri.”
Kelas menatap Jaya, campur rasa khawatir dan kagum. “Jika acara ini gagal, mereka akan menulis di mana-mana. Jika berhasil, mereka juga akan menulis di mana-mana.”
“Begitulah hidup,” jawab Jaya. “Kita akan menulis juga—dengan tindakan.”
Tiga hari kemudian, rombongan datang dipimpin seorang perempuan bernama Lela, yang menatap kota seperti menatap peta yang sudah pernah ia jelajahi berkali-kali. Wina—jurnalis yang menginap—diam-diam memperhatikan dari sudut lobi. Ia mengaku sedang menyusun feature tentang “kota-kota yang belajar berdamai setelah badai ekonomi”. Samodra, entah bagaimana, masuk ke dalam rute liputannya.
Malam pertama, rooftop berubah menjadi lingkaran kecil dengan lampu-lampu neon sederhana dan tikar pandan. Jaya meminjam gamelan mini dari sanggar dekat hotel—hanya dua bonang kecil dan kendang—lalu meminta seorang teman memainkan tabuhan pelan sebagai latar. Lela mengajak timnya berbicara. Mereka menertawakan kegagalan, mengakui kebingungan, dan menuliskan mimpi-mimpi pada kertas yang kemudian dilipat menjadi perahu. Perahu-perahu kertas itu diletakkan di mangkuk air, mengapung pelan di bawah langit kota yang pucat.
“Terima kasih,” kata Lela setelah sesi usai. “Kau tidak memberi kami paket wisata. Kau memberi kami ruang untuk jujur.”
Jaya menjawab, “Kami pun belajar jujur. Bahwa kami belum sempurna, tapi ingin menjadi tempat di mana orang bisa bernapas.”
Keesokan harinya, sebuah ulasan muncul di media sosial: “Rooftop kecil di hotel kecil, tapi kami merasa besar karenanya.” Akun itu ternyata milik salah satu anggota tim Lela yang memiliki ribuan pengikut. Di lobi, Retna mengirimkan tautan ke grup internal. Malam itu mereka merayakan dengan teh manis dan roti keju. Tidak ada spanduk, tidak ada terompet, hanya percakapan yang lebih ringan dan mata yang lebih berkilau.
.
Wina Menulis, Kota Menjawab
Wina mendekati Jaya di “Ruang Bersua”. “Aku ingin menulis tentang hotel ini,” katanya. “Boleh aku mengamati lebih lama?”
“Tentu,” jawab Jaya. “Asal kau juga mau mendengar cerita kami yang tidak selalu indah.”
Wina tertawa. “Cerita yang tidak indah justru membuat dunia terasa lebih jujur.”
Ia mengikuti Madi yang sedang mengajari staf baru membersihkan kamar tanpa terburu-buru—menyapu dari pojok terdalam, mengganti seprei seperti melipat awan, meletakkan handuk sebagaimana orang menaruh doa. Ia mencatat perbincangan Umar dengan petugas listrik tentang kabel tua yang mesti diganti. Ia duduk bersama Retna ketika resepsionis itu menenangkan tamu yang kehilangan dompet, membawa air hangat, dan membantu melapor ke polisi.
Pada suatu sore, Wina meminta Jaya berjalan bersamanya menyusuri kota. Mereka melewati pasar ikan, terminal angkot, dan gang sempit yang tiba-tiba membuka diri menjadi lapangan kecil dengan anak-anak bermain. “Aku lahir di kota ini,” kata Wina. “Lalu pergi. Aku pikir kota ini akan berhenti menunggu. Ternyata ia masih menyimpan tempat untukku.”
Jaya menatapnya. “Kota tidak punya hati, katanya. Tapi manusia yang tinggal di dalamnya saling mengembalikan hati satu sama lain.”
“Dan di hotelmu,” Wina melanjutkan, “orang-orang itu tampak saling mengembalikan hati mereka.”
Jaya diam. Ada bagian dari kalimat itu yang menyalakan sesuatu di dalam dadanya: harapan yang sederhana.
.
Krisis yang Menguji Janji
Tak ada cerita yang melaju tanpa hambatan. Pada malam ketiga setelah rombongan Lela pergi, seorang tamu mengirimkan keluhan pedas di platform ulasan: air panas tidak berfungsi, kamar berbau lembap, pelayanan lambat. Akun itu memiliki pengikut puluhan ribu. Retna yang membaca pertama kali tampak pucat.
“Kita selesaikan di sini,” kata Jaya. Ia mengajak tim memeriksa kamar yang dimaksud. Ternyata pipa air panas tersumbat oleh kerak karena lama tidak dipakai. Umar mengerjakan perbaikan butuh waktu tiga jam. Jaya menulis pesan pribadi pada tamu tersebut, meminta izin untuk bertemu langsung.
Mereka duduk di kafe hotel. Tamu itu, seorang pengusaha kecil bernama Rengga, mengangkat alis melihat Jaya datang bersama Retna dan Umar. “Saya hanya ingin tidur dengan tenang,” katanya ketus.
“Kami mengerti,” jawab Jaya. “Kami tidak meminta Anda memaafkan. Kami ingin memperbaiki.”
Ia tidak menjanjikan voucher atau potongan harga dulu. Ia meminta Rengga menceritakan kartu hidupnya—perjalanan bisnisnya, ketakutannya, alasan ia marah ketika air panas tidak menyala. Rengga bercerita: ia baru saja kehilangan tender besar, istrinya menunggunya di rumah dengan kabar hamil muda. Ia takut pulang sebagai orang gagal.
Retna menawarkan teh hangat dan menaruh roti kecil di meja. “Saya pun pernah takut pulang,” katanya pelan. “Karena di rumah ada adik yang menunggu.” Kata-kata itu mengalir seperti selimut. Rengga menghela napas panjang.
Ketika mereka berpisah, Rengga berkata, “Saya akan mengedit ulasan saya. Yang saya butuhkan memang bukan air panas, tapi kepala dingin. Terima kasih.”
Pagi berikutnya, ia menulis: “Saya datang dengan amarah, pulang dengan tenang. Hotel ini mungkin tidak sempurna, namun orang-orangnya berusaha menghormati kita sebagai manusia.”
.
Lomba Kecil Melawan Diri Sendiri
Seminggu kemudian, Kelas mengusulkan “Lomba Kecil” untuk seluruh staf. “Bukan lomba siapa yang paling hebat,” katanya. “Tapi siapa yang mengalahkan dirinya sendiri.”
Aturannya sederhana: setiap staf menuliskan satu kebiasaan kecil yang ingin diperbaiki dalam tujuh hari—datang tepat waktu, menyapa tamu sebelum ditanya, memeriksa kabel sebelum lampu mati, menyisakan uang untuk sedekah kecil di kotak lobi. Tidak ada hadiah besar. Hanya kartu ucapan dan potret polaroid yang ditempel di dinding “Ruang Bersua”.
Hasilnya mengejutkan. Kehangatan di mata orang-orang meningkat. Tamu-tamu mulai meninggalkan catatan manis—bukan hanya bintang di aplikasi, melainkan tulisan tangan yang menyebut nama-nama: “Terima kasih, Madi, sudah memperbaiki lampu kamarku.” “Retna, kamu membuat perjalanan ini terasa ringan.” “Umar, semoga anakmu cepat pintar baca.”
Agung, yang sejak awal lebih sering menunduk pada spreadsheet, mulai tersenyum lebih sering. “Aku lupa bagaimana rasanya percaya,” katanya pada Jaya suatu malam di rooftop. “Sekarang aku ingat lagi.”
Jaya menatap kota yang berkilat. “Kita tidak sedang bikin keajaiban,” jawabnya. “Kita hanya menyalakan lampu satu per satu.”
.
Masalah Lama yang Datang: Hutang
Namun, ada satu hal yang tidak bisa dinyalakan hanya dengan niat: hutang. Samodra masih memikul cicilan masa lalu. Pemasok menagih. Bank mengingatkan. Agung memegang kepalanya. “Kalau ini tidak ada jalan keluar,” katanya, “semua yang sudah kita bangun bisa patah.”
Jaya menarik napas panjang. Ia mengajak tim inti berkumpul. “Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan semuanya sekaligus,” ucapnya. “Tapi kita bisa melakukan satu hal: jujur.”
Mereka mengundang para pemasok dan perwakilan bank datang ke hotel—bukan untuk rapat formal, melainkan untuk temu wicara di “Ruang Bersua”. Mereka menjelaskan kondisi, menunjukkan data okupansi yang mulai merangkak naik, memperlihatkan ulasan tamu yang semakin hangat. Jaya berbicara tanpa retorika, hanya dengan kalimat-kalimat pendek yang bisa ditanggung oleh hati manusia.
“Beri kami delapan bulan,” katanya. “Kami akan cicil dengan debit yang hidup. Kami tak ingin lari. Kami ingin bertahan.”
Seorang pemasok tua, yang dahulu marah-marah di telepon, menatap Jaya lekat-lekat. “Kau mengingatkanku pada anakku,” katanya. “Ia juga baru belajar jujur pada dirinya sendiri.” Ia mengangguk pelan. “Baik. Delapan bulan.”
Bank tidak semudah itu, tetapi ruang untuk bernegosiasi tiba-tiba muncul ketika Wina menerbitkan tulisan panjangnya tentang Samodra: “Hotel yang Menyalakan Lampu Kecil”. Tulisan itu beredar luas, bukan karena gaya bahasanya, tetapi karena ia menangkap sesuatu yang orang-orang rindukan: tempat yang menaruh manusia lebih dulu.
Telepon Kelas berdering-dering. Perusahaan kecil, komunitas seni, lembaga pendidikan—semua ingin mengadakan acara di rooftop, di lobi, di “Ruang Bersua”. Bank, yang membaca pergerakan itu, pelan-pelan mengendurkan kaku. “Kami percaya rencana kalian bukan ilusi,” kata pejabat kredit yang datang meninjau. “Bukan karena pemasukan, tapi karena kepercayaan orang-orang yang nyata.”
.
Jatuh Hati pada Kota yang Tak Sempurna
Di tengah hiruk-pikuk, Jaya menemukan dirinya sering kali duduk di “Ruang Bersua” menjelang malam, memandangi dinding yang kini penuh polaroid dan catatan. Ia mengingat pertemuan pertama dengan lelaki tua penambal payung. Ia menyesal tidak sempat menanyakan namanya. Namun mungkin memang demikian cara kota bekerja: orang datang memberi kalimat, lalu menghilang, menyisakan jejak yang bisa menuntun orang lain pulang.
Suatu malam, Wina mendekat sambil membawa dua gelas teh jahe. “Aku akan pergi besok,” katanya. “Ada kota lain yang menunggu.”
Jaya menatap gelombang kecil di permukaan minuman. “Terima kasih sudah membuat kata-kata menjadi jembatan,” ujarnya.
“Bukan aku,” jawab Wina. “Kalian yang menyediakannya. Kota ini, hotel ini, orang-orangnya. Aku hanya menulis karena tidak ingin lupa rasanya.”
Ia ragu sejenak, lalu menambahkan, “Di sini aku mengerti, kadang-kadang yang kita perlukan bukan pahlawan, melainkan seseorang yang berani meminta maaf lebih dulu.”
Mereka tertawa. Malam seperti menutup pintu dengan lembut.
.
Pagi Terbuka, Lampu Tetap Menyala
Delapan bulan kemudian, angka-angka mulai masuk akal. Okupansi melewati 70 persen pada akhir pekan, 55 persen pada hari kerja. Paket “workation” menjadi produk andalan. “Ruang Bersua” menyumbang reputasi yang tak bisa dibeli. Para pemasok, yang dulu marah-marah, kini datang membawa risalah menu baru. Bank mengirimkan pesan singkat: “Terima kasih atas komitmen Anda.” Di dinding lobi, catatan berbunyi: “Jika tindakanmu membuat orang lain bermimpi lebih, belajar lebih, berbuat lebih, dan menjadi lebih—kau pemimpin.” Kalimat itu ditulis Retna dengan spidol hitam, tanpa menyebut siapa pun pengutipnya.
Tapi hidup tidak pernah tuntas. Pada suatu pagi, kabar buruk datang: Madi jatuh saat membersihkan kaca luar. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan kaki terkilir parah. Jaya bergegas menyusul. Di ruang perawatan sederhana, Madi terbaring dengan mata memerah.
“Aku bodoh,” katanya. “Aku lupa mengunci pengaman.”
“Tidak,” jawab Jaya, memegang bahunya. “Kau lelah. Kita yang salah karena membiarkanmu kelelahan.”
Ia menatap Retna yang duduk di kursi, menahan tangis. Umar berdiri di pojok, memegang topi. Kelas mengirim pesan: “Aku akan mengatur shift. Pekerjaan Madi kami bagi.” Agung datang, membawa tanda tangan persetujuan cuti berbayar penuh.
Sore itu, Jaya menulis pengumuman internal: “Kecepatan bukan kehebatan. Keselamatan adalah martabat. Setelah ini, semua pekerjaan berisiko harus dikerjakan berdua.” Ia menempelkan pengumuman itu di ruang staf, lalu menambahkan kalimat kecil yang menghangatkan: “Terima kasih, Madi, sudah mengingatkan bahwa kita ini manusia.”
.
Festival Kecil, Doa Panjang
Ketika Madi pulih, Samodra mengadakan “Festival Kecil”—sehari untuk merayakan kerja tanpa membuat kebisingan tidak perlu. Ada sesi membaca puisi di “Ruang Bersua”, pameran foto polaroid, workshop melipat perahu kertas di rooftop, dan makan malam sederhana dengan menu rumahan: sayur lodeh, ikan bakar, sambal bawang. Para tamu, tetangga sekitar, dan pemasok diundang. Di panggung kecil, Jaya mengajak semua berdiri sejenak.
“Kita bukan hotel terbesar,” katanya, “dan mungkin tidak akan menjadi yang paling mewah. Tapi kita bisa menjadi tempat di mana orang merasa layak.”
Ia memandang satu per satu wajah yang menatapnya: Retna dengan mata yang tetap merah namun berani, Umar dengan senyum yang jarang, Kelas yang memeluk folder event seperti memeluk anak kecil, Madi yang bertongkat tapi tertawa, Agung yang tak lagi terlihat sendirian. Ia ingin berkata banyak, tapi memilih kalimat yang paling ia percaya.
“Urip iku urup,” ucapnya. “Hidup adalah menyala. Dan cahaya lebih terang ketika dibagi.”
Malam itu, di bawah langit yang kebetulan cukup bersih, mereka menyalakan lampion kertas. Lampion-lampion itu terbang pelan, membawa catatan-catatan kecil: Terima kasih telah bertahan. Maaf atas marah yang tak perlu. Mari pulang lebih jujur. Anak-anak tetangga tertawa mengejar bayangan di tanah. Beberapa tamu mengangkat ponsel, merekam, tetapi sebagian besar hanya menatap dengan mata yang tidak ingin berkedip.
Wina mengirim pesan dari kota lain: “Kalian mengingatkanku, Indonesia adalah kumpulan ruang bersua yang menunggu dinyalakan.”
.
Apa yang Tersisa Setelah Semua Ini
Musim hujan kembali. Jaya berjalan sendiri di jembatan yang sama tempat ia dulu bertemu penambal payung. Kali ini ia yang menambal—bukan payung, melainkan janji pada dirinya sendiri agar tidak lagi kabur dari hal-hal yang menuntut kejujuran. Di kantongnya, ia menyimpan catatan kecil dari buku lobi: tulisan tangan seorang tamu yang pernah datang bersama rombongan Lela.
“Terima kasih telah menyediakan tempat kami bertemu dengan diri sendiri.”
Jaya tersenyum. Ia tahu, suatu hari ia akan lelah lagi, ragu lagi. Dunia kerja, kota, dan manusia terlalu rumit untuk dijinakkan dengan satu pidato. Namun ia juga tahu, setiap kali lampu-lampu itu padam, ada orang lain yang akan menyalakannya. Kepemimpinan bukan tentang satu orang paling terang, melainkan tentang banyak orang yang rela menjadi sumbu. Di sanalah ia akan kembali menaruh tenaganya, setetes demi setetes.
Di lobi, Retna menyambutnya dengan sepotong roti—kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. “Untuk pagi yang panjang,” katanya.
“Untuk pagi yang ingin kita jaga,” jawab Jaya.
Ia duduk di “Ruang Bersua”, membuka buku catatan, dan menulis sebuah kalimat yang ingin ia ingat ketika hari-hari sukar datang: “Kepemimpinan adalah seni menjaga orang lain tetap bisa berlari.” Lalu ia menutup buku, berdiri, dan mulai bekerja lagi—menyalakan lampu-lampu kecil yang membuat orang-orang merasa pulang.
.
“Tak semua lampu mampu menerangi jalan, tapi setiap cahaya, sekecil apa pun, bisa membuat hati orang lain merasa pulang.”
.
.
.
Jember, 12 Agustus 2025
.
.
#CerpenIndonesia #KompasMingguStyle #Kepemimpinan #Hospitality #FilosofiJawa #UrbanStory #RuangBersua #InspiringFiction