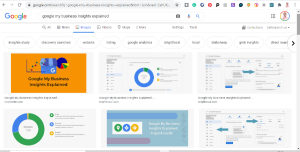Pion yang Menguasai Diri
“Jangan jadi raja di mulut, tapi budak di diri. Kuasai dirimu—baru kuasai langkahmu.”
.
Hujan Jakarta turun seperti butir-butir kaca yang rontok dari langit, pecah kecil-kecil di aspal Senen yang licin. Di depan kios fotokopi yang lampunya menggigil, Jayeng berdiri menunggu bus malam terakhir ke arah Grogol. Jaket hitamnya masih basah di bahu kiri, menggelantung seperti sayap burung yang malas berkibar. Di saku jaketnya, sebuah pion catur plastik yang ia temukan dua minggu lalu di halte Rawasari, ia jadikan gantungan kunci. Pion kecil itu sekarang memantulkan lampu jalan, sementara bayangannya yang panjang menukik ke trotoar seolah berubah menjadi raja: menjulang dan bermahkota.
“Lihat, Din,” katanya waktu itu pada adik perempuannya melalui video call. “Kecil begini, tapi bayangannya bisa seperti raja.”
Adaning, adiknya, tertawa di seberang Jember. “Kamu itu selalu nemu makna di benda aneh, Mas. Tapi bagus juga. Biar kamu ingat, kamu bisa jadi apa saja.”
Malam ini, kata-kata itu menghangatkan telinga Jayeng. Bus datang, wiper kaca depan menyapu air seperti tangan raksasa yang malas. Jayeng naik, duduk di kursi paling belakang, dan untuk pertama kali dalam seminggu ia membiarkan kepalanya mimpi sebentar.
.
Keesokan paginya, jam lima, ia sudah berdiri di lobi Hotel Kartika—hotel menengah yang menjadi tempatnya bekerja sebagai petugas front desk shift pagi. Jakarta belum sepenuhnya bangun. Lampu-lampu lobi masih berwarna kuning lembut, aroma kopi mengalun dari pantry, dan seorang cleaning service bernama Maya sedang memoles meja marmer dengan kain mikrofiber yang seperti sayap kelabu.
Maya—lelaki kurus berusia empat puluhan yang semua orang panggil Maya karena wajahnya yang teduh—menyapa, “Selamat pagi, Jayeng.”
“Pagi, Ya,” balas Jayeng. “Udara masih dingin ya.”
Maya tersenyum. “Dingin di luar gampang diatasi, Ding. Dingin di hati yang sulit. Ngopi dulu.”
Mereka tertawa. Jayeng suka percakapan ringan dengan Maya. Lelaki itu punya kebiasaan melempar pitutur dengan nada main-main. Ucapannya seperti biji yang ia lemparkan begitu saja; siapa tahu ada tanah yang mau menyerap dan menumbuhkannya.
Sistem komputer front desk menyala. Jayeng mengecek daftar check-out, daftar booking, dan catatan tamu VIP. Hari ini akan ada rombongan peserta konferensi startup—anak-anak muda bawa laptop, jaket hoodie, dan ide sebanyak awan. Manager operasional, Madi, sudah berkeliling sejak subuh, menyuruh ini-itu, suaranya datar seperti penggaris.
“Pastikan welcome drink siap jam delapan,” kata Madi, tanpa menatap. “Dan jangan sampai ada tamu yang nunggu lama di check-in, kemarin review kita turun 0,2 poin.”
Jayeng mengangguk. “Siap, Mas.”
Madi beranjak, sepatu kulitnya mengetuk lantai seperti metronom. Jayeng menatap punggung lelaki itu, merasakan sesuatu menggelitik di dadanya. Madi bukan orang jahat, hanya keras pada standar—keras pada diri sendiri pertama-tama, lalu menetes ke orang lain. Mungkin karena itu Jayeng tak terlalu sakit hati kalau sewaktu-waktu teguran itu terdengar tajam.
Pada pukul tujuh, lobi sudah padat. Check-out dari tamu lama, check-in early dari peserta konferensi, telepon berdering, email berdenting. Jayeng bergerak seperti bidak catur yang tahu kapan harus maju, kapan menahan diri. Senyumnya tetap, kata-katanya rapi. Ia ingat pitutur simbah di Jember: “Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana.” Harga dirimu dari ucapanmu, raga dihormati dari bagaimana kau menampilkan diri. Maka ia memilih kata lebih hati-hati daripada memilih dasi.
Sekitar jam sepuluh, listrik padam sepersekian detik lalu menyala lagi—sekedip mata yang membuat semua orang di lobi menoleh. Jayeng melihat lampu gantung berayun pelan. Di belakang, Maya sudah berdiri, memandang ke atas.
“Kamu lihat?” tanya Maya, berbisik.
“Lihat.”
“Kalau ada perubahan kecil, biasanya ada gelombang besar di belakangnya. Siap-siap saja.”
Jayeng tertawa. “Kamu ini, Ya. Filosof kopitiam.”
Tapi benar saja, dua jam kemudian, hujan yang tadi menggantung turun dengan deras. Jalan depan hotel berubah menjadi sungai kecil. Kabar masuk dari F&B: beberapa supplier terjebak banjir, stok welcome drink habis. Dari housekeeping: dua kamar di lantai tiga bocor di sudut jendela, air berlari kecil di dinding. Dari engineering: genset sempat ngadat waktu listrik berkedip.
Madi mendatangi front desk dengan wajah yang baru kali ini terlihat sedikit tegang. “Jayeng, kamu handle tamu yang komplain soal banjir di depan. Sampaikan ada shuttle kecil untuk antar ke halte terdekat. Gratis. Singkat, jelas.”
“Siap.”
“Dan minta tolong Maya koordinasi sama housekeeping untuk penampakan lobby. Jangan sampai terkesan berantakan.”
“Baik.”
Jayeng bergerak. Ia memanggil driver yang lagi standby, memesan dua mobil tambahan dari mitra transportasi online dengan akun perusahaan untuk kebutuhan darurat. Ia menemui tamu-tamu yang resah dengan suara rendah, menenangkan, menawari payung, handuk tangan, teh panas. Dalam kekacauan kecil itu, Jayeng merasa tenang seperti bidak yang menemukan jalurnya: maju satu-satu tapi pasti.
Menjelang sore, badai reda. Namun masalah sebenarnya baru datang: kabar menyusul bahwa ballroom—ruang utama konferensi—kebanjiran setinggi mata kaki karena saluran tersumbat. Panitia konferensi sudah di jalan menuju hotel; jadwal dimulai pukul lima. Wajah Madi pucat, bibirnya menipis.
“Ini gawat,” katanya singkat. “Engineering bilang butuh tiga jam buat beresin. Kita cuma punya dua.”
Jayeng menatap lantai, kemudian menatap ke arah restoran yang baru saja sepi karena jam makan siang lewat. Ruangan resto cukup luas, ada panggung kecil untuk band, akustiknya lumayan. Ia mengangkat tangan, merasakan jari-jarinya dingin tapi kepalanya jernih.
“Mas Madi,” ia berkata. “Bagaimana kalau sesi pembuka konferensi dipindah ke restoran? Kita alihkan bahan presentasi ke layar portabel. Kursi bisa dipindah. Ballroom kita kejar untuk sesi kedua.”
Madi mengernyit. “Resto? Kapasitasnya?”
“Seratus lima puluh. Sesi pembuka audiensnya pun tidak full; berdasarkan rundown kemarin, hanya undangan, keynote, panitia. Kita bisa set hingga dua ratus dengan tambah kursi banjar. Kalau butuh, area lounge kita jadikan overflow.”
Maya yang entah sejak kapan berdiri di belakang mereka menimpali, “Saya bisa minta satpam bantu geser kursi. Housekeeping siapkan taplak dan signage. Kalau bergerak sekarang, jam empat selesai set.”
Madi memandang mereka bergantian seperti melihat papan catur yang mendadak hidup. Ia mengangguk sekali, cepat. “Eksekusi.”
Maya berlari kecil; Jayeng menenteng HT, suaranya mengalir. “Tim, kita pindah set ke restoran. Layout classroom. Signage ‘Opening Session’ dipindah. AV, siapkan layar portabel dan mic clip-on. F&B siapkan kopi gelombang pertama jam empat kurang.”
Begitulah: kursi-kursi berderit, meja bundar didorong, taplak putih terentang seperti gulungan ombak. Jayeng memegang ujung-ujung yang longgar, mengikatnya dengan penjepit, merapikan lipatan, menempelkan signage yang ditulis cepat dengan spidol besar. Maya menyapu lobi yang basah dengan kain tebal, semprotan disinfektan menari di udara seperti hujan kecil.
Jam empat lewat sepuluh, panitia konferensi datang dengan wajah panik. Jayeng menyambut di depan, menunduk sedikit, kemudian menunjukkan layout darurat.
“Kita pindah ke restoran untuk sesi pembuka,” katanya, nada tenang. “Ballroom sedang dibersihkan. Diperkirakan siap untuk sesi kedua.”
Ketua panitia—lelaki muda berkacamata—menarik napas. “Oke, Mas. Terima kasih, ini penyelamat. Kami ikut arahan.”
Pada jam lima tepat, sesi pembuka berlangsung. Lampu hangat restoran membuat suasana jadi intim, suara presentasi mengalun melalui speaker. Di luar, engineering bekerja seperti prajurit: menyedot, menyeka, memungut daun-daun yang menyumbat saluran. Pada jam tujuh, mereka melapor: ballroom siap. Sesi terakhir malam itu pindah ke sana, lebih luas, lebih megah. Para peserta memotret, mengunggah ke media sosial dengan caption: “Banjir tak menghalangi ide. Salut untuk hotel yang sigap.”
Madi berdiri di samping Jayeng di belakang ballroom. “Kamu cepat,” katanya pelan. “Aku lihat kamu tidak panik, padahal tadi…”
Jayeng tersenyum, menatap panggung. “Saya teringat pitutur, Mas. Ngeli nanging ora keli. Ikut arus tanpa hanyut. Air membawa kita, tapi kita tetap menentukan arah.”
Madi menatap wajah Jayeng, seolah menemukan sesuatu yang sebelumnya ia lewatkan. “Besok pagi, jam sembilan. Datang ke ruanganku.”
Kalimat itu seperti sebuah buah yang masih menggantung—kita belum tahu manisnya atau asamnya.
.
Di kamar kos sempitnya di Grogol, Jayeng merebahkan tubuh. Kipas angin tua memecah udara dengan suara serupa helikopter di kejauhan. Ia video call Adaning. Wajah adiknya muncul, berkerudung santai, ada suara penggorengan dari dapur.
“Mas, kamu kelihatan capek,” kata Adaning.
“Capek enak.” Jayeng menceritakan kejadian hari ini. Adaning mendengarkan, matanya berbinar seiring cerita bergulir.
“Kamu tahu, Din,” kata Jayeng di akhir. “Aku baru paham, yang kita kuasai ternyata bukan keadaan. Yang kita kuasai adalah diri. Dari situ, keadaan ikut mengikuti.”
Adaning mengangguk. “Kuasai diri, kuasai langkah. Kamu bilang itu dulu waktu aku takut ikut lomba pidato.”
“Dan kamu juara dua, kan?”
“Juara satu.” Adaning tertawa. “Kamu rong puluh persen mengurangi pencapaianku.”
Jayeng juga tertawa. Tawa yang menipiskan lelah.
Sebelum tidur, ia menatap gantungan kunci pionnya di meja. Bayangannya jatuh di dinding, memanjang hingga tepi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Jayeng bermimpi: ia berjalan di antara deretan pion yang bergerak satu-satu, dan di ujung sana, bukan mahkota yang ia lihat, tetapi cermin. Di cermin itu, ia melihat versinya yang sama—tidak bertambah tinggi, tidak bertambah gemuk—hanya lebih tegap, matanya lebih terang.
.
Pukul sembilan, ruangan Madi wangi kopi dan kertas baru. Di meja, ada berkas-berkas dengan sticky note warna-warni. Madi menandai satu, lalu menatap Jayeng.
“Kamu sudah berapa lama di front desk?”
“Tiga tahun delapan bulan, Mas.”
“Pernah terpikir melompat ke operasional?”
Jayeng terdiam sesaat. “Pernah. Tapi saya… ya, masih belajar.”
Madi menyandarkan punggung. “Kamu tahu, dalam catur, pion yang sampai ujung bisa promosi. Itu bukan sulap. Itu karena pion memilih untuk maju terus, melintasi bahaya, dan saat tiba waktunya, dia berubah. Kemarin, kamu promosi sebentar—bukan jabatan, tapi cara berpikir.”
Jayeng menahan senyum yang tiba-tiba ingin keluar. “Terima kasih, Mas.”
“Ada posisi duty manager malam yang kosong dua bulan lagi. Kalau kamu siap, aku ingin kamu ikut jalur seleksi internal. Bukan hadiah. Kamu tetap akan tes, presentasi, dan turun langsung. Tapi mulai sekarang, aku minta kamu bayangan dulu. Setiap malam, bergiliran, kamu ikut duty manager belajar mengatur operasi lintas departemen.”
Jayeng mengangguk. Ia bisa merasakan degup di dadanya—campuran takut, girang, dan tekad. “Saya siap belajar.”
Madi mengulurkan tangan. “Oke. Mulai malam ini.”
Keluar dari ruangan itu, Jayeng bertemu Maya yang membawa troli pembersih. “Wajahmu seperti habis menelan matahari,” kata Maya. “Ada kabar baik?”
Jayeng mengerling. “Ada. Aku mau jadi bayangan dulu sebelum jadi pion yang sampai ujung.”
Maya tertawa. “Ingat pitutur simbah: Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Biar tidak mudah takjub, tidak mudah kaget, dan tidak sombong.”
“Siap, Ya.”
Malam tiba. Jayeng berdiri di belakang duty manager senior, Umar, yang semua orang panggil Madi—eh, bukan, yang ini Umar Madi, nama lengkapnya memang begitu; orang kantor menyingkatnya jadi Madi—tapi kita ceritakan begini: di shift malam, duty manager yang membimbing Jayeng bukan Madi yang tadi manager operasional, melainkan seorang lelaki lain bernama Umar Madi yang lebih tua, tenang, dan suka menggumamkan syair lama—adaptasi nama dari kisah Menak yang berkelindan dalam darah urban.
“Dengar, Jayeng,” kata Umar Madi, “operasional itu bukan sekadar memadamkan api. Itu membaca kemungkinan api sebelum ia muncul.”
Mereka berkeliling: mengecek back of house, suhu chiller, buku log security, night audit, key control. Di laundry, mesin berputar seperti planet, memeras air dari sprei yang akan jadi putih lagi. Di gudang, kardus-kardus berbaris seperti pasukan menunggu komando.
“Kalau kamu mau jadi duty manager yang baik,” lanjut Umar Madi, “belajar betul-betul dari housekeeping. Dari mereka kamu memahami detail. Dari kitchen, kamu belajar tempo. Dari engineering, kamu mengerti batas. Dari security, kamu tahu keberanian.”
Jayeng mencatat dalam kepalanya, setiap kalimat seperti paku yang ia tancapkan pelan-pelan di papan memori.
Malam-malam berikutnya, Jayeng menjalani pola yang sama: siang front desk, malam beberapa kali seminggu bayangan duty manager. Tubuh lelah, tapi ada semacam api yang memelihara. Ia belajar menegur staf tanpa mematikan semangat, belajar menenangkan tamu yang mabuk tanpa memanggil polisi, belajar memberikan keputusan kecil yang berdampak besar. Kadang Madi (manager operasional) mengajukan pertanyaan yang membuatnya berkeringat: “Kenapa kamu pilih buka outlet kopi tambahan di lobi saat jam sarapan penuh?”—dan Jayeng harus menjawab dengan analisis sederhana: arus tamu, kecepatan transaksi, konversi upsell.
Di sela itu, ia masih sempat menelepon Adaning, mengirim uang bulanan untuk ibu di Jember, dan sesekali pulang naik kereta untuk memeluk rumah. Di meja ruang tamu, papan catur plastik selalu “standby” karena ibu suka main dengan tetangga. Satu malam, ibu berkata sambil menggeser kuda: “Hidup itu bukan soal bisa loncat jauh. Yang lebih sulit itu menunggu giliran melangkah.”
“Seperti bidak?” tanya Jayeng.
“Seperti bidak. Tapi kalau bidak sabar dan percaya diri, di ujung dia bisa jadi apa saja.”
Kata-kata itu menempel seperti stiker di kaca hati Jayeng.
.
Suatu Sabtu dini hari di bulan berikutnya, hotel kedatangan tamu penting: seorang tokoh publik yang mendadak meminta early check-in dan privasi ketat. Media ramai di luar, paparazzi mengendap di lobi. Duty manager malam itu sakit; Madi menunjuk Jayeng sebagai acting.
“Ini ujianmu,” kata Madi. “Bukan untuk memamerkan jago, tapi buat memantapkan urat tenangmu.”
Jayeng menarik napas. Ia mengatur jalur masuk dari basement, meminta security untuk menutup akses tertentu, menyiapkan kamar dan amenities spesifik, memastikan registration card sudah diisi oleh asisten, dan menyiapkan kata-kata yang akan ia ucapkan—tidak banyak, tapi jelas.
Tamu itu masuk tanpa suara. Mata semua orang mengikuti, tetapi prosedur berjalan mulus. Di lift, hanya suara ding kecil. Setiba di lantai, tamu disambut housekeeping yang sudah bersiaga. Jayeng memantau dari HT, setiap koordinasi mengalir seperti orkestra.
Pagi menjelang, hotel hidup seperti biasa. Jayeng duduk sebentar di lorong belakang, memegang pion gantungan kuncinya. Maya muncul membawa dua plastik roti dan dua gelas teh gula batu.
“Kalau kau ingin jadi raja di bayanganmu, ya kau harus jadi pekerja di cahayamu,” ucap Maya sambil duduk. “Simbahku bilang begitu.”
Jayeng merasakan tenggorokannya hangat. “Aku takut gagal, Ya.”
“Semua orang takut. Bedanya, ada yang berkenalan dengan takutnya, ada yang lari dari takutnya. Kamu yang mana?”
Jayeng mengunyah roti. “Aku mau mengajaknya ngobrol.”
Maya tersenyum. “Wis pinter.”
Beberapa jam kemudian, Madi memanggilnya.
“Fotonya tidak bocor, jalur aman, permintaan terpenuhi, dan pagi ini media memuji kita karena menolak wawancara dengan sopan. Bagus. Aku daftarkan kamu resmi masuk seleksi duty manager. Minggu depan presentasi.”
Jayeng memejam sejenak. Seluruh lelah seperti menjelma jadi satu kata: syukur.
.
Hari presentasi datang. Ruang rapat kecil di lantai dua. Sekelompok penguji: Madi, HR, Kepala F&B, Chief Engineering, dan seorang konsultan yang diundang pemilik. Jayeng berdiri di depan layar. Slide pertama menampilkan foto pion yang bayangannya raja—ia memotret gantungan kuncinya tadi malam dengan lampu belajar.
“Presentasi saya berjudul ‘Satu Langkah, Seribu Dampak,’” katanya. “Prinsipnya sederhana: penguasaan diri adalah prasyarat penguasaan operasi. Tanpa kendali emosi, data hanya angka; tanpa kendali ego, wewenang berubah jadi masalah. Saya ingin mencontohkan tiga situasi kecil yang, ketika kita kuasai diri, menjadi kesempatan besar.”
Ia memaparkan kasus banjir dan pemindahan sesi konferensi, kasus tamu publik yang early check-in, dan satu kasus kecil tapi penting: bagaimana ia mengubah sistem lost & found agar lebih transparan dengan mencatat kronologi dalam aplikasi ticketing. Data ia sertakan: respons time turun 25%, komplain hilang barang menurun signifikan.
“Semua ini saya lakukan karena memegang pitutur: Ngeli nanging ora keli. Mengikuti arus situasi tapi tidak hanyut oleh panik. Dan prinsip global yang saya pegang dari Epictetus: ‘We cannot control the wind, but we can adjust the sails.’ Kita tidak bisa mengatur angin, tapi kita bisa mengatur layar.”
Ia menutup dengan menampilkan foto cermin kecil yang ia letakkan di laci front desk: pengingat untuk memeriksa wajah, kata, dan niat sebelum mengambil keputusan.
Ruang itu hening sebentar. Madi mengetuk meja dua kali. “Terima kasih, Jayeng.”
Sesi tanya-jawab dimulai, tajam tapi adil. Kepala F&B bertanya soal manpower planning saat banquet penuh; Chief Engineering menguji soal SOP ketika genset drop; konsultan memancing soal service recovery jika terjadi overbooking. Jayeng menjawab sebaik yang ia bisa, jujur ketika tidak tahu, menawarkan rencana belajar, dan merekam semua masukan.
Dua hari kemudian, pengumuman keluar. Jayeng diterima sebagai duty manager malam. Ia menelepon Adaning dengan suara bergetar; adiknya berteriak menembus sinyal, ibu di belakang mengucap syukur. Maya memeluknya sebentar di lorong back of house.
“Selamat, Raja Bayangan,” ujarnya.
“Jangan gitu,” Jayeng menepuk punggung Maya. “Nanti aku lupa kalau aku hanya bidak yang belajar sabar.”
Maya menunjuk dadanya. “Kau bukan hanya bidak atau raja. Kau manusia yang sedang menjadi.”
.
Sebulan menjadi duty manager, Jayeng menghadapi malam-malam yang diisi kejutan. Ada tamu yang pingsan karena gula darah drop; ia koordinasikan ambulance. Ada sprinkler rusak yang tak sengaja menyembur kamar kosong; ia panggil engineering, pindahkan tamu sebelah, minta maaf dengan buah dan surat tulisan tangan. Ada pertengkaran kecil di bar; ia minta musik diturunkan, memisahkan dua orang dengan pendekatan yang tak memalukan.
Ia belajar menyapa staf satu per satu: nama-nama yang diadaptasi dari kisah lama Menak yang entah bagaimana menyeberang ke Jakarta—Umar Maya di cleaning; Umar Madi senior; Jayengrana yang ternyata nama sapaan barista, “saya dipanggil Jayeng juga, Mas”; Adaning yang magang di marketing sambil kuliah; bahkan ada kawan satpam bernama Wong Agung yang tinggi besar tapi takut jarum suntik.
Kota yang keras dan cepat itu—dengan suara klakson yang tak pernah kehabisan napas—pelan-pelan membukakan kelembutan di sela-sela: roti hangat dari pedagang kaki lima, senyum capek resepsionis yang baru selesai night audit, mop basah yang wangi sabun.
Suatu malam yang berat, hujan turun sampai pagi. Jalanan berubah menjadi genangan raksasa. Kelompok relawan lingkungan yang menginap di hotel memutuskan membagi sembako ke RW terdekat yang kebanjiran. Mereka kekurangan tangan. Jayeng menimbang sebentar—standard operating procedures biasanya melarang staf pergi di jam kerja untuk urusan di luar—tetapi ia melihat kesempatan pelayanan.
Ia cek roster: lobi cukup aman, tamu sedikit. Ia ajukan ke Madi melalui telepon: “Saya ingin melepas dua staff security dan dua housekeeping bersama relawan selama dua jam. Kita dokumentasikan. Ini akan menolong warga dan menambah nilai bagi hotel.”
Diam di ujung sana. Lalu: “Ambil risiko yang kamu bisa pertanggungjawabkan.”
Jayeng melakukan itu: menulis surat izin sementara, mencatat jam keluar dan kembali, memotret bantuan yang disalurkan, memastikan anggota kembali tepat waktu. Pagi hari, warga mengirim pesan terima kasih ke akun hotel. Siang, pemilik hotel yang jarang muncul mengirim pesan: “Good decision. Hospitality should be human.”
Malam itu, Jayeng berdiri di teras belakang, menatap hujan di bawah lampu kuning. Pion kecil di kantong celananya terasa berat setengah gram. Ia mengeluarkannya, membiarkan lampu membentuk bayangan raja di lantai yang basah. “Bukan soal mahkota,” gumamnya. “Soal keberanian mengambil satu langkah lagi.”
Maya muncul, membawa payung. “Kalau kamu telanjur menjadi hujan, jadilah hujan yang menumbuhkan.”
“Pitutur dari mana itu?”
“Dari mulutku sendiri.” Maya tertawa. “Tapi inti pitutur Jawa sama semua: urip iku urup. Hidup itu menyala—untuk orang lain.”
.
Pada hari libur yang jarang berhasil ia genggam, Jayeng pulang ke Jember. Kereta memotong sawah yang memantulkan langit. Di rumah, ibu menyiapkan sayur lodeh dan tempe garit kesukaan. Adaning memamerkan piagam lomba jurnalistik kampus. Sore, mereka main catur di teras.
“Kalau aku,” kata Adaning sambil menggeser gajah, “kurasa pion itu bahagia bukan karena jadi ratu. Tapi karena ia berhasil memaafkan langkah kecilnya yang dulu diejek orang.”
“Memafkan langkah kecil?” Jayeng mengulang.
“Ya. Yang dulu dibilang lambat, kecil, sederhana. Ternyata, di langkah-langkah itulah ia dilatih sabar.”
Jayeng mengangguk. “Kamu sudah siap jadi orang besar, Din.”
“Orang baik dulu, Mas. Orang besar kalau keburu-buru bisa jadi gedung tanpa fondasi.”
Malam itu, di kamar lamanya, Jayeng menulis kalimat di catatan ponsel: “Jangan cari mahkota. Cari cermin. Di cermin, lihat siapa yang kamu kendalikan.”
.
Setahun berlalu. Jayeng terbiasa dengan ritme duty manager: memecahkan masalah, menulis laporan, memuja tidur. Di dinding kantor staff, poster baru terpampang: “Ajining diri saka lathi.” Di bawahnya, terjemahan sederhana: “Harga dirimu ada pada caramu berkata.” Madi memasangnya setelah rapat koordinasi. “Biar ingat,” ujarnya, “kita bukan hanya mengatur ruangan, tapi merawat perasaan.”
Suatu pagi, Madi memanggil Jayeng ke ruang rapat kecil.
“Kamu tahu, hotel akan buka sayap baru tahun depan,” ujarnya. “Akan ada posisi asisten manajer operasional. Ini bukan janji, tapi aku ingin kamu mempertimbangkan jalur kesana. Belajar keuangan lebih serius. Ambil sertifikasi keamanan pangan minimal level satu. Dan mulai mentoring anak-anak baru.”
Jayeng menyahut pelan, “Baik, Mas.”
“Dan satu lagi,” tambah Madi. “Kamu pernah bilang waktu wawancara, kamu ingin suatu saat bikin komunitas buat anak-anak kampung belajar bahasa Inggris dan hospitality dasar?”
Jayeng terkejut. “Masih, tapi… saya menunggu waktu. Dan partner.”
Madi menyodorkan selembar kertas. Proposal kecil: Community Class: Pion Muda. Dalam daftar panitia: Maya, Adaning (akan magang satu bulan di Jakarta), barista Jayengrana, security Wong Agung. Lokasi: aula RW belakang hotel, tiap Sabtu sore.
“Ini idemu,” kata Madi. “Kami bantu fasilitas kecil: proyektor, papan tulis, snack. Sisanya, kau yang pimpin.”
Jayeng menatap kertas itu lama-lama, seperti menatap cermin. Ia teringat dirinya yang dulu berdiri di halte, memegang pion dengan bayangan raja. Ia teringat lobi basah, kursi-kursi didorong, wajah-wajah panik yang perlahan reda. Ia teringat ibu dan catur plastik, teras rumah yang sabar.
“Boleh saya mulai bulan depan?”
“Boleh,” jawab Madi. “Ingat, Jayeng: raja yang baik bukan yang mahkotanya berat. Yang baik itu yang bisa menunduk tanpa kehilangan tegak.”
.
Kelas Pion Muda dimulai dengan sebelas anak—lima SMP, enam SMA—beragam. Ada yang malu-malu, ada yang terlalu ramai. Maya membuka pertemuan dengan humor: “Kalau kalian pusing, salahkan kopi saya.” Mereka tertawa. Jayeng mengajarkan bahasa Inggris dasar untuk menyapa tamu, dasar-dasar tata krama, dan yang paling lama ia bahas: self mastery.
Ia menggambar papan catur di whiteboard. “Siapa di sini yang suka catur?” Dua tangan terangkat. “Siapa pun yang tidak, bayangkan saja ini game di HP. Ada level. Pion ini seperti kita: langkahnya kecil. Tapi jangan anggap enteng. Pion kecil yang sabar bisa menutup jalan menteri. Pion kecil yang disiplin bisa sampai ujung dan promosi. Di hidup, promosi itu bukan hanya jabatan. Promosi adalah ketika kita lebih tenang hari ini dibanding kemarin, lebih jujur pada diri sendiri, lebih berguna untuk sekitar.”
Seorang anak bernama Karyo—yang bapaknya tukang tambal ban—berkata, “Bang, kalau kita sudah sabar tapi tetap disalahin gimana?”
Jayeng menatapnya. “Sabar itu bukan supaya orang lain berhenti menyalahkan. Sabar itu supaya kita berhenti menjadi orang yang gampang menyalahkan. Dari situ, langkah kita jernih. Biar orang lain tetap ribut, kita tetap jalan.”
Kelas itu tak sempurna—kadang mereka gaduh, kadang Jayeng kehilangan cara menyederhanakan istilah. Tapi setiap Sabtu, ia pulang dengan napas panjang yang ringan. Seperti baru saja main catur, kalah-menang tidak terlalu penting karena ia tahu ia bertambah satu jam sabar.
Di akhir sesi bulan kedua, anak-anak menempelkan kertas kecil di papan: “Apa yang kamu kuasai bulan ini?” Ada yang menulis, “Aku kuasai bangun pagi.” Ada yang menulis, “Aku kuasai menahan marah sama adik.” Ada yang menulis, “Aku kuasai minta maaf ke ibu.”
Jayeng memotret kertas-kertas itu. Malamnya, ia duduk sendirian di lobi yang sepi, memandangi foto. Maya datang, duduk di sebelah.
“Dulu kamu cari mahkota,” kata Maya, “sekarang kamu bikin cermin untuk banyak orang.”
Jayeng menggeleng. “Aku bahkan tidak tahu apakah aku layak.”
Maya menepuk bahu. “Laku dulu. Layak menyusul.”
Di kaca lobi, bayangan mereka memanjang. Di saku, pion kecil itu tetap ada—bukan jimat, bukan janji, hanya pengingat: jangan berhenti menjadi bidak yang melangkah.
.
Pada suatu malam yang lembap, Jayeng pulang agak larut. Jalanan Slipi gemerlap, lampu kendaraan memanjang seperti benang putih yang ditarik. Ia berhenti sejenak di jembatan penyebrangan, menatap kota. Gedung-gedung tinggi seperti raja-raja tanpa wajah, tapi di bawahnya, ada peluh orang-orang yang membuat semua itu tetap berdiri.
Ia mengetik pesan di ponsel, mengirimkannya ke grup “Pion Muda”:
“Kalau kalian merasa kecil, ingat ini: ‘Langkah kecil yang jujur lebih kuat daripada lompatan besar yang kosong.’ Jangan buru-buru jadi raja. Jadilah manusia yang menguasai diri—karena dari situlah, kalian bisa menguasai arah.”
Tak lama, notifikasi muncul: Karyo: “Sip, Bang.” Sari: “Besok aku mau coba minta maaf ke ibuku.” Nisa: “Aku mau belajar nyapa orang pakai ‘Good evening’ nggak cempreng.” Mereka menutup malam dengan emotikon setengah matang, tapi Jayeng merasakan sesuatu matang di dadanya.
Hujan rintik jatuh, tipis-tipis. Ia memasukkan ponsel, memegang pion di saku, lalu melanjutkan langkah.
Kota terus bergerak, seperti catur yang tak pernah selesai dimainkan. Tapi malam itu, dalam perjalanan pulang, Jayeng tahu satu hal yang tak akan berubah: ia akan terus memilih menjadi bidak yang sabar—karena hanya dengan begitu, bayang-bayangnya akan tetap tegak tanpa perlu mahkota.
Dan jika kelak orang bertanya apa yang membuatnya sampai di tempat yang ia tempuh, ia akan menjawab:
“Bukan kemenangan besar. Bukan rezeki kaget. Hanya kebiasaan menggilas kebiasaan buruk—pelan-pelan, satu langkah, lalu satu langkah lagi.”
.
.
.
Jember, 19 Agustus 2025
.
.
#CerpenIndonesia #PituturJawa #MasterYourself #EtosKerja #UrbanStory #Hospitality #MotivasiHidup