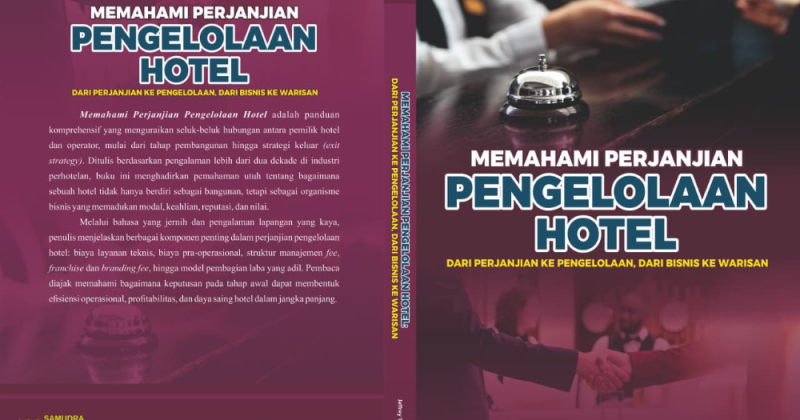Lara dan Luruh
“Lara itu tidak selalu berteriak;
kadang ia duduk diam di sudut kamar,
menunggu kau berani mengaku:
‘Aku lelah, tapi aku belum selesai.’”.
Malam di Jakarta turun pelan seperti tirai bioskop yang hendak menutup adegan terakhir.
Dari lantai dua puluh sebuah apartemen di kawasan Kuningan, kota itu tampak seperti papan sirkuit: garis-garis cahaya oranye mengalir di jalan layang, gedung-gedung kaca memantulkan bintang yang kalah terang, dan suara klakson samar mengendap di udara.Ragil Kuning menatap semua itu dari balik jendela besar ruang tamunya, satu tangan menggenggam mug teh chamomile, tangan lain memegang ponsel yang bergetar tak henti. Notifikasi WhatsApp memenuhi layar. Di atas, ada satu nama grup yang sudah lama ia bisukan: Menak Urban 2019.
Ikon grup itu foto lama: enam orang di sebuah kafe Kemang, tertawa terlalu lebar untuk orang-orang yang kini saling berjarak.
Ragil menarik napas. Dada kirinya seperti diremas sesuatu yang tak kelihatan.
Ia menyentuh layar. Jempolnya ragu sesaat, lalu membuka.
Deret pesan memenuhi chat, bergerak cepat seperti subtitle film.
Jayengrana: “Guys, gue ke Jakarta bulan depan. Launching buku sekalian meeting investor. Yuk reuni kecil?”
Anggraini: “Gila, lima tahun! Aku ikut!”
Umar Maya: “Kalau nggak ada job nikahan, gue gas.”
Umar Madi (Adi): “Market lagi jungkir balik, tapi gue usahain.”
Kartini: “Sidangku mepet, tapi aku coba mampir.”Di atas semua pesan itu, ada voice note lima belas detik dari Jayengrana. Ragil menekannya.
Suara Jayengrana memenuhi ruang tamu yang sepi.
“Gil… kamu baca nggak sih grup? Lima tahun, Gil. Lima tahun. Dulu kita tiap malam debat di kafe, sekarang baca kabar masing-masing aja udah susah. Kalau sempat, aku pengin banget lihat kamu. Kalau pun nggak… yah, minimal jawab dong.”
Suara itu bergetar sedikit pada kata terakhir. Ragil menutup mata.
Lima tahun.
Padahal terasa seperti kemarin, ketika mereka duduk melingkar di kafe kecil di Kemang, menertawakan dunia dan menyusun janji yang terlalu besar.
Sekarang, jarak di antara mereka bukan lagi soal lokasi, melainkan soal musim hidup.
Dan entah kenapa, justru di detik ini, kata yang paling mengapung di benaknya bukan “reuni” atau “senang”, melainkan dua kata yang ia pilih sebagai nama usaha kecilnya: Lara dan Luruh.
.
Lima tahun lalu, kafe itu masih beroperasi; lampu-lampu kuningnya menetes lembut di meja kayu, musik jazz mengisi jeda di antara tawa. Mereka ber-enam menamakan diri Menak Urban, parodi dari cerita Menak yang dulu mereka pelajari di kelas sastra Jawa.
Jayengrana-lah yang mencetuskan nama itu.
Malam itu ia berdiri di kursi, mengangkat gelas latte, dan berpidato seolah di hadapan pasukan.“Dengarkan, wahai rakyat jelata!” serunya. “Mulai hari ini, kerajaan Menak pindah ke Kemang. Ksatria-ksatrianya adalah pekerja kantoran, senjatanya laptop, kudanya ojek online!”
Mereka tertawa sampai pelayan kafe ikut tersenyum.
Di meja itu duduk enam orang dengan hidup rapi versi katalog:
Jayengrana, si penggagas startup logistik, baru saja resign dari perusahaan lama demi mengejar mimpinya.
Umar Maya, fotografer yang siang hari kerja di agensi periklanan, malamnya memotret apa pun yang bergerak.
Umar Madi, yang mereka panggil Adi, analis investasi dengan jam kerja tanpa jam pulang.
Anggraini, penari klasik yang merintis studio tari anak-anak di pinggir kota.
Kartini, pengacara junior di firma internasional.
Dan Ragil, HR Manager sebuah grup hotel, baru selesai satu modul S2 Manajemen, masih rajin ikut seminar dan mengurus training.
Malam itu, seperti biasa, obrolan mengalir ke masa depan.
“Lima tahun dari sekarang, kita semua udah beda banget,” kata Anggraini sambil menggambar garis di tissue. “Aku bakal punya studio tari sendiri, lantainya kayu, kaca besar, muridnya dari berbagai kota.”
“Lima tahun dari sekarang,” sahut Umar Maya, “aku punya pameran foto di galeri. Bukan cuma foto pengantin, tapi foto-foto manusia yang lagi berjuang.”
“Gue minimal udah pegang fund sendiri,” kata Adi, menggoyang-goyangkan sendok di gelas. “Bukan cuma jadi anak buah yang ngitung risiko orang.”
Kartini meregangkan leher, mengusap kantung mata. “Aku sudah bosan jadi pembawa map. Lima tahun dari sekarang, aku mau berdiri di depan hakim luar negeri, pakai blazer yang benar-benar jahitan sendiri.”
Jayengrana menatap mereka satu per satu.
“Gue nggak muluk-muluk,” katanya, padahal semua tahu ia paling ambisius. “Lima tahun dari sekarang, kalau kita ketemu lagi, gue cuma mau lihat kita semua nggak jadi figuran di hidup orang lain. Minimal, kita hidup sebagai tokoh utama di kisah masing-masing.”Mereka menoleh ke Ragil.
“Kalau kamu?” tanya Anggraini.
Ragil memandang ke luar jendela kafe. Jakarta malam itu tak seramai malam-malam sekarang; belum ada sirine ambulans yang saling tumpuk, belum ada masker yang menutupi wajah-wajah asing.
“Aku…” Ragil berhenti. “Aku nggak tahu mau jadi apa. Tapi aku pengin… bertahan. Apa pun yang terjadi, aku masih bisa berdiri utuh.”
“Cuma itu?” protes Umar Maya.
Ragil mengangkat bahu, tersenyum kecil.
“Kadang, kemampuan bertahan itu sendiri sudah cukup ambisius.”Mereka tertawa, lalu kembali membahas hal-hal remeh: siapa yang diam-diam suka siapa, gaji siapa yang paling kecil.
Tak ada yang menyangka, lima tahun ke depan, kalimat “bertahan” akan berubah menjadi doa yang berat.
.
Lalu 2020 datang seperti kabar buruk yang tidak sopan: tanpa mengetuk pintu lebih dulu.
Suara sirine ambulans menggantikan bunyi musik di kafe.
Hotel-hotel tempat Ragil bekerja berubah dari tempat liburan jadi gedung kosong dengan lampu-lampu mati.
Tamu-tamu menghilang, digantikan tanda-tanda pembatalan.Rapat-rapat darurat diadakan.
Kertas-kertas berisi nama-nama karyawan menumpuk di meja Ragil.
Setiap nama punya cerita, punya keluarga, punya cicilan.“Maaf, Mbak, saya baru saja ambil motor.”
“Pak, anak saya masih bayi.”
“Mbak Ragil, saya bisa kerja apa saja, tolong jangan pecat saya.”Kalimat-kalimat itu menempel di dinding pikirannya seperti poster yang tak bisa dicopot.
Hingga akhirnya, setelah berbulan-bulan menjadi penyampai kabar buruk, ia sendiri menerima email itu:
restrukturisasi organisasi.Di lobi hotel yang sepi, Ragil duduk dengan satu kotak kardus di pangkuan.
Di luar, hujan mengguyur parkiran.
Di dalam, pendingin ruangan tetap menyala seakan-akan tak terjadi apa-apa.Ponselnya bergetar.
Ragil: “Teman-teman… aku di-PHK.”
Balasan datang tak lama kemudian.
Anggraini: “Astaga, Gil… peluk jauh.”
Adi: “Sabar. Kita cari jalan, ya.”
Umar Maya: “Kalau nggak pandemi, kita udah kumpul sambil maraton kopi.”
Kartini: “Kalau kamu butuh konsultasi soal hakmu, kabari aku.”
Jayengrana: “Gil, gue yakin ini bukan akhir. Gue telpon nanti malam, ya.”Malam itu, telepon yang dijanjikan tak pernah benar-benar berdering.
Jayengrana stuck di video call dengan calon investor.
Kartini terjebak sidang daring.
Anggraini mengajar kelas tari via Zoom.
Adi lembur demi mengejar pasar yang menukik.
Umar Maya sedang memotret keluarga yang tetap memaksa menggelar pesta kecil.Notifikasi di grup menghilang di antara notifikasi lain.
Tak ada yang berniat menyakiti; hidup mereka hanya kebanjiran darurat masing-masing.Namun bagi Ragil, itu cukup menjadi luka kecil yang lama-lama menganga.
.
Hari-hari setelahnya, hidupnya bergerak dalam mode bertahan: mengurangi pengeluaran, menunda mimpi, melamar ke sana-sini, menelan penolakan seperti pil pahit.
Suatu malam, saat duduk sendirian di kamar kontrakan, ia menyalakan lilin aromaterapi pemberian tamu asing yang dulu sering menginap di hotel. Aroma kayu putih dan citrus menyelimuti ruangan. Ada tenang yang datang pelan, seperti tangan yang mengusap punggung.
“Kenapa aku tidak membuatnya sendiri?” pikirnya.
“Aroma yang mengingatkanku bahwa lara bisa pelan-pelan luruh.”Dari situ lahir ide kecil yang kemudian menjadi usaha mikro: Lara & Luruh—lilin aromaterapi dengan nama-nama wangi yang ia kutip dari perasaan: “Pulang Pelan-Pelan”, “Sisa Rindu di Sudirman”, “Tawa yang Tertinggal di Kemang”.
Usaha itu tidak langsung meledak.
Awalnya hanya beberapa teman yang membeli, lalu teman dari teman, lalu entah bagaimana satu unggahan Anggraini di Instagram menarik pelanggan baru.
“Ini lilin buatan temanku yang dulu kerja di hotel,” tulis Anggraini. “Aromanya kayak lobi bintang lima, tapi ceritanya tentang bertahan hidup.”Di tengah pelan-pelan tumbuhnya Lara & Luruh, grup Menak Urban makin sepi.
Mereka tetap saling mengikuti di media sosial, menekan tombol “like”, sesekali komentar pendek, namun obrolan panjang seperti dulu lenyap.Ragil beberapa kali mengetik pesan panjang—tentang betapa kesepiannya mengantar berkas lamaran, tentang betapa canggungnya kembali ke rumah orang tua, tentang bisnis kecil yang kadang rugi, kadang nyaris bangkrut—lalu menghapusnya sendiri.
Ia belajar menahan cerita, menyimpan lara, dan membiarkannya luruh pelan-pelan di malam yang sepi.
.
Waktu menyusup tanpa suara.
2021 berganti 2022, lalu 2023.Ragil pindah ke apartemen kecil hasil gabungan tabungan lama dan omzet usaha. Ia mulai diminta mengisi pelatihan HR dan sesi motivasi untuk karyawan yang dirumahkan. Dalam ruangan-ruangan meeting hotel yang kini ia datangi sebagai pembicara, ia melihat wajah-wajah yang dulu pernah ia dampingi dari sisi lain meja.
“Nama saya Ragil,” demikian ia selalu membuka sesi. “Saya pernah duduk di kursi Anda. Saya pernah takut, marah, merasa tidak adil. Tapi ternyata, dari semua itu, ada sesuatu yang tetap bisa saya bawa: kemampuan untuk jujur pada diri sendiri, bahwa saya sedang terluka.”
Setiap kali selesai sesi, ada saja yang menghampirinya.
“Terima kasih, Mbak. Saya baru berani bilang bahwa saya sedih,” kata seorang bapak paruh baya.
“Terima kasih, Mbak. Saya kira saya satu-satunya yang merasa ditinggalkan teman-teman,” kata perempuan muda dengan mata sembab.Ragil pulang dengan lelah, tetapi lelah yang berbeda: lelah karena memberi, bukan sekadar bertahan.
Namun setiap membuka ponsel dan melihat nama grup Menak Urban, ada ruang kosong di dadanya yang belum sepenuhnya terisi.
Pada suatu masa, mereka sangat dekat.
Sekarang, ia bahkan ragu, kalau bertemu di lobi mall, apakah mereka akan saling peluk, atau hanya mengangkat tangan sambil berkata, “Eh, lama nggak ketemu, ya,” lalu berlalu..
Undangan reuni dari Jayengrana datang di hari Senin yang basah.
Jakarta baru saja diguyur hujan sore. Di luar jendela, lampu-lampu kendaraan memantul di aspal. Di dalam apartemen, mesin lilin Ragil berdengung pelan.“Lima tahun,” gumamnya, memandang layar ponsel. “Lima tahun sejak malam di Kemang itu.”
Ia membuka satu per satu profil teman-temannya.
Jayengrana, kini tinggal bolak-balik Jakarta–Singapura, memimpin ekspansi startup yang dulu hanya ia ceritakan di antara seruput espresso.
Umar Maya mengunggah foto-foto pernikahan, tapi juga seri foto dokumenter tentang pekerja jalanan. Di salah satu caption, ia menulis: “Bertahan itu kadang cuma soal bangun besok pagi.”
Adi tidak terlalu aktif di media sosial, tapi sesekali menulis analisis panjang tentang keadaan ekonomi, diselipkan humor sinis.
Anggraini mengajar tari untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Video latihannya selalu penuh tawa.
Kartini berdiri di depan gedung pengadilan luar negeri, senyumnya tipis namun matanya mantap. Di bawah foto itu ia menulis: “Perjalanan panjang dari membawakan map orang lain hingga membawa berkas sendiri.”
Mereka semua bergerak.
Melejit.
Menabrak langit versinya masing-masing.Ragil menatap etalase kecil Lara & Luruh di sudut apartemen—rak kayu dengan lilin-lilin berbagai ukuran, label yang ia desain sendiri, aroma yang ia uji dengan telaten.
“Lima tahun lalu, aku hanya bilang ingin bertahan,” katanya pelan. “Mungkin sekarang waktunya mengakui: aku bukan cuma bertahan. Aku berubah.”
Namun perubahan itu tak menghapus getir.
Ada bagian dari dirinya yang masih bertanya:
Mengapa saat ia terjatuh paling keras, tak ada satu pun dari mereka yang benar-benar menemaninya?Pertanyaan itu seperti lara yang enggan pergi.
.
Hari-hari menjelang reuni, hidup Ragil justru bertambah padat.
Permintaan pesanan lilin meningkat—ada perusahaan yang memesan untuk hampers akhir tahun, ada hotel yang ingin aroma khusus untuk lobi.
Ia juga dijadwalkan mengisi workshop untuk karyawan yang terkena efisiensi di sebuah perusahaan besar.Tanggalnya bertabrakan dengan hari launching buku dan reuni kecil versi Jayengrana.
Suatu malam, ketika sedang menempel label pada puluhan jar kaca, ponselnya kembali bergetar. Pesan pribadi dari Jayengrana.
“Gil, ini undangan resminya ya.
Jujur, satu hal yang pengin banget gue lihat di ruangan itu… kamu.
Tapi gue juga ngerti hidup orang sekarang nggak sesederhana cabut terus nongkrong.
Apa pun keputusanmu, gue cuma mau bilang: thanks. Obrolan kita dulu nggak bakal gue lupa.”Ragil membaca pesan itu pelan.
Ada hangat yang merambat naik ke tenggorokan.“Kenapa baru sekarang bilang begitu?” ia mengomel pada udara.
Tetapi barangkali, memang begitulah cara hidup bekerja.
Beberapa kalimat hanya bisa diucapkan ketika masing-masing sudah berdiri tegak di jalannya sendiri.Ia mengetik balasan, menghapus, mengetik lagi.
Akhirnya, ia mengirim:“Jaye, terima kasih sudah ingat.
Aku senang kamu sampai di titik ini.
Tapi hari itu aku harus mengisi workshop buat orang-orang yang baru di-PHK.
Dulu aku di posisi mereka, dan waktu itu aku tahu rasanya sendirian.
Kali ini, aku nggak mau mereka merasa begitu.
Kalau semesta berbaik hati, kita akan ketemu di bab lain.”Titik tiga kecil di ujung layar berkedip.
Jayengrana: “Aku ngerti, Gil.
Kamu tetap Ragil yang dulu: mikirin orang lain dulu sebelum diri sendiri.
Semoga sekarang, di antara semua itu, kamu juga sempat mikirin dirimu.
Kirim alamatmu, ya. Nanti aku titipkan sesuatu.”Senyum kecil muncul di bibir Ragil.
Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia merasa lara di dadanya bergeser sedikit—tidak lagi tajam, hanya getir yang bisa ditertawakan pelan..
Siang hari yang ditentukan, Ragil berdiri di depan ruangan meeting hotel di Sudirman.
Di luar, lalu lintas mengalir. Di dalam, tiga puluh kursi terisi. Mata-mata lelah menatap ke arahnya.“Selamat siang,” sapanya. “Nama saya Ragil. Saya pernah berada di posisi Anda: kehilangan pekerjaan, merasa ditinggalkan, marah pada dunia.”
Hening sejenak. Ia meneruskan, pelan tapi mantap.
“Waktu itu, saya menunggu teman-teman datang. Menunggu telepon yang tak kunjung berdering. Rasanya pahit. Tapi justru dari situ, saya belajar sesuatu: ada lara yang tidak bisa disembuhkan orang lain, hanya bisa kita rawat agar pelan-pelan luruh.”
Ia tak menyebut nama-nama di masa lalunya. Ia tidak perlu.
Hari ini, perannya bukan sebagai korban cerita, melainkan saksi bahwa orang bisa bangkit dengan caranya sendiri.Sesi itu berjalan haru. Beberapa peserta menunduk, mengusap mata. Ada yang datang setelah acara usai hanya untuk menyalami.
“Mbak Ragil,” kata seorang perempuan muda dengan jilbab biru. “Saya kira saya satu-satunya yang ditinggal saat paling butuh. Ternyata… ya begitulah hidup, ya?”
“Begitulah,” jawab Ragil. “Orang datang dan pergi. Tapi kalau kita mau jujur, mereka juga punya lara masing-masing. Yang penting, kita tidak ikut meninggalkan diri kita sendiri.”
Perempuan itu mengangguk, bibirnya bergetar.
“Terima kasih. Kata-kata Mbak hari ini… mungkin akan lama saya simpan.”Saat melangkah keluar ruangan, Ragil mendongak sebentar menatap lampu-lampu crystal di langit-langit lobi hotel. Aroma karpet baru dan kopi dari sudut kafe bercampur di udara—menghadirkan nostalgia kehidupan lamanya.
Hatinya berdesir, tapi kali ini bukan karena rindu yang menyakitkan.
Lebih karena rasa syukur: ia pernah menjadi bagian dari dunia ini, dan sekarang ia membawa serpihan keahliannya ke tempat lain..
Senja baru saja turun ketika ia tiba di apartemen.
Di depan pintu, ada paket cokelat dengan pita emas.
Pengirimnya: nama asing, tapi begitu dibuka, di dalamnya ada buku dengan judul yang sering ia lihat berseliweran di media sosial—buku karya Jayengrana.Di halaman pertama, ada tulisan tangan:
Untuk Ragil:
Beberapa tahun lalu, kita duduk di kafe dan membahas masa depan seolah dunia akan selalu ramah. Kenyataannya tidak begitu. Tapi di antara semua benturan, ada kalimatmu yang selalu aku ingat: ‘Aku hanya ingin bertahan.’
Terima kasih sudah mengajarkan bahwa bertahan itu pun sebuah keberanian. Semoga lara-lara yang pernah kita bawa kini sudah mulai luruh, meski pelan.
—J.
Ragil terdiam lama.
Matanya terasa panas, tapi bukan karena sedih semata; lebih karena lega, karena sesuatu akhirnya mendapat kata.Ia meletakkan buku itu di rak, di samping deretan lilin aromaterapi yang menunggu dikirim.
Lalu, seperti ritual kecil, ia menyalakan satu lilin bertajuk “Lara dan Luruh”—varian aromanya yang belum ia jual ke mana pun, hanya ia simpan untuk dirinya sendiri: campuran wangi kayu manis, bergamot, dan sedikit lavender.Cahayanya lembut.
Api kecilnya menari-nari di permukaan.Ragil duduk di depan jendela besar, memandang kota yang tak pernah benar-benar tidur.
Lalu ia membuka ponsel, masuk ke grup Menak Urban.Ada foto yang baru diunggah: lima orang berdiri di atas panggung launching buku, tertawa ke arah kamera. Di baris depan, ada satu kursi kosong.
Seperti menungguku, pikirnya sambil tersenyum kecil.
Tanpa terlalu banyak mikir, ia menulis:
Ragil: “Maaf nggak bisa datang hari ini.
Tapi aku lihat dari foto, kalian baik-baik saja.
Jagalah bahagia itu, ya.
Pada suatu masa kita pernah dekat, dan bagiku itu tidak akan pernah jadi sia-sia.”Tidak lama, balasan bermunculan.
Anggraini: “Gil… kita kangen. Next time, ya. Dan aku mau pesan lilin lagi!”
Umar Maya: “By the way, di launching tadi gue bawa lilin ‘Sisa Rindu di Sudirman’. Panitia suka.”
Adi: “Jaga dirimu baik-baik. Kalau suatu saat kamu butuh modal, cerita ke gue.”
Kartini: “Terima kasih pernah jadi rumah untuk keluh kesah kami dulu. Sekarang kamu jadi rumah untuk banyak orang lain, kayaknya.”Jayengrana menutup dengan satu kalimat:
“Gil, terima kasih sudah datang sejauh ini—meski tidak secara fisik. Menurutku, itu pun sudah cukup.”
Ragil tertawa pelan.
Ada hangat yang menyebar dari dada ke ujung jari.Di luar, lampu-lampu kota terus berkedip.
Di dalam, lilin kecil di meja terus menyala, menyisakan aroma yang pelan-pelan mengisi ruang.Lara masih ada.
Ia tidak tiba-tiba hilang.
Sesekali masih datang diam-diam, mengetuk di jam-jam paling lengang.Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, Ragil merasa lara itu sudah tahu tempatnya: bukan lagi di tengah dada, melainkan di sudut ruangan, duduk manis bersama kenangan yang lain—menunggu saatnya benar-benar luruh.
Ia mengangkat mug teh yang mulai dingin, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela.
“Terima kasih, Ragil,” bisiknya pada diri sendiri. “Sudah berani tetap tinggal, bahkan ketika banyak yang pergi.”
Di luar sana, dunia terus berputar tanpa menunggu siapa pun.
Tapi di dalam ruangan kecil di lantai dua puluh, seorang perempuan bernama Ragil Kuning akhirnya paham:Kadang, yang paling penting bukanlah siapa yang tinggal atau pergi,
melainkan bagaimana kita belajar merawat lara
hingga pelan-pelan, dengan sabar,
ia menjadi luruh.
.
.
.
Malang, 13 November 2025
.
.
#LaraDanLuruh #CerpenKompasMinggu #UrbanStory #PersahabatanDewasa #HealingJourney #NarasiFilmisJakarta