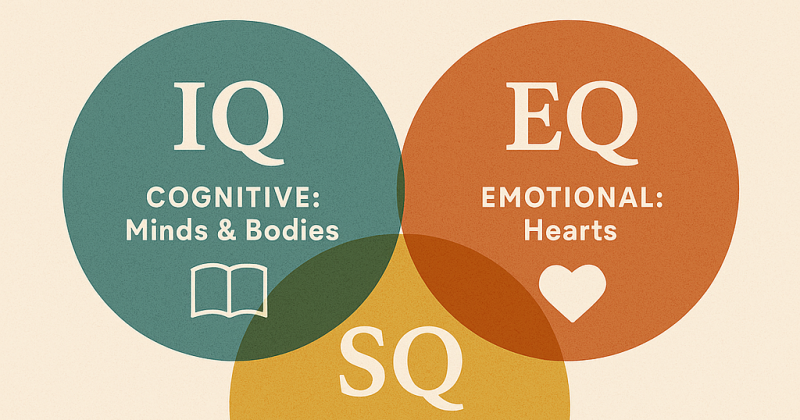Langkah-Langkah Kecil untuk Bertahan
“Hidup bukan tentang sorot lampu, melainkan tentang keberanian belajar pelan-pelan setiap hari di hadapan cermin ekspektasi.”
.
Malam turun di Surabaya seperti lembar kain hitam dengan jahitan lampu-lampu oranye. Sirene ambulans menjerit lalu padam. Di trotoar basah Gubeng, seorang pemuda berjaket parasut berjalan cepat sambil menahan ransel lusuh di punggung. Namanya Adipati. Ia datang dari Sumenep, membawa sepotong doa ibu dan sebungkus singkong goreng yang sekarang tinggal serpihan.
Ia selalu merasa kota ini punya dua wajah: satu menatapmu seperti teman yang ramah, satu lagi menatapmu dingin seperti satpam minimarket yang mencurigai semua orang. Di antara dua tatapan itu, Adipati menggeser langkah, mencari celah untuk bertahan.
Di terminal Bungurasih, sebelum berangkat tiga bulan lalu, ibunya memeluk erat. “Lek pas ora iso mlayu, Le, sinau mlaku alon-alon. Ojo isin diwiwiti saka nol.” Jika tak bisa berlari, pelajarilah berjalan pelan. Jangan malu memulai dari nol. Kalimat yang sederhana, namun mengendap dalam dada seperti obat yang larut perlahan.
Kota menuntut satu hal yang tak pernah tertulis di papan lowongan kerja: basic life skills—kemampuan menakar beras dengan takaran hemat, membaca emosi lawan bicara, merapikan kasur agar pikiran tidak berantakan, mencatat pengeluaran, menahan diri agar tidak meledak saat diprovokasi, memijat hati sendiri ketika tidak ada yang sudi menenangkan.
Adipati mencatat semuanya dalam buku kecil yang sampulnya mulai mengelupas. Di halaman pertama ia menulis: “Bertahan itu bukan hanya gaji. Bertahan itu relevansi.”
.
Warung Kopi Arya
Bangku plastik merah berderit saat ia duduk. Warung kopi kecil di tepi jalan itu milik Arya, lelaki paruh baya dengan rambut memutih seperti garam yang ditabur angin. Orang-orang kampung bilang Arya dulu aktivis yang pandai bicara, sekarang lebih pandai diam. Di sana pula Puspa sering nongol, mahasiswi seni rupa yang pernah menggambar wajah Adipati pada tisu—rapuh, mudah robek, tetapi menyimpan jejak.
“Capek?” Puspa mengangkat alis. Di hadapannya, gelas kopi tubruk masih berputar seperti pusaran kecil yang tak mau berhenti.
“Capek itu biasa,” jawab Adipati. “Yang tidak biasa itu menyerah.”
Arya terkekeh. “Kowe kudu iso masak, Di. Bisa masak itu bukan soal selera, tapi soal martabat. Orang yang bisa memasak, ora gampang kelangan arah—tak mudah kehilangan arah. Di dapur, kau belajar waktu, sabar, dan api.”
Malam demi malam, warung itu berubah menjadi kelas kecil. Arya mengajarkan cara menyapu lantai tanpa menerbangkan debu ke meja orang, cara memindahkan panci panas tanpa panik, cara menakar gula agar kopi tidak menipu. Puspa mengajarkan Adipati membuat poster digital gratis untuk kampanye kebersihan kampung. Adipati mengajari Arya mengelola kas sederhana di buku catatan; ia belajar sendiri dari video-video yang diputar diam-diam dengan paket data hemat.
Di satu sudut, angin membawa bau bensin dari jalan raya; di sudut lain, ada bau air hujan yang jatuh ke seng. Suara sendok bertemu gelas terdengar seperti metronom kecil—ting, ting, ting—mencatat langkah-langkah pelan menuju kewarasan.
.
Jakfar
Pekerjaan datang seperti tamu tak diundang—seadanya tapi disyukuri. Jakfar, pemuda Bangkalan yang dikenal ringan tangan dalam hal membantu dan sama ringannya dalam hal meledak, mengajak Adipati kerja sambilan di kafe modern: barista cadangan, apapun artinya. Gaji kecil, jam tak pasti, senyum wajib. Di balik mesin espresso, hidup tampak rapi, tapi di balik itu, manusia tetap rumit.
Suatu malam, seorang pelanggan protes karena cappuccino-nya berbusa terlalu tebal. Jakfar bersuara lebih tebal. Kata-kata naik, kursi ikut bergeser. Adipati menyelip di antara dua murka, tangan terbuka, suara rendah, “Mas, kita benerin. Minute ya.”
Pelanggan itu mendorong, mungkin sengaja, mungkin tidak. Adipati tersungkur; cangkir pecah, bunyinya seperti hati kecil retak. Manajer datang, menatap sekelebat, memutuskan cepat: keduanya out. Jakfar karena temperamen, Adipati karena “tidak mampu menjaga suasana.” Pada akhirnya, sistem suka lupa membedakan penyelamat dan tersangka.
Di kamar kos pengap berukuran dua kali tiga meter, Adipati menatap langit-langit. Kipas angin berbunyi sumbang. Ia menahan napas agar tetangga tidak mendengar tangisnya. Ia malu. Bukan malu pada dunia, tapi pada dirinya sendiri yang masih sering limbung. Ia mengingat pesan ayah: “Wong kuwat kuwi dudu sing ora tau tiba, tapi sing iso ngadeg maneh sanajan wis tiba bola-bali.” Orang kuat bukan yang tak pernah jatuh, melainkan yang bangkit meski jatuh berkali-kali.
Pagi berikutnya ia kembali ke warung Arya. “Gagal?” tanya Arya tanpa nada menghakimi.
“Kelihatan ya?”
“Gagal itu bukan stempel, Di. Gagal itu guru sing cerewet—kalau pelajarannya belum dipahami, ia akan datang lagi.”
.
Rapat Kampung
Di balai RW, rapat dimulai dengan lagu Indonesia Raya yang maigak. Setelahnya, polarisasi kecil langsung terasa: kelompok ibu-ibu yang ingin lomba kebersihan, kelompok bapak-bapak yang ngotot soal portal jalan, dan sekelompok anak-anak muda yang memikirkan festival mural. Di meja depan, Wirawangsa—pedagang kain dari Pasar Turi yang kiosnya hangus terbakar bulan lalu—duduk menunduk, tangannya bergetar pelan.
Ketua RW memutar kursi. “Siapa yang mau jadi notulen?”
Adipati berdiri. Ia menulis cepat, menyalin perbedaan pendapat menjadi daftar aksi: gotong royong Sabtu pagi, perbaikan portal pakai iuran sukarela, undang dosen seni untuk kurasi mural, pelatihan digital untuk UMKM pasar. Di sela rapat, ia menengok Wirawangsa.
“Bapak ikut pelatihan digital, ya?” sapanya.
Wirawangsa menggeleng. “Aku iki wis tuwo, Le. Aku sudah tua. Ponsel pintar terasa seperti pasar gelap. Anak-anak sibuk sendiri. Aku bingung.”
“Kita belajar bareng,” kata Adipati. “Kalau Bapak bisa mencatat jualan di buku, kita pindahkan pelan-pelan ke ponsel. Nanti saya buatkan foto baju Bapak, kita unggah. Pelan-pelan.”
Matanya memantul cahaya lampu neon. Basah, tapi bukan sedih; lebih mirip orang yang melihat jembatan di atas sungai yang lama menghalangi jalannya.
Puspa yang duduk di belakang tak henti menatap. Seusai rapat, ia menunjukkan sketsa: di kertas itulah tertulis garis-garis di sekeliling Adipati yang berdiri di antara banyak suara, seperti tiang yang menyangga tenda. “Kamu tidak tahu betapa bergunanya orang yang bisa menenangkan,” katanya.
“Di grup WhatsApp, aku juga kaya gitu kok,” sahut Adipati bercanda. “Menenangkan tanpa dibayar.”
Mereka tertawa. Tawa yang ringan, setidaknya malam itu.
.
Hujan Orang-Orang
Hujan pertama di bulan berikutnya turun seperti seseorang yang tak sabar untuk bicara. Air menyapu jalanan, mengangkut plastik, daun, dan sedikit ketakutan. Selokan meluap; air cokelat naik menakutkan. Di gang depan warung, motor-motor berhenti, pengendara melindungi ponsel seperti kitab suci kecil.
Arya mematikan sebagian lampu, menutup rak kerupuk, mengikat tabung gas. “Kalau air naik, kita geser kompor ke meja paling tinggi,” katanya.
“Di, tolong bantu.” Puspa menggulung lengan, mengangkat kardus. “Kalau ada anak kecil sama ibu-ibu, suruh ke dalam sini saja.”
Hujan jadi kata kerja. Orang jadi jamak. Adipati berlari bersama para tetangga. Mereka memindahkan barang, mengangkat nenek yang tidak bisa berjalan, menggendong anak yang takut suara guntur. Di satu rumah, ada kandang burung yang hampir hanyut. “Bawa,” kata seseorang. “Semua yang hidup punya hak selamat.”
Di tengah kepanikan, Jakfar muncul basah kuyup. Beginilah kota: pertengkaran kemarin tak punya kuasa ketika air naik. Ia ikut mendorong lemari, menahan pintu agar tidak terbanting, menepuk bahu Adipati tanpa kata. Bahasa yang paling adil: tindakan.
Di warung Arya, mereka menggelar dapur darurat. Kompor menyala; panci besar mengepul. Nasi, sayur bening, telur kecap—menu yang menyelamatkan banyak malam Indonesia. Ada orang yang hanya ingin duduk di bawah lampu dan mendengar panci bergemerincing. Ada yang ingin diam karena suara hujan cukup berisik.
“Di,” bisik Puspa, “kamu bisa koordinasi?”
Adipati menarik napas panjang. “Oke, kita bagi peran. Tiga orang di dapur. Dua orang di pintu—cek suhu, lihat apakah butuh pertolongan pertama. Sisanya ke dalam—bikin tempat tidur dari kardus. Nanti catat siapa yang makan agar tidak ada yang dobel, dan agar besok kita tahu berapa banyak bahan yang harus dibeli.”
“Hebat juga kamu,” ujar Arya. “Belajar dari mana?”
“Belajar dari warung ini,” jawab Adipati. “Dan dari bapak ibu sekalian.”
Malam itu, ia menyusun papan tulis darurat. Kolom-kolom dengan kapur: logistik, konsumsi, kesehatan, data warga rentan. Basic life skills berubah menjadi basic community skills. Kota yang besar mengecil ke beberapa meter persegi, cukup untuk menampung manusia yang saling memerlukan.
Di pojok warung, Wirawangsa duduk dengan selimut tipis. Kakinya dingin. “Aku ini merasa seperti kain sisa,” ujarnya pelan.
“Pak,” kata Adipati, “kain sisa itu sering jadi taplak yang paling banyak dipakai. Jangan remehkan fungsi.”
Wirawangsa tertawa kecil. “Kowe iki pinter nguwongke wong.” Kau pandai memanusiakan manusia.
.
Pagi Setelah Banjir
Pagi datang dalam bentuk bau tanah yang kelelahan. Matahari mengusap perlahan. Jalanan bekas tergenang tampak seperti peta yang ditarik paksa; garis-garis lumpur membingkai rumah. Orang-orang membersihkan. Sapu lidi menjadi alat paling setia; di bawah sinar tipis, semua tampak mulia.
Di warung, Arya menghitung sisa beras dan mencatat kebutuhan. Puspa memotret, mengunggah ke akun komunitas. “Kita butuh sabun, selang, sarung tangan karet,” tulisnya. Notifikasi masuk seperti hujan baru: orang-orang menawarkan bantuan.
Jakfar datang membawa pompa air pinjaman. “Biar aku urus selokan.” Ia mengikat tali ke pinggang, turun, bekerja tanpa komentar. Adipati menghampiri. “Terima kasih, Far.”
“Tadi malam kita semua sama,” jawabnya pendek. “Kita semua cuma orang yang ingin hidup.”
Setelah pompa berhenti, Adipati duduk di trotoar, telapak tangannya perih. Ia menatap telapak itu lama-lama: ada garis-garis yang tak pernah ia baca, ada luka baru yang tak ingin ia namai. Di kepalanya, ibunya berbisik, “Ojo isin saka nol,” jangan malu dari nol. Sambil tersenyum, ia menulis lagi di buku kecil: “Menyapu lumpur lebih jujur daripada menyapu masalah ke bawah karpet.”
.
Pelatihan Kecil, Harapan Besar
Seminggu setelah banjir, balai RW kembali ramai. Di dinding, poster buatan Puspa: “Warung Belajar Warga: Foto Produk dengan Ponsel, Tulis Caption Jujur, Hitung Modal dengan Waras.” Wirawangsa duduk di baris depan. Jakfar di sisi kanan, pura-pura tidak tertarik tapi tak beranjak.
Adipati memulai dengan menyalakan proyektor pinjaman. “Kita mulai dari yang kita punya. Kamera ponsel, alas putih dari kain, cahaya dari jendela. Kita tidak mengejar sempurna; kita mengejar cukup jelas dan cukup jujur.”
Ia menunjukkan contoh: memotret baju batik di lantai, menahan kerutan dengan selotip yang disembunyikan di belakang, menulis caption yang tidak hiperbola. “Kalau bahannya rayon, bilang rayon. Kalau ada sisa jahitan, bilang ada—tapi juga bilang, ini karya tangan tetangga kita sendiri. Orang suka kejelasan.”
Kemudian ia mengajarkan membuat lembar modal: harga kain, biaya listrik, waktu kerja. “Kalau capek, itu juga biaya—kita beri nilai agar kita ingat mengistirahatkan diri.”
Wirawangsa mencoba memotret. Tangannya gemetar; beberapa foto buram. Puspa mendekat, memandu. “Ambil napas dulu, Pak. Tahan ponsel dengan dua tangan. Tarik pelan, lepas pelan.” Foto ketiga jernih. Wajah Wirawangsa merekah seperti kain yang baru dijemur.
“Aku iso, Le,” ucapnya perlahan. Aku bisa.
“Bapak bukan kain sisa,” sahut Adipati. “Bapak lembar utama dari buku ini.”
Tepuk tangan kecil terdengar. Jakfar mengangkat tangan. “Aku mau tanya. Kalau komentar orang di online pedas, harus bagaimana?”
“Sama seperti saat di dunia nyata,” jawab Adipati. “Tetap tenang. Ucapkan terima kasih atas masukannya. Bilang kita perbaiki. Kalau troll yang tidak mau berdialog, kita abaikan. Jangan beri bensin pada api yang tidak memanaskan siapapun.”
Jakfar mengangguk. Ada sesuatu di matanya yang turun beberapa derajat dari marah: belajar percaya.
.
Kabar dari Rumah
Di sore yang kurang angin, telepon masuk dari Sumenep. Ibunya sesak napas, mungkin karena cuaca yang tak menentu dan obat yang tidak teratur. Adipati merapikan baju dan berangkat ke terminal. Puspa menyelipkan amplop tipis. “Ini dari kas warung dan orang-orang yang mau urunan. Jangan ditolak.”
“Bagaimana aku membalas?” tanya Adipati.
“Dengan kembali,” jawab Puspa. “Dan melanjutkan apa yang kamu mulai di sini.”
Di bus yang bergerak seperti lagu lama, Adipati menatap sawah dan langit, mengingat masa kecil: belajar menanak nasi dengan kayu, membersihkan ikan di ember, menepuk-nepuk bantal agar tidak berdebu. Ia sadar: semua itu basic life skills yang diam-diam menyelamatkannya di kota. Kita sering mengejar gelar, lupa memeluk kecakapan asli—yang membentuk tulang belakang keberanian.
Ibunya menunggunya dengan senyum yang lebih kuat dari paru-paru. Di teras, mereka minum teh manis yang terlalu manis. “Kamu makin kurus,” kata ibunya.
“Biar bisa lari lebih kencang,” jawab Adipati. Mereka tertawa. Di malam itu, ia merapikan obat dalam kotak plastik, memberi label, membuat jadwal. “Obat itu seperti kata-kata baik, Bu. Tak harus banyak, yang penting tepat waktu.”
Dua hari kemudian, ibunya membaik. Adipati kembali ke Surabaya dengan rasa yang lain: rasa bahwa pulang bukan mundur; pulang adalah mengisi ulang.
.
Orang-Orang Menjadi Kota
Kota menyambutnya dengan berita-berita kecil: mural di gang selesai setengah, warung Arya kini menempelkan papan harga jujur—kopi, teh, listrik, kebersihan; Wirawangsa sudah membuat akun marketplace dan menjual dua potong kain; Jakfar diterima menjadi teknisi pompa di bengkel tetangga. Dan Puspa—Puspa membuat pameran kecil berjudul “Langkah Kecil Penjaga Kota” di aula kampung, menggambar tangan orang-orang yang bekerja saat banjir.
“Pameran?” tanya Adipati, terkejut.
“Bukan untuk gaya-gayaan,” jawab Puspa. “Supaya kita ingat bahwa kota ini bukan gedung-gedungnya, kota ini adalah orang-orangnya.”
Di pameran itu, Adipati melihat sketsa dirinya: mengangkat panci besar, keringat jatuh seperti hujan yang kalah. Ia menunduk lama, malu pada gambar yang begitu tulus. Di bawah sketsa, Puspa menulis: “Ia tidak paling kuat. Ia tidak paling pintar. Tapi ia berdiri di tempat yang pas.”
“Kenapa aku?” gumamnya.
“Karena kamu itu tali,” kata Puspa. “Tidak terlihat megah, tapi membuat tenda tidak ambruk.”
Adipati menatap matanya yang bening. Ada sesuatu yang hendak diucapkan, lalu urung. Mereka tertawa kecil, lalu diam panjang. Diam yang tidak canggung; diam yang punya kursi sendiri.
.
Seminar Kecil, Kota Besar
Undangan datang dari kelurahan: tolong isi kelas keterampilan hidup untuk karang taruna. “Aku?” kaget Adipati.
“Kenapa tidak?” Arya menepuk bahunya. “Sing ngerti dalan, sing tau kesasar. Yang tahu jalan adalah yang pernah tersesat.”
Di aula kelurahan, puluhan anak muda duduk setengah malas. Adipati membuka dengan pertanyaan, bukan nasihat. “Siapa yang pernah tidak punya uang sampai akhir bulan?” Banyak tangan terangkat. “Siapa yang pernah bertengkar di grup organisasi?” Lebih banyak tangan. Tawa pecah. Jarak runtuh.
Ia menulis di papan: Masak, Cuci, Hitung, Dengarkan, Bicara, Menolak, Meminta Maaf, Meminta Tolong, Bertanya, Mencatat, Menyimpan Arsip, Pertolongan Pertama, Peta & Arah, Mengelola Emosi. “Ini kurikulum kita,” katanya. “Tidak ada gelar, tidak ada toga. Tapi kalau kita kuasai, kita bisa berdiri di mana saja.”
Ia mengajak mereka praktik: memasak telur ceplok tanpa gosong, mencuci piring tanpa boros air, mengelola uang saku dalam amplop; ia memperagakan menolak ajakan yang tidak perlu dengan kalimat sederhana, “Terima kasih, tapi aku belum bisa. Aku punya janji pada diriku sendiri.” Ia memperagakan meminta maaf tanpa tetapi, meminta tolong tanpa terpaksa. Ia memberi contoh mendengar: menatap mata, mengangguk, tidak memotong. Ia mengeluarkan kotak P3K, menjelaskan luka lecet, luka sayat, pingsan.
“Kenapa repot-repot?” tanya seseorang.
“Karena kota ini seperti laut,” jawab Adipati. “Kalau kamu tidak bisa berenang, kamu akan tenggelam. Kalau kamu bisa mengapung—menguasai hal-hal kecil—kamu bisa menunggu pertolongan atau malah menolong.”
Seusai kelas, seorang gadis mendekat. “Mas, caranya supaya tidak mudah marah bagaimana?”
“Latih napas,” jawab Adipati. “Hafalkan kalimat ini: ‘Aku memilih kata-kata yang menyelamatkan.’ Ucapkan dalam hati sebelum bicara. Kalau perlu, mundur sebentar. Diam juga keterampilan.”
Gadis itu tersenyum. Ia mengulang pelan-pelan, seperti menghafal mantra.
.
Malam yang Mengharukan
Malam itu, di warung Arya, mereka berkumpul tanpa agenda. Puspa membawa gitar kecil; Jakfar membawa cerita lucu; Wirawangsa membawa kain motif bunga yang baru jadi. “Untuk taplak di sini,” katanya. “Warung ini sudah jadi rumah darurat waktu banjir.”
Arya menaruh taplak itu. Warna birunya menyejukkan, menenangkan mata yang lelah. “Kita foto,” kata Puspa. “Aku mau unggah dengan caption: ‘Kebaikan adalah kain yang menutup meja luka.’”
Mereka tertawa. Lalu hening. Ada jenis hening yang tiba-tiba membuat udara menebal; orang-orang seperti menatap ke dalam diri sendiri dan menemukan anak kecil yang dulu pernah ingin menjadi seseorang. Seseorang yang bisa apa saja. Seseorang yang disorot lampu. Seseorang yang tidak pernah takut.
“Dulu,” kata Adipati pelan, “aku pikir ekspektasi orang itu beban. Sekarang aku tahu, ekspektasi itu peta. Peta tidak selalu benar, tapi tanpanya kita bisa tersasar lebih lama.”
Puspa menatapnya, ada air yang berpendar di pojok mata. “Lalu kamu mau ke mana?”
“Ke tempat yang tidak menjanjikan tepuk tangan,” jawabnya. “Ke tempat orang sedang belajar berdiri.”
Di luar, motor melintas. Di dalam, seseorang mulai bersenandung. Malam melipat kota seperti kain taplak yang baru disetrika.
.
Ketika Lampu Padam
Beberapa hari kemudian, listrik padam di separuh kampung. “Byar-pet nasional,” orang-orang bercanda. Anak-anak menjerit gembira, orang dewasa menjerit pelan. Telepon menjadi senter, senter menjadi matahari darurat. Di warung Arya, mereka menyalakan lilin. Wajah-wajah seperti relief candi—terang di satu sisi, gelap di sisi lain.
“Mana buku kecilmu?” tanya Arya.
Adipati mengeluarkan buku itu. Halamannya penuh coretan. Ia membuka halaman kosong dan menulis judul besar: “Saat Lampu Padam.” Lalu ia mencatat: bekal air minum, informasi cadangan, cara menghemat baterai, giliran jaga, kalimat untuk menenangkan lansia, permainan tradisional untuk menenangkan anak, cara menyimpan makanan, cara mematikan kompor yang lupa dimatikan. Ia memimpin menggambar peta evakuasi sederhana.
“Kalau nanti ada kebakaran?” tanya seorang ibu.
“Air jangan langsung disiram ke minyak,” jawab Adipati. “Kita tutup pakai kain basah. Panik itu api kedua. Kita matikan dengan informasi.”
Malam itu terasa panjang tapi penuh makna. Di tengah gelap, orang-orang belajar melihat. Ketika listrik menyala kembali, sorak meledak. Namun di antara sorak, ada sesuatu yang lebih halus: rasa percaya bahwa mereka bisa mengatasi hal-hal kecil bersama-sama.
.
Surat ke Diri Sendiri
Di kamar kosnya, setelah semua itu, Adipati menulis surat untuk dirinya sendiri:
**“Di, hidup mandiri bukan berarti hidup sendirian. Kota ini multi dimensi, multi kultural, dinamis. Jangan pernah merasa paling benar. Belajar memasak, menyapu, menabung, meminta maaf, meminta tolong. Belajar memimpin kalau diperlukan, belajar mengikuti kalau ada yang lebih paham. Jadilah seseorang yang bisa diandalkan saat orang-orang mencari arah. Ingat: lampu sorot akan padam, tetapi tugas-tugas kecil tidak pernah mati. Lakukan dengan cinta. Lakukan dengan tenang. Lakukan sampai tanganmu hafal gerakannya.
Kalau suatu hari kamu lupa siapa dirimu, datanglah ke warung kecil di tepi jalan. Di sana, panci akan tetap bernapas, kopi tetap bermakna, dan teman-temanmu menunggu tanpa banyak tanya.”**
Ia menutup buku. Dari jendela, lampu kota berkerlip seperti morse raksasa. Ia membalas dengan senyum yang kecil. Kadang, kecakapan paling sulit adalah mensyukuri kemarin, bukan merencanakan besok.
.
Kota yang Mengajar
Beberapa bulan berselang, mural di gang selesai: gambar tangan-tangan yang saling mengikat, dengan tulisan “Singkat kata: kita butuh satu sama lain.” Warung Arya semakin rapi, dengan alur kerja yang ditempel di dinding: masak, cuci, simpan, catat, evaluasi. Wirawangsa punya pelanggan dari luar kota; ia mengirim kain dengan catatan kecil, “Terima kasih sudah percaya pada tangan-tangan kecil kami.” Jakfar mulai bisa menahan napas sebelum bicara. Puspa diterima magang di studio desain sosial; ia menulis pesan panjang pada Adipati: “Terima kasih telah mengajariku bahwa desain terbaik adalah ruang yang membuat orang merasa berguna.”
Di trotoar Gubeng, Adipati berjalan tanpa terburu-buru. Ia bukan siapa-siapa bagi baliho besar. Namun di buku kecil sebagian warga, namanya ada di samping kata “hubungi kalau bingung.” Ia tersenyum. Itu cukup.
Ia menoleh ke langit yang sering murung, lalu menulis satu kalimat terakhir di buku kecilnya:
“Ekspektasi untuk menguasai basic life skills bukan beban; itu adalah cara paling manusiawi untuk mencintai diri sendiri dan sesama di kota yang selalu bergerak.”
.
.
.
Jember, 9 September 2025
.
.
#CerpenIndonesia #KompasMinggu #BasicLifeSkills #HidupMandiri #Surabaya #SastraKota #SolidaritasWarga #UMKMDigital #NamakuBrandku