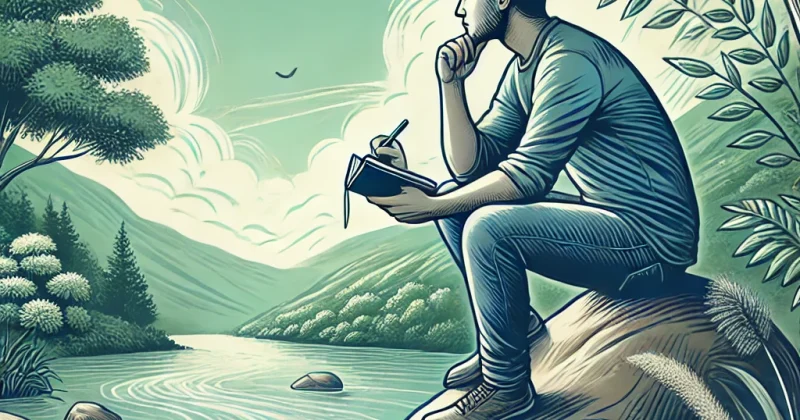Ketika Lelaki Baik Akhirnya Berkata Cukup
“Amarah yang tersimpan di balik hati yang baik, adalah badai paling dahsyat yang tak seorang pun ingin bangkitkan.”
.
Malam itu Jakarta tampak seperti layar LED raksasa yang kelelahan: menyala, berganti gambar, lalu menguap dalam kabut lembab. Dari balkon lantai dua puluh sebuah apartemen di sudut Kuningan, Ranggalawe memandang lampu-lampu yang berdetak seperti denyut nadi kota. Ia menatap jauh, melewati atap-atap gedung, sampai pada dirinya sendiri yang kecil di jendela kaca—lelaki yang dikenal santun, tak pernah meninggikan suara, dan selalu bisa diandalkan.
Di kantor, ia adalah event strategist pada sebuah biro komunikasi yang banyak menangani program pemerintahan: kampanye ekonomi kreatif, festival pendidikan vokasi, konferensi energi terbarukan. Pada kartu namanya tercetak huruf-huruf yang rapi, tetapi yang tak pernah tercetak adalah jam-jam lembur, ide-ide yang digeser nama lain, dan penyangga-penyangga mental yang ia paku sendiri setiap pulang larut.
Orang-orang memujinya: tidak ribut, tidak ambisius, tidak cari panggung. Lalu sedikit demi sedikit, “tidak” itu berubah jadi “bisa dimintai tolong.” Tolong revisi malam ini. Tolong susun konsep yang “aku sebut saja nanti sebagai arahan tim.” Tolong bantu tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya. Dan orang yang paling lihai memintanya adalah Wiradikara—atasan yang fasih tersenyum di depan pejabat, lihai menggeser kredit di balik layar.
“Mas Rangga ini andalan kita,” kata Wiradikara di rapat, menyentuh punggung Ranggalawe di depan klien. “Nanti detailnya saya rapikan, ya.” Detail yang dimaksud adalah ide Rangga yang akan tampil dengan suara Wiradikara.
Di rumah, badai berputar pada poros yang berbeda. Apartemen itu awalnya dibeli dengan uang muka tabungan Rangga dan pinjaman bank. Ia mengajak adiknya, Anggara, untuk tinggal sementara—hingga “sekolah lagi atau kerja dulu,” katanya dua tahun lalu. Nyatanya, “sementara” menjelma sofa-sofa penuh kemasan makanan, pintu yang tak pernah benar-benar tertutup ketika teman-teman datang, sepatu-sepatu yang diletakkan di jalur sempit depan lift, dan tagihan kartu kredit yang anehnya melonjak ketika Rangga merasa tidak pernah membelanjakan apa-apa.
“Bang, pinjam dulu ya, nanti aku ganti begitu logo klienku di-approve,” kata Anggara, mantan mahasiswa desain yang drop out dan sedang “eksperimen” menjadi freelancer. Kata “nanti” adalah buku tabungan kosong yang tetap disodorkan ke teller harapan.
Ema Ratnasih, ibu mereka di Pamekasan, menelpon setiap malam Jumat. Suaranya adalah angin yang menidurkan masa kecil: lembut, hangat, sejuk. “Sabarlah, Rangga. Namanya juga adikmu. Dia butuh disayangi biar tak salah langkah.”
Rangga mengangguk, selalu mengangguk. Pada telepon, pada atasan, pada hidup yang meminta tanpa tahu caranya mengembalikan.
.
Ia menyiapkan ruang nafasnya sendiri, bernama Ruang Huma Kenanga—bukan miliknya, melainkan milik sahabat lamanya, Kenanga, seorang psikolog yang merangkai ilmu klinis dengan Bach Flower Remedy. Di rumah kayu sederhana di pinggir Setiabudi, ada bau air rebusan jahe dan buku, ada remang lampu yang memanjangkan sabar, ada kursi anyaman yang mengerti berbagai jenis tangis.
“Kamu seperti danau di musim kemarau,” ujar Kenanga pada sesi pertama setelah lama tak bertemu, suaranya tidak menghakimi. “Permukaanmu terus memantulkan langit. Indah. Orang senang memandangnya. Tapi berapa lama lagi kita bisa berpura-pura tak ada pusaran di bawah?”
Rangga menghela napas. “Aku tidak tahu caranya menolak. Kata ‘tidak’ seperti batu di lidah. Keras. Berat. Kalau kulempar ke muka orang lain, aku takut melukai.”
Kenanga meramu sebotol kecil tetes bunga dan menuliskan formula: centaury untuk yang terlalu mudah mengiyakan, walnut untuk transisi, larch untuk keyakinan, dan pine untuk rasa bersalah yang tak perlu. “Ini bukan sihir,” katanya. “Ia hanya membantu menenangkan. Selebihnya, kamu yang menentukan garis di peta hidupmu.”
“Garis?” Rangga mengulang.
“Batas. Boundary. Bukan untuk jadi dingin. Tapi agar kamu tetap utuh.”
.
Seminggu setelahnya, kantor menjadi panggung utama yang menguji batas. Ada proyek besar bernama “Festival Ekonomi Kreatif Nusantara”—sebuah festival yang diharap menjadi etalase: seni bertemu industri, UMKM bertemu investor, kota-kota bertemu cerita. Rancangan awalnya: tiga hari, empat zona, lima panggung, satu narasi yang menyulam identitas dan bisnis. Narasi itu adalah milik Rangga. Ia merumuskan tagline, merancang alur pengunjung, mengatur pengalaman yang menyentuh—agar setiap langkah menjadi kisah, setiap transaksi menjadi pertemuan, setiap panggung menjadi jembatan.
Presentasi internal berjalan mulus sampai tiba di meja Wiradikara. “Ini bagus,” katanya, “tapi kita sederhanakan diksi agar mudah dipahami pejabat pusat.” Esoknya, di hadapan gubernur dan kementerian, narasi itu meluncur dari mulut Wiradikara tanpa satu pun “terima kasih” kepada pengarangnya. Tepuk tangan menutup pertemuan, genggaman hangat berpindah ke telapak Wiradikara. Nama Rangga lenyap dalam bilik udara.
Malamnya, apartemen berubah menjadi ruang pesta kecil. Anggara dan dua kawannya, Jokotole dan Cakra, memutar musik EDM dari speaker portable. Kaleng-kaleng minuman berjejal di meja kaca, sisa minyak ayam goreng mengambang di piring aluminium. Rangga baru masuk ketika Jokotole melangkah mundur tanpa melihat, menabrak meja sepatu, menumpahkan minuman manis ke sepatu kulit favorit Rangga—hadiah dari bonus tahun lalu yang tak besar tapi berarti, sepatu yang ia rawat bagai jabat tangan kepercayaan dirinya.
“Oh, sorry, Bang,” kata Jokotole, tanpa benar-benar menatap. Anggara tertawa canggung. “Bro, besok aku pinjam motor ya. Ada meeting sama klien. Janjian di Senopati.”
Rangga menatap sepatu yang basah, menatap wajah adiknya, menatap jam yang melewati tengah malam. Di kepalanya, suara Kenanga pelan: “Garis.” Di dadanya, ada sesuatu yang lama-lama menepi, lalu berdiri.
“Tidak,” ucapnya, pertama kali dengan bibir yang mantap, “Keluar dari rumah ini malam ini juga.”
Musik berhenti. Udara jatuh. Anggara memandang seperti baru mengenal wajah kakaknya. “Bang, kita bisa ngomong baik-baik.”
“Sudah terlalu lama kita ‘baik-baik’ hanya untuk menjaga kenyamananmu. Aku bukan ATM. Bukan sopir. Bukan peredam salahmu. Aku kakakmu, dan tugasku menjaga agar kamu tidak menghancurkan dirimu sendiri. Malam ini kamu cari tempat lain. Besok kamu cari pekerjaan yang benar. Dan kalau kamu mau pulang suatu hari nanti, kamu datang sebagai orang yang menghormati rumah.”
Diam panjang. Cakra memungut tas, Jokotole mematikan speaker. Anggara bergerak lambat, mulutnya ingin menyusun pembelaan, tapi tidak ada bahasa yang cukup. Mereka pergi, pintu menutup seperti tanda tangan besar pada kontrak baru: perjanjian antara Rangga dan dirinya sendiri.
Rangga membersihkan tumpahan dengan tangan gemetar. Ia duduk di lantai, memandang sepatu. Sepatu itu masih bisa dipakai, pikirnya. Mungkin esok ia bawa ke tukang sol. Mungkin ada yang bisa diselamatkan. Hatinya? Ia belum yakin. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa mimpi dikejar-kejar oleh rapat, tagihan, dan tawa yang tidak sopan.
.
“Sudah terjadi?” tanya Kenanga ketika Rangga duduk di kursi anyaman pada sore berikutnya.
Rangga mengangguk. “Aku takut setelahnya aku akan menyesal. Tapi yang kurasakan hanya… lega.”
“Bukan amarah yang memandumu,” kata Kenanga, menuang teh hangat, “melainkan rasa hormat pada dirimu sendiri. Ada bedanya.”
Mereka berbincang tentang batas—bukan tembok, melainkan pagar kecil dengan pintu yang terkunci rapi: siapa pun bisa masuk, asalkan mengetuk. Mereka membahas cara-cara praktis yang tak diajarkan sekolah: cara bilang “tidak” tanpa merasa jahat; cara mengutarakan harapan dalam rapat tanpa terdengar memamerkan; cara menulis perjanjian kerja sama yang adil. Kenanga menuliskan “rencana pulih” seperti menuliskan resep: ubah sandaran, bukan memutus silaturahmi; latih keberanian dengan kalimat pendek; pelihara tubuh—tidur cukup, makan seperlunya, berjalan.
“Pulih,” kata Rangga pelan, “rasanya kata itu seperti pesisir setelah badai.”
“Pulih bukan kembali seperti semula,” jawab Kenanga. “Pulih adalah tiba sebagai versi dirimu yang lebih jujur.”
.
Perubahan yang kecil-kecil ternyata memberi gema yang besar. Di rapat berikutnya, Rangga—dengan telapak tangan yang masih berkeringat—mengangkat suara ketika Wiradikara hendak menutup presentasi “Festival Ekonomi Kreatif Nusantara”.
“Sebelum kita akhiri, saya mengusulkan agar dokumen final mencantumkan nama tim kreatif sesuai kontribusi. Selain adil, ini akan membantu kita membangun kultur kerja yang sehat. Saya siap menuliskan pembagian peran yang jelas.”
Ruang rapat hening dua detik. Seorang rekan, Sekarputri, menatap Rangga dengan mata yang menyala kecil, kemudian mengetuk meja pelan. “Setuju,” katanya. Tetap tenang, tetap rapi, tetapi kalimat itu seperti meletakkan batu pertama di sebuah jembatan.
Wiradikara tersenyum tipis. “Baik. Nanti kamu susun yah,” suaranya berkendara di antara diplomasi dan dominasi. Namun sejak hari itu, kredit tidak lagi bisa melenggang liar tanpa saksi.
Di rumah, Anggara pindah ke rumah kontrakan bersama kawannya. Minggu-minggu pertama berlalu seperti jalan lengang yang tetap membuat tegang—sepi kadang lebih berisik daripada pesta. Telepon Ema membawa kabar: “Anggara sering ke warung bu Lis bantu-bantu desain kemasan. Katanya dia juga ikut kursus singkat di BLK. Doakan, ya.” Suara Ema memintal harapan kecil, tidak mewah, tidak dramatis, tetapi cukup untuk menyalakan lampu di teras.
.
Jakarta yang sama pelan-pelan tampak berbeda. Lampu-lampu gedung masih berkedip, tetapi kini Rangga melihat jeda di antaranya. Ia belajar berangkat lebih pagi, turun di stasiun MRT, berjalan kaki melewati deretan pohon tabebuya yang suatu hari berbunga seperti kertas warna-warni dijatuhkan dari langit. Ia mampir ke toko sol sepatu tua di Benhil. Tukangnya—lelaki berambut putih bernama Panji—menerima sepatu yang basah itu dengan tangan penuh bekas lem.
“Masih bisa,” kata Panji, “Saya ganti lining-nya, saya poles, saya jahit ulang bagian yang sobek. Sepatu yang dirawat suka balik sayang.”
“Kayak orang,” gumam Rangga.
Panji mengangguk, seperti memahami percakapan yang tidak diucapkan. “Kalau mau awet, tahu kapan dipakai dan kapan diistirahatkan.”
Kalimat sederhana, tapi menempel lebih dalam dari ceramah-caramah manajemen waktu yang pernah Rangga dengar.
.
Festival yang disusun setengah tahun itu akhirnya berlangsung di Kemayoran. Panggung-panggungnya berdiri seperti kapal, lampu-lampu rapi, stan-stan UMKM menata kain, keramik, kopi, chocolate bean-to-bar. Jalur pengunjung mengalir seperti sketsa yang berubah menjadi arus manusia. Gubernur membuka acara, kementerian bergantian memberi kata sambutan. Di layar besar, rundown memajang “Tim Kreatif” dengan huruf yang sama besar dengan “Ketua Panitia.” Nama Rangga ada di baris kedua. Ia tidak bersorak, hanya mencatat bahwa di antara keramaian, keadilan sesederhana menulis nama.
Di area panggung literasi, seorang penulis yang dulu jadi idolanya mengatakan kalimat yang kemudian ditulis Rangga di catatan telepon: “Kita punya dua pilihan di hidup dewasa: jadi komposer yang mengarang musiknya sendiri, atau jadi alat musik yang dipakai banyak orang tanpa pernah didengarkan nadanya.” Ia pulang dengan rasa lelah yang bersih—letih karena bekerja, bukan karena diremehkan.
Di tengah keramaian itu, ponsel Rangga bergetar. Pesan dari Anggara:
“Bang, aku dapat project kecil desain kemasan sambal bu Lis. Enggak besar, tapi aku dikasih DP. Minggu depan aku bayar setengah dari uang yang dulu aku pinjam, ya. Maaf sudah lama. Aku lagi belajar untuk gak ngutang sama masa depan.”
Rangga menatap layar lama-lama. Dadanya terasa ditempeli sesuatu yang hangat. Ia membalas, singkat, “Terima kasih sudah berusaha. Jaga dirimu.” Hapus, lalu menulis ulang: “Aku percaya kamu bisa rapi hidupmu.” Ia menekan kirim, dan merasa ada kursi kecil yang ditarik untuk duduk bersama kedewasaan.
.
Beberapa bulan berlalu, dan hidup memilih cara-cara halus untuk menguji keteguhan. Wiradikara meminta Rangga mengerjakan konsep “secepatnya ya malam ini” tanpa kompensasi jelas. Rangga menulis email rapi: menyetujui pekerjaan dengan mencantumkan batas, jam, dan rincian honor. Ia bukan sedang tawar-menawar; ia sedang membangun pagar yang pintunya jelas.
“Mas Rangga sekarang sistematis sekali,” komentar Sekarputri pada ruang pantry. “Dulu kamu… ya, mengalir saja.”
Rangga tersenyum. “Aku belajar dari danau. Permukaan memang seharusnya tenang. Tapi dasar danau perlu dipetakan, supaya kapal tidak karam.”
Di Ruang Huma, Kenanga menepuk bahu Rangga ketika lelaki itu menceritakan perubahan kecil-kecil hariannya: jadwal makan yang tidak lagi dilompati, jam tidur yang menjadi disiplin, berjalan 7.000 langkah sehari di trotoar yang sempit tapi cukup, menolak rapat yang tidak perlu, menyimpan ponsel satu jam sebelum tidur. “Tubuh yang terasa aman memudahkan hati untuk jujur,” kata Kenanga.
“Lucunya,” kata Rangga, “ketika aku berhenti menjadi spidol untuk menulis hidup orang lain, orang lain mulai mengundangku untuk menulis bersama, bukan menulis untuk mereka.”
“Karena mereka kini melihatmu,” jawab Kenanga, “bukan hanya melihat manfaatmu.”
.
Suatu senja di Situ Lengkong—danau kecil di sudut kompleks perkantoran yang tak jauh dari tempat Rangga bekerja—langit seperti surat yang lama ditulis, lalu dilipat. Angin menyisir permukaan air, menciptakan riak yang menenun. Rangga duduk di bangku beton, menaruh ponsel, dan membiarkan telinganya diisi suara yang bukan notifikasi.
“Dulu aku kira pulih itu seperti memutar ulang cerita ke bab pertama,” katanya pada Kenanga yang duduk di sampingnya, “kembali ke masa sebelum keruwetan. Tapi ternyata tidak. Pulih adalah menulis bab berikutnya dengan pena milikku sendiri.”
“Dan menerima bahwa ada halaman yang tidak perlu dibaca ulang,” sahut Kenanga.
Rangga menarik napas, aromanya seperti kue-kue di rumah masa kecilnya. “Aku ingin mengirim pesan ke ibu malam ini. Mengabarkan aku baik-baik. Mengabarkan juga bahwa aku tidak marah pada Anggara. Aku lebih marah pada diriku yang dulu lupa menjaga.”
Kenanga tersenyum. “Kemarahan yang jujur pada diri sendiri bisa jadi pelita, kalau kau pakai untuk melihat jalan, bukan membakar rumah.”
Mereka diam, bukan karena kehabisan kata, melainkan karena ada kalimat-kalimat yang baru bisa dipahami dengan hening.
.
Sore itu, Rangga pulang dan menulis di buku catatan—kebiasaan yang dihidupkan kembali. Ia menulis kalimat yang mungkin suatu hari akan ia temukan lagi di tengah kesibukan dan lupa:
“Menjadi baik itu mulia. Tetapi membiarkan diri disakiti terus-menerus bukanlah bentuk kemuliaan—itu pengkhianatan terhadap diri sendiri.”
Ia menutup buku, menatap sepatu yang dulu basah, kini mengilap dengan jahitan baru. Ia mengenakannya besok untuk presentasi—bukan karena sepatu itu mahal, melainkan karena sepatu itu mengingatkannya: sesuatu yang dirawat, dipoles, dijahit ulang, bisa kembali menapak lebih tegak. Tak lagi takut pada kubangan, karena tahu caranya mengering.
Malam pun turun seperti tirai yang menutup panggung. Tetapi untuk pertama kalinya setelah lama, panggung itu bukan lagi milik orang lain. Dan ketika teleponnya bergetar, muncul pesan singkat dari Anggara:
“Bang, aku mau mampir hari Minggu. Bawa sate madura. Kita makan di balkon. Aku janji bawa piring sendiri dan bersihin sendiri.”
Rangga tertawa kecil. Ia membalas dengan sebuah kata yang dulu terasa begitu berat, kini menjadi kata paling ringan di genggaman orang yang pulih: “Boleh.”
Lampu-lampu kota berkedip. Di tepian langit, ada garis tipis yang memisahkan malam dari esok hari. Garis itu bukan tembok. Ia adalah pagar dengan pintu yang bisa dibuka dan ditutup. Di baliknya, seorang lelaki baik duduk, akhirnya berani berkata cukup, dan justru karena itu, hidup mulai cukup juga untuknya.
.
Pulih
“Jangan dorong orang baik terlalu jauh. Karena saat ia meledak, bukan hanya akan melukai, tapi mungkin tak akan pernah kembali seperti semula.”
Kini Ranggalawe tahu: diam bukanlah kesabaran jika membuat dirinya hancur. Batas bukanlah benteng keangkuhan, melainkan pagar keselamatan. Cinta pada diri sendiri bukan egoisme; ia adalah izin untuk menjadi manusia yang lengkap—yang bisa berkata ya tanpa merasa dikerjai, dan bisa berkata tidak tanpa merasa berdosa.
Dan Kenanga tahu, lelaki itu akhirnya pulih—bukan semata karena tetes bunga atau daftar strategi, melainkan karena hati yang memutuskan untuk tidak menyalakan lampu rumah orang lain sambil membiarkan rumahnya sendiri padam.
Di langit Jakarta yang penuh reklame, ada bintang yang tidak dijual: keberanian untuk menyebut nama sendiri pada hidup yang kita jalani.
.
.
.
Jember, 8 Juli 2025
.
.
#BatasDiri #SelfRespect #KesehatanMental #CerpenIndonesia #KompasMinggu #KehidupanUrban #KakakAdik #Pulih #CeritaMotivasi #JeffreyWibisonoStyle
.
Quotes untuk pembaca
-
“Kesabaran tanpa batas sering kali hanya kedok dari batas yang tak pernah kita tetapkan.”
-
“Hidup dewasa adalah seni memilih: kapan mengalah untuk damai, kapan tegas untuk sehat.”
-
“Kebaikan yang sehat selalu menggandeng ketegasan yang jujur.”