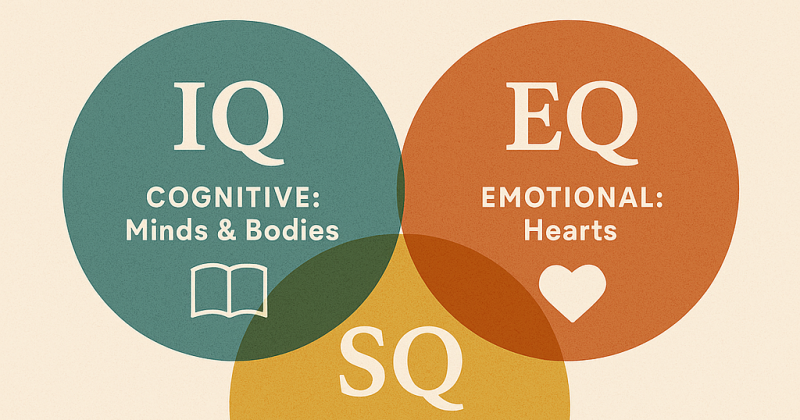Benang Tak Kasatmata
“Kadang hidup mempertemukan dua jiwa bukan karena mereka saling mencari, tapi karena semesta punya skenario yang lebih paham dari logika manusia.”
“Jika cinta adalah benang, maka waktu adalah jarum. Dan semesta hanyalah penjahit sabar yang menunggu momen paling tepat untuk menyatukan dua ujungnya.”
.
Gerimis dan Perempuan yang Tak Lagi Bertanya
Jakarta pagi itu lembap. Gerimis jatuh tipis seperti napas langit yang letih, menempel pada kaca-kaca tinggi gedung perkantoran yang berbaris seperti cermin-cermin raksasa. Di pojok kafe kecil di Cikini—bangku kayu yang selalu berderit tiap kali digeser—Dewi Rengganis duduk membungkuk, hoodie abu-abu menutupi lehernya. Di hadapannya, secangkir kopi hitam yang sengaja dibiarkan dingin, dan buku catatan lusuh penuh puisi setengah jadi.
Rengganis bukan perempuan yang lemah; ia hanya pernah terlalu percaya. Ia tumbuh di keluarga kelas menengah ke atas yang disiplin soal kesempatan: sekolah bagus, kursus musik, studi ke luar negeri, kemudian pekerjaan yang “pantas” untuk gelar dan reputasi. Namun perihal hati, tak ada kurikulum yang pasti. Ia pernah dicintai oleh seseorang yang lihai menyebut kata “selamanya” tapi mudah berpindah saat kalender berganti. Sejak itu, ada retak yang tak cukup ditambal oleh waktu—semacam lubang kecil yang membuat setiap kebahagiaan bocor perlahan.
Ia menutup catatan dan memandang ke luar. Di trotoar, payung-payung hitam bergerak seperti bintik-bintik tinta yang mengambang. Ia menghela napas, mencoba mengingat bahwa pulih bukan lomba cepat-cepat. Menulis membantu menahan diri agar tidak pecah: satu baris puisi setiap pagi, satu halaman esai setiap Senin, satu kalimat jujur setiap kali cemas datang tanpa permisi.
Di layar ponsel, notifikasi rapat Zoom dari kampus tempat ia menjadi dosen tamu menyala. Topiknya tentang “sastra urban dan empati publik”—bahasan yang sejak lama ia pakai untuk berdamai dengan kota: membiarkan Jakarta yang bising menjadi karakter, bukan musuh.
.
Pulang Bukan Selalu tentang Rumah
Di sisi lain kota, MRT Setiabudi memuntahkan penumpang dengan ritme mekanis. Jayengrana melangkah keluar, menyeret koper kabin yang roda-rodanya berdecit halus. Setelah empat tahun di Singapura sebagai analis strategi di perusahaan teknologi, ia memutuskan pulang: bukan karena rindu, melainkan karena lelah menawar dirinya di rapat-rapat tak selesai, karena kangen makan soto Betawi di warung dekat rumah, dan karena ingin berhenti menunda hal-hal yang tak pernah ia berani namai.
Kota menyambutnya dengan billboard raksasa, aplikasi transportasi yang berlomba memberi promo, dan jemari ibu di rumah yang lebih hangat daripada heater mana pun. Namun ada ruang kosong yang sulit ia jelaskan; semacam jeda di antara dua lagu yang belum ia isi dengan nada.
Ia membuka email: tawaran kerja di Berlin masuk dengan subjek yang mencolok. Gaji besar, tim internasional, proyek masa depan. Pikirannya berdesis: kesempatan. Hatinyajustru berbisik: apakah perjalananmu selalu harus diukur dengan jarak dan angka?
.
Tatap Pertama di Peron yang Basah
Hari itu, gerimis lebih sabar daripada lampu lalu lintas. Jayengrana naik rangkaian terakhir di Stasiun Dukuh Atas, sementara Rengganis masuk dari pintu yang sama, mengempit jas hujan tipis yang pola daunnya sudah pudar. Kereta mendadak mengerem pelan, tubuh mereka bersenggolan, buku catatan nyaris terjatuh.
“Maaf…” Rengganis refleks menunduk, tangannya menahan buku sekaligus menahan degup yang seketika, entah mengapa, ingin berlari.
“Tidak apa,” jawab Jayengrana, senyum sekilas tercetak di sudut bibirnya—senyum yang tidak memaksa, tidak menahan, hanya lewat dan tinggal seperti jejak sepatu di lantai basah.
Kereta melaju lagi. Di jendela, lampu-lampu kota seperti bintang yang ditarik-tarik garisnya oleh hujan. Mereka berdiri dalam diam. Di kepala Rengganis, satu kalimat pendek menyalakan diri: mungkin hidup hanya meminta kita saling melihat dulu, sebelum saling menyapa.
.
Pertemuan yang Terlalu Konsisten untuk Disebut Kebetulan
Setelah hari itu, kota seperti punya kebiasaan baru: mempertemukan mereka di trotoar, di minimarket dekat Rasuna, di toko buku tua di Taman Ismail Marzuki yang aroma kertasnya mengembalikan ingatan Rengganis pada ruang perpustakaan di masa kecil. “Jakarta ini kecil, atau semesta sedang bercanda?” batin Jayengrana setiap kali melihat sosok itu lagi—hoodie, tas kain, mata yang sembari tertawa masih menyisakan luka di ujungnya.
Mereka belum saling menyapa, tetapi jarak di antara mereka menyusut seukuran pengakuan: sama-sama penumpang kota yang suka berhenti di halaman-halaman sunyi.
.
Payung Hitam, Jalan Basah, dan Percakapan Pertama
Sore itu hujan mendadak seperti amarah yang tak punya rencana. Kereta berhenti total akibat gangguan listrik. Rengganis terjebak di bawah jembatan penyeberangan, ponselnya mati kehabisan baterai. Ojek daring berganti status driver unavailable. Warung kopi tua di bawah jembatan menyalakan lampu neon yang gemetar.
“Sini,” suara itu tiba-tiba ada di sampingnya, menawarkan payung hitam besar yang seluruh sisi kainnya sudah bercerita tentang banyak hujan. Jayengrana tidak basa-basi, tidak memaksa. Mereka berjalan berdua, ritme langkah menyelaraskan diri tanpa kesepakatan.
Di warung kopi tua, mereka duduk di kursi plastik yang dingin, memesan kopi tubruk dan roti bakar keju. Percakapan pertama mereka sederhana, tetapi jujur: tentang musik lama yang sering diputar bapak Rengganis tiap Minggu pagi; tentang konser jazz di Esplanade yang Jayengrana tonton sendirian; tentang mantan yang hilang tanpa pamit, meninggalkan ghosting yang dinginnya lebih lama dari musim hujan.
“Kenapa kita percaya pada orang-orang yang akhirnya pergi?” tanya Rengganis, setengah kepada dirinya sendiri.
“Mungkin karena percaya adalah satu-satunya cara kita tinggal,” jawab Jayengrana, pelan. “Kalau tidak percaya, kita selalu pulang paling cepat. Padahal rumah kadang butuh kita berlama-lama, untuk tahu letak lampunya.”
Malam itu mereka tidak jatuh cinta. Mereka hanya membuka jendela kecil di dalam dada masing-masing, membiarkan angin dari orang lain lewat dan mengganti udara yang pengap. Itu saja—dan justru itu yang membuatnya berarti.
.
Kebersamaan yang Tak Bernama, Tapi Terasa
Hari-hari berikutnya mengikuti pola yang tak disusun siapa pun. Rengganis mengajar, menulis, membuka kelas kecil tentang “Menulis untuk Bertahan Hidup”. Jayengrana mulai freelance consulting, mengurangi rapat yang menyeretnya ke jam-jam terlalu larut. Mereka bertemu tanpa janji: di pameran foto di Galeri Nasional, di bazar buku kampus, di pasar kue subuh saat insomnia menolak kompromi.
Mereka bukan kekasih, bukan sekadar teman. Mereka adalah semacam rumah sunyi yang berdua mengerti bunyi masing-masing. Tidak ada janji yang dipahat, tidak ada definisi yang dipaksa. Mereka belajar satu hal yang dulu sering gagal mereka lakukan: menunggu dengan baik.
Rengganis mengajak Jayengrana ikut kelas menulisnya. “Bukan untuk jadi penulis,” katanya. “Tapi supaya kamu ingat bahwa perasaan yang tidak ditulis akan mencari panggung yang lebih keras.” Jayengrana datang, duduk di barisan belakang, menulis dua paragraf pendek tentang hujan dan ibu. Rengganis membacanya dan memuji cara ia menahan kalimat di tepi batas. Mereka tertawa, lalu diam, lalu saling menyadari bahwa kedekatan bisa serapih itu: tanpa harus mengucap, tanpa harus menguasai.
.
Tawaran ke Berlin dan Sebuah Halaman yang Disobek
Email itu akhirnya dijawab. Berlin memberi waktu dua minggu untuk memutuskan. Jayengrana resah seperti pintu yang terayun-ayun diterpa angin. Ia mengirim pesan pada Rengganis: ketemu di tempat yang bisa menenangkan?
Mereka bertemu di belakang Museum Nasional, di antara pohon trembesi tua yang akarnya seperti kisah masa lalu yang enggan benar-benar pergi. Bangku semen basah. Jakarta baru saja selesai hujan.
Jayengrana meletakkan sebuah buku catatan lusuh di pangkuannya. “Aku menulis, seperti katamu,” ujarnya, setengah malu. “Tentang hari-hari yang kubiarkan terlalu panjang, dan tentang tempat-tempat yang membuatku ingin pulang.”
Rengganis tersenyum kecil. “Bagus.”
“Dan ini,” Jayengrana menyobek halaman terakhir, membiarkan suara krek terdengar jelas. “Untukmu.”
Rengganis menerimanya. Di halaman itu ada sketsa sederhana: dua jari kelingking terikat satu garis merah, tipis. Di bawahnya tertulis: Jika kamu percaya, benang ini tidak akan putus. Hanya ditarik lebih panjang. Sampai waktunya tepat untuk disatukan.
Rengganis tidak menangis. Ia memilih tersenyum, sebab beberapa pertemuan lebih pantas dirayakan dengan tenang. “Hati-hati di sana,” katanya, menautkan matanya pada mata Jayengrana. “Jadilah berat bagi hal-hal yang benar, dan ringan bagi hal-hal yang salah.”
Mereka tidak berpelukan. Mereka tidak berjanji. Mereka hanya berdiri, membiarkan kota mengarsipkan sore itu sebagai sesuatu yang kelak akan mereka cari lagi.
.
Tiga Tahun Tanpa Kabar, Tapi Tidak Tanpa Arti
Waktu bergerak seperti kereta yang akhirnya tepat waktu. Rengganis mengajar lebih sering, bukunya terbit dengan judul “Kota yang Menyimpan Air Mata”. Ia menjadi dosen tamu di beberapa kampus di Jakarta dan Bandung, lalu puisinya diundang untuk pameran internasional di Frankfurt. Ia ragu untuk pergi—asing baginya adalah kata yang tajam—tetapi halaman kecil dari buku Jayengrana selalu ia simpan di dompet, warnanya kini memudar. Setiap kali ia menyentuh helai kertas itu, semacam keberanian menetes pelan-pelan.
Ia menyiapkan pameran dengan cara yang tidak tergesa: memilih puisi yang paling jujur, foto yang paling tidak memaksa. Di sela kesibukan, ia menjadi relawan di komunitas baca anak di Tanah Abang, mengajak mereka menulis surat untuk diri sendiri sepuluh tahun ke depan. “Tulis saja yang kamu mau,” katanya pada seorang anak yang giginya ompong. “Surat ini akan menemukanmu nanti, ketika kamu siap membalasnya.”
Di malam-malam cemas, ia mengulang-ulang satu kalimat: pulih adalah cara lain menyebut sabar. Ia belajar menutup laptop sebelum kantuk menjadi marah. Ia belajar mematikan notifikasi agar hati punya waktu mendengar dirinya sendiri. Ia belajar bahwa menjadi kelas menengah ke atas bukan alasan untuk tidak peka—bahkan justru alasan paling kuat untuk menunduk dan mengulurkan tangan.
.
Berlin, Jakarta, dan Kota-kota yang Mengubah Cara Memeluk
Sementara itu, Jayengrana bertahan di Berlin. Ia belajar mengucap selamat pagi pada udara dingin yang menggigit, belajar antre dengan sabar meski jam tangan memalingkan muka, belajar memasak sup kentang yang tidak terlalu asin. Proyeknya sukses; grafik pendapatan bulanan perusahaan melengkung naik seperti senyum yang akhirnya mau tinggal.
Namun setiap usai rapat, setiap selesai presentasi yang dipuji, ada semacam jeda yang tidak diisi tepuk tangan. Ia menulis lagi—berlembar-lembar, lalu melukis. Bukan supaya dilihat orang, tapi supaya ia tahu rupa perasaannya. Di banyak kanvas, garis merah menghubungkan subjek yang saling membelakangi. Galeri kecil di Kreuzberg tertarik memamerkannya. Seseorang menyebut seri lukisan itu: The String Between Us.
Ia menulis sepucuk email yang disimpan di drafts selama berminggu-minggu: Apakah benangmu masih kamu simpan? Email itu tak pernah dikirim. Bukan karena ragu, melainkan karena ia percaya—benang itu bekerja di wilayah yang di luar kata, di luar sinyal, di luar jam kerja.
.
Frankfurt: Lukisan Benang, Nama yang Terpajang
Di galeri Frankfurt yang berlantai semen abu-abu, Rengganis berjalan pelan, memutar tubuh di antara pengunjung yang berbisik dalam bahasa-bahasa yang saling meminta ruang. Puisinya dipasang di dinding tengah: tentang Jakarta yang penuh suara sekaligus sepi, tentang gerimis yang membuat orang-orang canggung, tentang bangku semen di belakang museum dan halaman yang disobek.
Di sudut lain, matanya tertumbuk pada sebuah kanvas: dua figur membelakangi satu sama lain, jari kelingking mereka diikat garis merah. Judul di bawahnya: The String Between Us. Rengganis merasakan dadanya dirangkul dari dalam. Ia mendekat, membaca nama di sudut: Jayengrana Wicaksana.
Dunia tiba-tiba mengecil menjadi jarak antara dirinya dan lukisan. Ia menelan pelan, lalu menoleh. Ada seseorang berdiri tak jauh, jaket wolnya gelap, wajahnya sedikit lebih tirus daripada terakhir ia lihat, matanya masih memelihara ketenangan yang anehnya hangat.
“Hai,” kata Jayengrana.
“Hai,” jawab Rengganis.
Mereka tidak berlari. Mereka tidak bertanya kenapa. Mereka berdiri, membiarkan waktu yang selama ini menjadi jarum, menyatukan benang yang sabar menunggu disimpul.
.
Menamai yang Pernah Kita Biarkan Tanpa Nama
Mereka duduk di bangku kayu dekat jendela galeri. Di luar, salju tipis menaruh dirinya di bahu orang-orang. Frankfurt sore itu seperti kota yang mengurangi volumenya sendiri agar mereka bisa mendengar. Rengganis bercerita tentang kelas menulisnya, tentang anak bernama Sigit yang ingin kelak menjadi fotografer karena bosan difoto tanpa diminta. Jayengrana bercerita tentang lukisan-lukisannya, tentang perempuan lansia di Kreuzberg yang selalu datang pada hari Jumat dan berkata “garis merahmu membuatku ingat suamiku”.
“Apakah kamu pernah berhenti menunggu?” tanya Rengganis, suaranya pelan seperti halaman buku yang dibalik hati-hati.
“Tidak,” kata Jayengrana, jujur. “Tapi aku berusaha tidak menjadikan menunggu sebagai alasan berhenti hidup.”
Malam itu mereka berjalan di tepi sungai Main. Airnya memantulkan lampu kota seperti potongan-potongan kalimat yang sengaja dipatahkan agar pembaca menghentikan langkah. Mereka mengucap sedikit hal, tetapi mengingat semuanya. Di hotel, Rengganis menulis satu puisi pendek—bukan tentang bertemu setelah lama berpisah, tetapi tentang benang yang akhirnya bertemu jarumnya.
.
Jakarta Pulang, Berlin Pulih
Mereka memutuskan menamai apa yang dulu mereka biarkan tanpa nama. Bukan karena kata-kata lebih kuat daripada perbuatan, melainkan karena kata-kata bisa mengatur napas. Mereka sepakat untuk menjaga jarak yang wajar, untuk tidak membiarkan karier membakar semua waktu, untuk memelihara jeda yang menjadi taman kecil di antara dua kehidupan yang sibuk.
Ketika mereka kembali ke Jakarta beberapa bulan kemudian—Jayengrana mengambil cuti panjang, Rengganis pulang dengan koper yang isinya sebagian buku—kota menyambut dengan matahari yang lebih bersahabat. Mereka mencari apartemen dengan balkon kecil yang cukup untuk dua pot kembang telang, satu tiang jemuran, dan dua kursi yang tidak cepat letih. Setiap Sabtu pagi mereka berbelanja di pasar, belajar menawar tanpa merasa bersalah, belajar mengucap terima kasih tanpa tergesa.
Mereka tidak menjadi pasangan yang sempurna. Mereka tetap bertengkar tentang hal remeh: posisi sendok di laci, jumlah bantal di ranjang, urutan menaruh buku. Tetapi mereka belajar satu hal yang lebih penting daripada menang: memeluk kesalahpahaman sebelum tidur, membiarkan ego turun dari kursi tamu, dan memberi ruang bagi humor untuk menyiram bara.
Rengganis tetap mengajar—kini kelasnya lebih penuh karena orang-orang kota semakin sadar bahwa menulis adalah cara terbaik untuk membuat jarak dengan lelah. Jayengrana membuka studio seni kecil di Kuningan, menyelenggarakan lokakarya “Mewarnai Luka”. Di dinding studionya, ia memasang sebuah kalimat: di balik setiap garis, ada tangan yang gemetar. Gemetar itu bukan lemah—itulah tanda hidup.
.
Benang Tak Kasatmata: Tumbuh Jadi Jaring
Dengan bertambahnya tahun, benang yang dulu mereka sebut tak kasatmata itu tumbuh menjadi jaring: jaring dukungan, jaring pertemanan, jaring yang menangkap hari-hari jatuh sebelum pecah. Mereka bergantian menjaga orang tua yang menua, menabung untuk hal yang mereka sebut “masa depan yang masuk akal”—bukan rumah terlalu besar yang kosong, melainkan perpustakaan kecil, warung kopi jalan kampung, beasiswa untuk anak-anak yang ingin menulis tentang kotanya tanpa takut salah.
Di ruang tamu, pada satu dinding putih, mereka membiarkan kanvas besar kosong—sengaja. “Supaya kita ingat,” kata Rengganis, “bahwa tidak semua hal harus segera diisi.” Jayengrana mengangguk, menempelkan sebuah sobekan kertas kecil di sudut kanvas: halaman yang dulu ia berikan di belakang museum, kini menguning oleh waktu. Garis merahnya masih jelas, meski tipis.
Pada malam-malam tertentu, mereka masih takut. Takut kehilangan, takut gagal, takut kota tiba-tiba berubah lebih cepat daripada kemampuan mereka berlari. Pada malam-malam seperti itu, mereka saling mengingatkan nasihat yang mereka bangun bersama, nasihat yang terdengar seperti doa:
“Hidup bukan tentang yang paling cepat sampai; hidup adalah kemampuan menata ulang langkah ketika peta berubah.”
“Kalau lelah, jangan mundur. Duduk dulu. Atur napas. Rencanakan ulang. Lalu berjalan lagi.”
.
Mengikat Tanpa Mencengkeram
Suatu sore, selepas kelas menulis, Rengganis menerima pesan dari salah satu mahasiswanya: “Kak, bagaimana jika benang itu tidak pernah membawa kita ke orang yang kita mau?” Rengganis berpikir lama sebelum membalas: “Benang bukan alat untuk menarik orang; benang adalah pengingat bahwa hatimu tidak berjalan sendirian. Kalau ujung satunya bukan manusia, mungkin ujung sana adalah dirimu yang lebih baik. Ikatlah.”
Dalam perjalanan pulang, di atas kursi MRT yang dingin, ia melirik Jayengrana yang tertidur sebentar—lelah setelah lokakarya seharian. Ada rasa sayang yang tidak lagi tegang seperti dulu; sayang yang tidak mencengkeram, melainkan mengikat longgar agar udara tetap bergerak.
Ia menyandarkan kepala di bahu Jayengrana, dan dunia tiba-tiba mengecil lagi, kali ini menjadi suara roda kereta yang meluncur di rel, menjadi pengumuman stasiun yang sudah ia hafal, menjadi detak yang tidak perlu lagi ia sembunyikan.
.
Apa yang Kita Jahit, Apa yang Kita Wariskan
Beberapa tahun kemudian, studio di Kuningan pindah ke ruang lebih besar. Kelas-kelas menulis Rengganis berkembang menjadi program beasiswa. Mereka mengadakan pameran tahunan: Benang-Benang Kota, menampilkan karya anak-anak dari berbagai sudut Jakarta—dari Menteng sampai Marunda. Di pembuka pameran, Rengganis membacakan kutipan yang kini menjadi semacam kompas:
“Jangan terburu-buru menyebut patah sebagai akhir. Patah adalah ruang untuk menyambung, dan benang-benang terbaik dirajut dari kesabaran.”
Jayengrana berdiri di sampingnya, menggenggam jemari yang dulu hanya ia kenal sebagai sketsa. Di kerumunan, sebuah wajah kecil mengangkat tangan: Sigit, bocah yang dulu menulis surat untuk dirinya sepuluh tahun ke depan, kini remaja dengan kamera menggantung di leher. “Kak,” katanya, “benang itu ternyata kuat, ya.”
Rengganis tersenyum. “Kuat, kalau kita merawatnya.”
Malam turun di atas kota. Lampu-lampu menyalakan bahasa mereka sendiri. Dari balkon apartemen, dua pot kembang telang menunduk pelan; angin memintal aroma tipis yang tak terlihat. Rengganis dan Jayengrana duduk, menatap kanvas kosong yang masih mereka biarkan untuk esok.
Mereka tidak lagi menunggu semesta menulis akhir. Mereka memegang jarum bersama, menenun hari-hari dengan benang yang dulu tak kasatmata—kini ada di tangan, terasa, dan terus disambung, bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk kota yang diam-diam selalu menunggu seseorang berani menjahitnya ulang.
.
.
.
Jember, 12 Juli 2025
.
.
#BenangTakKasatmata #CerpenUrban #SastraKota #Rengganis #Jayengrana #MenakMadura #KompasMingguVibes #PulihPelanPelan #JakartaStory #EmpatiKota
.
Kutipan-kutipan untuk naskah
-
“Pulih adalah cara lain menyebut sabar; ia berjalan pelan, tetapi jaraknya selalu tepat.”
-
“Menunggu bukan alasan berhenti hidup; menunggu adalah seni merapikan napas.”
-
“Di balik setiap garis yang bergetar, ada tangan yang belajar jujur pada luka.”
-
“Kita tumbuh bukan saat tak ada badai, tetapi ketika memilih menambal layar.”