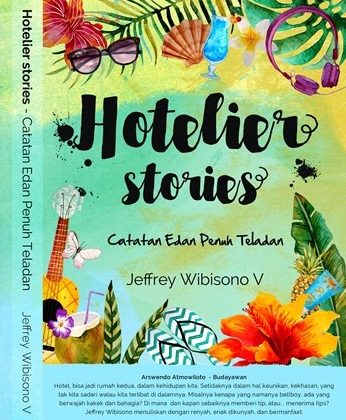Napas Kota Kita
“Kadang yang paling berat bukan badai di luar, melainkan suara di dalam kepala yang menyuruh kita berhenti. Teruskan saja langkahmu—perlahan pun tetap maju.”
.
Kota itu selalu bangun sebelum matahari. Lampu-lampu jalan masih bersinar kekuningan ketika suara pasar menjemput subuh; troli sayur berderak, plastik berdesis, dan dari mulut gang sempit terdengar seruan tawar-menawar senada doa. Di atasnya, rel kereta komuter bergetar seperti syahadat besi yang diulang-ulang. Di bawah flyover yang ditempeli sisa poster kampanye, angin menyapu debu, menyiapkan panggungnya sendiri.
Adipati memandangi jendela kantornya yang buram oleh sisa hujan malam. Gedung itu asing, dinginnya tertib dan bersih, seakan diatur oleh jam yang tidak pernah salah. Di mejanya, berkas-berkas tebal menunggu ketegasan; peta-peta digital berseliweran di layar: garis biru sungai, garis abu-abu jalan, titik-titik merah permukiman yang akan digusur demi dinding banjir baru. Ia menggosok pelipis. Di luar, kota mendorong jamnya tanpa kompromi. Di dalam, satu kalimat yang lama ia hapal kembali memantul: “Jalankan saja prosedur, jangan ikut perasaan.”
Sejak kecil ia percaya, kota adalah rumus. Hanya belakangan ia tahu, rumus pun berdenyut; ada jeda napas di antara angka-angka. Itu ia pelajari dari Siti—perempuan yang datang ke ruang rapat dengan sandal basah dan bau kopi, yang menatapnya bukan sebagai pejabat, melainkan manusia yang kebetulan duduk di seberang meja. Siti memimpin kelompok warga bantaran Kali Gembira, nama yang terdengar seperti lelucon di musim hujan: kali yang lebih sering murka daripada gembira.
Pagi itu, sebelum rapat, Adipati turun sendirian ke tepi kali. Airnya cokelat kelabu, membawa bungkus mie instan dan ranting. Di kejauhan, suara adzan menembus kabut, membelit menara-menara crane yang menggigiti langit. Seorang pengemudi ojek daring menghentikan motornya, menyalakan rokok. Di dinding rumah semi permanen, mural bergambar perahu sampan memuat tulisan tangan: “Tujuan kita kadang tak jelas, tapi dayunglah dulu.”
Jokotole yang melukisnya. Anak pasar itu tangannya cekatan ketika menyablon kaus, ketika menyalakan tungku kopi, ketika menempelkan harapan ke dinding tembok. Ia memanggil Adipati “Mas” tanpa ragu, seakan panggilan itu bisa menurunkan jarak jabatan ke tinggi mata. “Kalau dinding banjir jadi, Mas,” katanya, “tolong kasih warna sedikit. Biar kalau lewat hari-hari berat, orang masih ingat kota ini bisa ramah.”
Rapat siang itu seperti biasa: air conditioner terlalu dingin, kopi terlalu pahit, bahasa terlalu cepat. Siti menghamparkan peta kampungnya sendiri—bukan dari citra satelit, melainkan dari ingatan kaki. Ia menunjuk gang, sumur, pohon jambu tempat anak-anak bermain; garis-garis yang tidak pernah muncul di aplikasi, tetapi hidup di mulut orang-orang. “Kami ingin bertahan,” ucapnya, “bukan untuk keras kepala. Kami hanya ingin ikut menata nasib kami sendiri.”
Adipati menatap garis-garis itu. Ada rasa yang tidak masuk ke excel. Ia mengangguk pelan. “Kalau kita cari cara lain?” suaranya entah milik siapa, terasa agak asing di telinganya sendiri. “Misalnya, bukan menggusur, melainkan menggeser; bukan menghapus, melainkan merapikan.” Kata-kata itu seperti membuka jendela. Tiba-tiba udara masuk.
Sejak saat itu hari-hari terasa lebih padat, tetapi anehnya lebih terang. Ada kerja yang membosankan: mengecek nomor kavling, memverifikasi ukuran, menghubungi pemilik kavling yang alamatnya hilang di tengah riwayat pernikahan dan pindah domisili. Ia menandatangani surat-surat kecil yang tidak menarik, tetapi jadi tangga ke sesuatu yang lebih besar. Ia merasakan betapa kota dibangun bukan hanya dari keputusan legendaris, melainkan dari detail yang telaten: meteran pita yang tidak pernah bohong, foto-foto yang bertanggal jelas, panggilan telepon yang harus diulang tiga kali karena suara pesawat melintas.
Pada satu malam yang sunyi, ketika kantor setengah gelap dan pembersih lantai mendorong ember dengan sabar, Adipati menemukan peta tua di server yang nyaris terlupakan. Peta yang dibuat pada masa nenek buyutnya, saat kanal-kanal masih bernama bunga dan bukannya kode proyek. Garis-garisnya berbeda: sungai pernah lebih lebar, rawa-rawa pernah lebih sabar. Di antara garis itu ia menemukan jejak alur kecil—sebuah selokan purba yang dulu mengalir ke kali, kini tertutup rumah-rumah dan aspal. Mungkin di situlah air mengamuk saban puncak hujan, mencari jalan lama yang dirampas.
Keesokan harinya, ia mengajak Jokotole dan Siti menelusuri jalur itu. Mereka menyusup di antara jemuran dan pagar seng, mengukur langkah, mencatat elevasi seadanya. Di satu sudut, mereka menemukan sumur tua tertutup papan, airnya dingin seperti rahasia. “Kalau jalur ini kita buka lagi,” ujar Adipati, “kita bisa kurangi beban kali. Kita bikin jalur hijau linear—taman sempit yang mengalirkan air sekaligus jadi ruang bermain.”
Siti menatapnya lama. “Berarti rumah orang harus digeser.”
“Ya,” jawab Adipati, “tapi bukan disingkirkan. Kita rapikan plotnya, kita tambah lantai, kita pasangkan rangka tahan banjir. Kita bangunkan hunian berundak di lahan yang legal; kita beli tanah kecil di seberang untuk kompensasi kebun. Kita libatkan kalian dari desain sampai pengawasan. Kita cat tembok dengan mural, seperti yang kau minta, Jokotole.”
Jokotole mengisap napas. “Berani juga, Mas.”
“Kalau tidak dicoba,” kata Adipati, “kita tidak akan pernah tahu.”
Sejak itu, kota seperti menyetrumkan ide-idenya sendiri. Di ruang tamu rumah warga, di lapak kopi, di pos ronda, mereka menggambar denah di atas kertas minyak yang direkatkan ke meja dengan isolasi bening. Rengganis—barista yang berhenti kuliah arsitektur karena biaya—membantu merapikan sketsa menjadi gambar kerja sederhana. Ia menyarankan modul dinding ventilasi, jalur evakuasi yang jelas, dan di sela-sela itu menyisipkan kebun pot di balkon yang bisa memetik sawi setelah hujan. “Rumah bukan hanya tempat pulang,” katanya, “tetapi tempat tumbuh.”
Kota merespons dengan caranya: ada pejabat yang sinis, ada kontraktor yang mencibir. Ada pesan singkat dari nomor tidak dikenal: “Jangan terlalu idealis kalau ingin karier panjang.” Ada juga tangan-tangan yang diam-diam membantu: staf kelurahan yang membuka laci lama, guru SMA yang mengirim daftar alumni pengukir kayu, tukang las yang mau mendermakan shift malam untuk bikin rangka balkon pertama. Di trotoar depan kampung, Jokotole melukis lagi: sampan berubah jadi perahu naga; kepalanya bukan naga, melainkan kepala anak-anak yang tertawa.
Dalam satu rapat evaluasi yang melelahkan, seseorang melempar angka. “Berapa persen efisiensinya? Berapa rupiah per meter persegi? Apa jaminan tidak banjir?” Angka-angka itu berloncatan seperti dadu. Adipati menjawab satu per satu, menunjuk peta lama, simulasi hidrolik sederhana yang ia ramu dari spreadsheet, dan kesaksian warga tentang arah arus. Ia tak tahu sejak kapan suaranya menjadi tenang. Barangkali karena setiap kali ia ragu, ia teringat pada satu adegan sederhana: ibu-ibu menjemur kasur di atap sesudah air surut, mengelus permukaan busa seakan menenangkan anak yang mengigau. Ada kehormatan di situ, kehormatan yang tidak meminta retorika, melainkan ruang kering.
Lahan-lahan itu mulai bergeser. Bukan dengan sirene dan palu godam, melainkan dengan gotong royong: benda berlayar di atas gerobak, bukti pajak dipotret, kontrak ditandatangani di meja makan. Para tukang datang, memaku, mengelas, tersenyum. Rengganis menggambar ulang fasad setelah atap pertama rubuh karena angin—bukan salah perhitungan, melainkan kayu yang terlalu tua. Dalam kepanikan kecil itu, tidak ada saling menyalahkan; ada air mata kecil di sudut mata Siti, ada tangan Jokotole yang menepuk bahu Adipati. “Kita bangun lagi,” katanya. “Kota tidak bisa selesai sekali kuas.”
Di tengah proses itu, skandal kecil beredar: ada vendor bahan bangunan yang mencoba memotong kualitas; besi yang dipesan ternyata lebih tipis dari spesifikasi. Adipati menahan marah seperti menahan batuk. Ia tidak berteriak di hadapan publik; ia mengundang vendor ke halaman masjid kecil di tepi proyek. Dengan meteran dan magnet, ia tunjukkan fakta. “Kita berada di tepi air,” katanya, “kalau satu baut berkompromi, kita mengkhianati semua yang sudah percaya.” Vendor terpaku, lalu mengangguk, lalu mengembalikan. Tidak semua keadilan butuh panggung, pikirnya, kadang cukup terang matahari.
Minggu-minggu memanjang seperti rel. Jam tidur Adipati berantakan; jam hidupnya entah kenapa justru terasa rapi. Ia mulai mengenali kota seperti mengenali nadinya sendiri: suara kereta persis sebelum rem, bau hujan pertama di atas aspal panas, jeda singkat lampu merah di perempatan di mana pedagang tisu berlari seperti pelari jarak pendek. Ia belajar melambat ketika perlu, mempercepat ketika genting, menahan diri ketika hampir meledak. Ia menulis di buku saku: “Kebijakan adalah keberanian yang bersih dari kekagetan.”
Di sela padat itu, ada jam-jam yang tiba-tiba membuahkan kilat. Seolah-olah sesuatu di kepalanya terbuka, memberikan jalan pada gagasan yang selama ini mengetuk. Ia memikirkan cara memanen air hujan di atap-atap baru, memikirkan trotoar yang memeluk akar, memikirkan kios buku bekas di bawah bayang flyover, memikirkan panggung kecil di atas saluran yang telah dibuka kembali tempat remaja-remaja membacakan puisi. Malamnya, ia menulis satu kalimat di ponsel: “Kalau sungai adalah teks, warga adalah pembacanya. Kita hanya menyiapkan tanda baca.”
Pada sebuah malam listrik sempat padam. Kampung terhalang gelap, tetapi langit memantulkan cahaya kota seperti lampu kedap-kedip. Di rumah Siti yang sedang direnovasi, orang-orang berkumpul. Rengganis menuang kopi dari ketel kecil; Jokotole memainkan gitar yang hanya punya lima senar; seorang anak kecil tertidur memeluk guling. Siti bercerita tentang masa kecilnya—bagaimana ayahnya menyeberang di atas perahu kecil, bagaimana ibunya menanak nasi di dapur yang bila air naik harus ditinggikan dengan batu bata. “Kami tidak menolak maju,” katanya pelan, “kami hanya ingin maju tanpa menjadi tamu di kota sendiri.”
Cahaya kembali hidup. Tepuk tangan kecil terdengar, seolah menyalakan satu lampu adalah prestasi bersama. Adipati menatap wajah-wajah itu dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa sendirian di pekerjaannya. Ia teringat kakeknya, seorang juru tulis kelurahan di kota kecil di timur laut pulau ini; kakek yang dulu mengajarinya bahwa tanda tangan bukan sekadar nama, melainkan kesediaan memikul doa-doa kecil orang lain.
Perlahan, rangka-rangka rumah berubah jadi dinding; dinding berubah jadi balkon; balkon menjadi tempat jemuran dan obrolan. Anak-anak berlari di jalur hijau linear, mengejar capung yang turun di atas genangan bening di kolam resapan; suara mereka mengalahkan dengung truk beton. Di sela tanaman, plakat kecil dipasang: bukan nama proyek, tetapi nama-nama orang yang menyumbang sesuatu—waktu, sekop, ide, bacaan, pelukan. “Kota adalah daftar panjang terima kasih,” tulis seorang warga.
“Bagaimana kalau hujan ekstrem datang?” tanya seorang pejabat yang akhirnya datang setelah melihat unggahan foto-foto warga di media sosial. Adipati menyodorkan grafik curah hujan, sumbu-sumbu sederhana yang masuk akal. “Air akan meluap,” jawabnya, “tetapi jalur ini akan memeluk luapannya. Kami tidak menjanjikan kering abadi. Kami menjanjikan bahwa orang punya ruang untuk menunggu surut tanpa kehilangan seluruh hidupnya.”
Pejabat itu mengangguk tak nyaman. “Siapa yang akan memelihara?”
“Nama-nama di plakat itu,” sahut Siti. “Kalau sehari saja taman ini kotor, kami yang malu.”
Pada sebuah senja, saat awan melepaskan warna jingga yang tidak ada di palet, Adipati duduk di tangga beton baru dan memandangi air. Di sebelahnya, Jokotole menggambar garis terakhir mural panjang yang membentang mengikuti jalur. Mural itu memulai cerita dari hulu: bibit ditanam, kota tumbuh, hujan turun, air mencari jalannya, manusia belajar merendah. Di ujungnya, ada perahu yang tidak lagi bingung; bukan perahu besar, hanya cukup untuk menampung dua orang. “Perahu ini,” kata Jokotole, “dikasih nama apa?”
“Endah,” jawab Rengganis yang baru datang, menaruh dua gelas kopi di tangga. “Biar ingat kalau keindahan itu kerja keras.”
Adipati tertawa kecil. “Atau ‘Laras’—supaya ingat bahwa sepi pun punya musiknya.”
Siti menatap mereka satu per satu, lalu menatap mural. “Beri saja nama ‘Napas’,” katanya. “Karena di kota yang terlalu bergegas, yang kita cari kadang hanya satu tarikan napas yang utuh.”
Malam itu mereka meresmikan jalur hijau tanpa pita, tanpa sambutan panjang. Anak-anak melintasi jalur sambil memegang lampion kertas; para ibu menabur biji sawi di planter; para bapak menancapkan paku signage kecil: “Dilarang membuang sampah. Diperbolehkan berharap.”
Di saku celananya, ponsel Adipati bergetar: email undangan naik jabatan. Kota yang lain memanggilnya ke lantai yang lebih tinggi, ke jabatan yang lebih mengilap. Dulu, ia akan menerimanya tanpa menoleh. Kini ia menatap air yang jernih di kolam resapan, menatap anak kecil yang melintasi jembatan kayu sambil melambaikan tangan, menatap wajah Siti yang lelah dan teguh. Ia menunda menjawab. Ada hal-hal yang lebih tinggi dari lantai gedung.
Malam-malam berikutnya, detail kembali menuntut: izin lingkungan yang belum terunggah, nomor IMB yang salah ketik, data densitas yang harus disesuaikan karena tiga keluarga sepakat tinggal satu atap untuk sementara. Ia kembali tenggelam dalam angka—tetapi angka yang kini punya wajah. Di meja kerja sempit, ia menuliskan daftar hal remeh yang tidak boleh remeh: “Baut M8 lengkap ring, selang pompa cadangan, daftar nomor darurat cetak laminasi, jadwal piket sampah, cat anti jamur untuk sisi timur.”
Ia belajar bahwa keberanian bukan hanya melawan, tetapi merawat. Bukan hanya memulai, tetapi menyelesaikan. Ia kembali ke kantor yang dingin, menata file digital dengan nama yang tidak akan membuat orang sesudahnya bingung: 2025-Plan-JalurHilir-V3-Final-beneran-Fix. Ia tertawa pada dirinya sendiri dan menghapus “Final-beneran-Fix”, lalu menyisakan tanggal. Kota, pikirnya, adalah pekerjaan yang selalu bersambung.
“Kalau kau pergi, siapa yang jaga?” tanya Jokotole suatu malam, ketika mereka duduk di warung mi ayam di pojok. Uap panas mengaburkan kacamata Adipati.
“Bukan siapa,” jawabnya. “Apa. Aturan yang kita buat bersama. Kebiasaan yang kita ulang. Cara kita menyapa satu sama lain.” Ia diam sebentar. “Tapi aku belum pergi.”
Jauh di sebuah gedung megah, rapat lain memutuskan proyek-proyek lain. Kota tidak pernah berhenti bertambah. Namun di kampung kecil itu, sesuatu menua dengan anggun: batu pijakan di tepi kali semakin halus, warna mural memudar karena matahari dan tawa, jalur hijau tumbuh akar yang memeluk tanah. Sesekali air kembali tinggi. Ada yang basah, ada yang gugup, ada yang kesal. Tetapi tidak ada yang panik. Mereka tahu harus mengangkat apa lebih dulu, menyelamatkan apa lebih dulu, menunggu di mana lebih aman. Tidak ada yang sempurna. Tetapi berharap terasa masuk akal.
Suatu malam, hujan turun lebih lama. Kilat menyalakan langit seperti kamera tua. Air naik perlahan, menyentuh bibir jalur, merambati batu. Adipati berlari kecil dari ujung jalan, Siti sudah berdiri di atas jembatan kecil, payung di tangan. “Masih sesuai hitungan?” tanya Siti.
“Lebih tinggi sedikit.”
“Cukup?”
“Cukup.”
Mereka berdiri tanpa banyak kata. Pada menit ketika air menyentuh batas yang mereka khawatirkan, ia berhenti, seperti orang yang teringat janji. Lalu, pelan, surut.
Siti menutup payungnya, menengadah. “Kau pernah rindu pada dirimu yang dulu?”
“Kadang,” jawab Adipati jujur. “Pada kesederhanaan pilihan. Tetapi rindu itu seperti hujan: datang, menyejukkan, lalu surut. Dan setelahnya, aku bisa menata ulang apa yang longgar.”
“Kalau begitu jangan pergi dulu,” kata Siti. “Masih ada yang harus kita rapikan. Masih ada jendela yang minta dibersihkan, masih ada nama-nama yang belum kita tulis di plakat.”
Adipati tersenyum. “Aku tidak akan ke mana-mana, setidaknya sampai napas ini stabil.” Ia meremas gagang payung, merasakan dingin logam menyusup ke tulang. Di kejauhan, suara kereta seperti doa yang dikabulkan terlambat—tetapi tetap dikabulkan.
Beberapa bulan setelah jalur itu berfungsi, seorang perempuan muda datang ke kampung. Tas punggungnya besar, matanya berbinar. Ia memperkenalkan diri sebagai peneliti kota dari universitas yang jauh. Namanya Rengganing—nama yang seperti saudara jauh Rengganis. Ia ingin belajar tentang bagaimana kota menata dirinya sendiri. Ia berjalan bersama Siti dan Adipati, mencatat, memotret, bertanya hal-hal kecil: “Bagaimana kalian menentukan jarak antar pot? Siapa yang memberi ide menaruh perpustakaan mini di sudut ini? Kenapa mural tidak memakai huruf besar semua?” Pertanyaan-pertanyaan itu seperti cermin kecil—membuat mereka melihat bahwa hal sepele pun pernah diputuskan dengan cinta.
Malamnya, di pinggir jalur, Rengganing membaca keras-keras satu paragraf dari catatannya: “Barangkali kita terlalu lama memikirkan kota sebagai mesin besar yang harus dilumasi dari atas. Hari ini aku melihat kota sebagai kumpulan genggam tangan yang tidak pernah bersamaan, tetapi, entah bagaimana, saling menahan.” Orang-orang tersenyum. Kata-kata itu terdengar seperti puisi yang tidak memerlukan panggung. Mereka melanjutkan mengikat tali jemuran, menutup kios buku, mematikan lampu-lampu kecil.
Ada saat ketika Adipati kembali sendirian ke tepi air. Bukan untuk memeriksa, bukan untuk menilai, bukan untuk mencari kesalahan. Hanya untuk duduk. Di seberangnya, bayang gedung-gedung memantul seperti kartu pos yang setengah terbakar. Ia mengeluarkan kartu undangan promosi jabatan yang masih ia simpan di saku. Kertasnya tebal. Ia membolak-balik, menatap huruf-huruf timbulnya. Lalu ia memasukkan lagi. Ia tahu jawabannya, meski belum menulis balasannya. Kota ini telah menempel di nadi, dan ia belum siap melepaskannya.
“Kadang,” gumamnya, “yang kita cari bukan jalan baru, melainkan cara baru melangkah.” Ia membayangkan hari ketika ia benar-benar pergi—bukan karena menyerah, melainkan karena selesai. Akan ada orang lain duduk di tangga ini, mungkin anak kecil yang hari ini belajar mengeja, mungkin Jokotole yang akhirnya membuka studio mural, mungkin Siti yang rambutnya memutih. Akan ada orang-orang baru datang, membawa names yang belum pernah ia dengar. Dan itu baik. Kota seharusnya selalu kedatangan.
Di detik itu, sebuah lambaian pelan memotong lamunannya. Seorang perempuan berdiri di ujung jembatan—Wara, perempuan yang dulu pernah duduk di sampingnya di bus antarkota, yang hilang dari hidupnya seperti halte yang tidak lagi disinggahi. Mereka berjalan saling mendekat, berhenti pada jarak suara. “Aku dengar kalian menata ulang alur air,” kata Wara. “Aku datang untuk melihat apakah alur hati juga bisa ditata.”
Adipati tertawa kecil, lebih gugup daripada yang ia ingin akui. Mereka menyusuri jalur hijau; Wara menyentuh dinding mural, membaca pelan nama-nama di plakat. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang kota lain yang juga mengajarinya menunggu. Di tangga beton, mereka duduk. Air memantulkan bulan yang separuh. Dalam diam yang tidak canggung, kota terasa lega—seperti orang yang selesai membereskan lemari, menemukan sapu tangan lama yang masih bisa menghapus sisa air mata.
“Kalau kau tanya apa yang paling sulit,” ujar Adipati, “jawabannya bukan mencari ide. Yang paling sulit adalah bertahan di tengah detail yang melelahkan, dan tetap melihat keseluruhan.”
Wara menoleh. “Kalau kau tanya aku apa yang paling penting,” katanya, “jawabannya adalah berani bertemu hal baru—meski ternyata hal baru itu adalah dirimu sendiri.”
Malam merapat. Lampu-lampu kecil menyala seperti kunang-kunang yang tersesat. Dari balik gang, terdengar doa yang dirapalkan seperti jadwal kereta, teratur dan tak tergesa. Angin membawa bau tanah basah, kopi, cat yang belum kering. Adipati menghela napas, napas yang utuh, lalu berdiri.
Keesokan hari, ia menulis pesan kepada Siti: “Mari kita susun pertemuan lintas kampung. Kita ajarkan bagaimana menata alur lama di tempat lain.” Siti membalas dengan emoji ikan dan peta kecil, humor kecil yang mencairkan jam. Di grup pesan, Jokotole mengirim foto anak-anak yang menanam bibit baru. Rengganis menautkan tautan donasi buku-buku bekas. Rengganing mengirim draf tulisannya yang ingin ia jadikan buku saku. Semua bergerak seperti arus yang saling menyapa.
Dan kota? Kota tetaplah kota—penuh kebetulan yang direncanakan, penuh kemungkinan yang menuntut keberanian. Kadang meletupkan keindahan seenaknya; kadang menguji dengan sabar. Tetapi kota itu kini punya jalur yang lebih jujur untuk airnya, dan barangkali, jalur yang lebih berani untuk hati-hati di dalamnya.
“Kalau kita bisa menata alur,” tulis Adipati di catatan hariannya, “mungkin kita juga bisa menata cara berharap.”
Ia menutup buku catatan, menatap ke luar jendela. Pagi baru menggelinding masuk ke gang-gang. Di tepi jalur, perahu kecil dengan nama sederhana menunggu: Napas. Ada ruang untuk dua orang, mungkin tiga jika rela berimpit. Adipati melompat ke dalamnya, mengayuh pelan, dan kota diam-diam ikut melaraskan dirinya.
.
.
.
Jember, 21 September 2025
.
.
#CerpenSastra #UrbanIndonesia #KompasMingguStyle #MenakMadura #KotaDanKita #JalurHijau #MuralKota #HarapanWarga #StorytellingFilmis #LiterasiKota