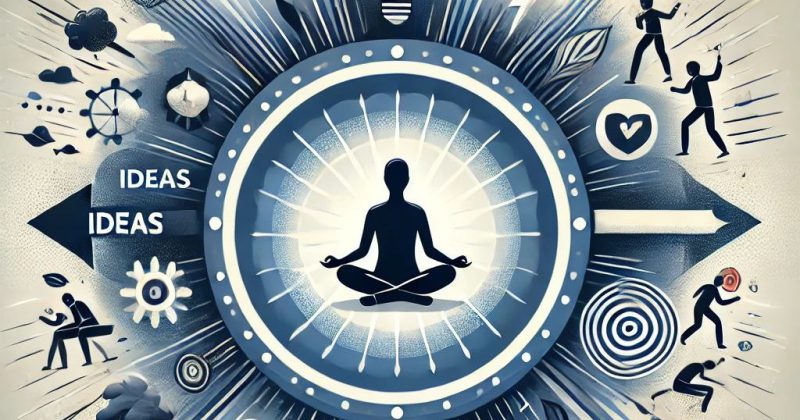Hening di Tengah Hiruk
“Yang paling sunyi bukanlah sepi, melainkan kita yang memilih diam saat hati ingin bersuara.”
“Kehampaan bukanlah kebetulan. Ia adalah tempat paling sunyi untuk merasakan keberadaan diri.”
.
Sebuah Kehilangan yang Tak Pernah Selesai
Langit Jakarta sore itu kelabu. Bukan sekadar polusi yang mengabukan jendela, melainkan dada yang tak kunjung selesai mengurai sesal.
Kumitir duduk di kursi rotan berdecit di lantai dua sebuah rumah kos tua di Menteng. Tangan kanannya menggenggam gelas kopi hitam tanpa gula—pekat, jujur, dan tak berkompromi seperti keputusan-keputusan yang telanjur diambil. Dari kisi jendela, ia mengawasi ruas jalan yang selamanya sibuk: klakson yang serak, sirene yang terburu-buru, suara tukang sate yang menggoyang-goyang kipas arang, dan sekelebat pengendara ojek daring yang menjemput waktu, bukan hanya penumpang.
Ia pernah menjadi tempat pulang bagi seseorang. Kini ia sekadar alamat yang mudah ditemukan aplikasi peta, namun mustahil dituju oleh kenangan yang enggan kembali.
.
Kumitir dan Dunia yang Tak Pernah Menunggunya
Di kalender usianya yang ke-35, hidup Kumitir tak bisa dikategorikan gagal—sebagaimana hidup orang baik yang tetap menyisakan cicilan dan tabungan receh. Ia penulis lepas untuk agensi konten; pekerjaannya mengolah kata agar merek-merek menubruk layar dan menempel ke kepala orang. Sering, ia menjadi editor antologi puisi yang indah tapi tak laku; mencoret koma, memindah titik, menahan napas menjaga ritme; seperti bidan yang membantu kelahiran bayi-bayi yang mungkin tak akan didatangi siapa pun di ruang bercahaya toko buku.
Ia penggemar Houellebecq, pembaca sosiologi kota, penikmat iklan lawas, dan pengkoleksi kalimat orang di halte busway. Absurd bagi sebagian, terlalu serius bagi sebagian lain. Orang menyebutnya idealis—padahal ia hanya payah berkompromi. Ia menyukai jarak dari perbincangan yang mau menang sendiri. “Orang seperti aku tak dilahirkan untuk lomba,” gumamnya suatu Magrib, di sela derit kipas plafon dan salam penutup imam dari surau ujung gang.
Hidup mengalir, bukan menunggu. Namun suatu hari, sesuatu yang tak ia nanti mengetuk.
.
Rara yang Datang Bersama Hujan
Rara Wulandari memasuki hidup Kumitir seperti hujan yang mematikan debu. Mahasiswi psikologi semester akhir, magang di NGO yang kebetulan bermitra dengan agensi tempat Kumitir menulis. Hari pertama, Rara memakai kemeja putih kebesaran dan celana hitam gombrong; sederhana, namun tatapannya bening, seolah dapat menampung alasan untuk bertahan.
“Mas Kumitir? Mbak Rani nitip bahan wawancara.”
Ia menyodorkan flashdisk berperekat washi tape bergambar awan. Senyumnya tipis, tapi telak.
Itu bukan cinta pandang pertama—lebih mirip waktu yang menyempit, melambat, dan diam-diam menggeser peletakan kursi di ruang tamu batin. Sejak hari itu, ponsel Kumitir tak lagi hanya berdering notifikasi pekerjaan; ada pesan Rara menanyakan buku, menautkan podcast, mengomentari puisi pendek yang ia unggah di jam-jam tanpa tidur.
Mereka bertemu di warung soto belakang kantor, menertawakan iklan kopi saset yang hiperbola, berbantahan manis tentang eksistensialisme, hingga menyusun daftar film yang tak selesai-selesai ditonton bersama—bukan karena bosan, tapi karena percakapan selalu lebih seru daripada kredit akhir.
Namun cinta yang lahir dari dua kegelisahan, sering rapuh oleh realitas yang menuntut nama terakhir dan alamat di kartu undangan.
.
Nama-Nama dari Menak yang Mengintai
Jakarta punya caranya memasukkan masa lalu ke lengan kita. Di kos itu, pemiliknya seorang pria tua berbahu tegap bernama wiraraja—nama yang ia bawa dari kampung di Pamekasan, sebuah nama yang terdengar seperti bab yang hilang dari hikayat. Wiraraja suka menyetel radio AM dini hari, menyalakan aroma minyak kayu putih di lorong, dan memelihara ayam kate yang tak pernah benar-benar tidur.
“Nama-nama itu ada tugasnya, Tir,” ucapnya suatu subuh saat mereka berpapasan di dapur, uap ketel bersiul. “Bukan kebetulan bapak dinamai begitu. Nama mengingatkan, bukan menyelamatkan.”
Di kantor, rekan diskusi Kumitir seorang desainer UI/UX bernama jokotole—keturunan penjual sate dari Bangkalan yang kini mengonsep perjalanan jempol orang di dalam aplikasi. Ia gesit, cerdas, dan ceria; setia menertawakan segala hal termasuk kekacauan deadline. “Kalau hidup adalah wireframe,” katanya sambil mendorong kacamata ke atas, “kita mungkin sudah kebanyakan CTA: ‘Sabar’, ‘Ikhlas’, ‘Move On’—tapi semua mengarah ke halaman error 404.”
Nama-nama itu—wiraraja, jokotole—seperti duduk di pinggir cerita Kumitir, mengingatkan ada warisan yang berdenyut sunyi. Seperti lagu lama tanpa penyanyi, tapi masih dihafal orang yang lahir belakangan.
Rara sendiri diam-diam menyebut dirinya kelaswara di dunia maya; bukan akun anonim, melainkan alter yang memuat catatan reflektif tentang kesehatan mental, hubungan, dan keberanian memulihkan diri. “Aku suka bunyinya,” kata Rara pada suatu malam di halte Dukuh Atas, “Kelaswara. Bukan untuk keren-kerenan. Buat mengingatkan bahwa suaraku boleh berbeda, tapi tetap milikku.”
.
Cinta dalam Ruang Tunggu
Mereka bukan remaja; mereka paham semesta dewasa dipenuhi formulir, tenggat, dan ekspektasi keluarga. Rara anak sulung dari tiga bersaudara, tinggal di Tebet dengan ibu yang mengelola katering rumahan dan adik yang gemar ekskul K-pop dance. Ayah bekerja sebagai manajer gudang di Cakung; jam pulangnya sering diambil lembur dan jalanan. Di rumah Rara, cinta tak membenarkan ketidakpastian terlalu lama.
“Kalau kamu sayang, kenapa belum pernah membicarakan arah?” Rara bertanya lirih di malam yang diikat gerimis. “Bukan cincin besok atau lusa. Peta. Atau sekadar kompas.”
Kumitir diam. Bukan karena tak ingin menjawab, melainkan takut jawaban akan merobohkan satu-satunya tenda yang menjaga mereka dari hujan: percakapan. Ia menunda, menyusun kalimat di kepala, berharap ada hari yang lebih tenang untuk kejujuran.
Namun Jakarta tak memberi jeda.
Seminggu kemudian, Rara pamit pulang ke Jogja untuk merapikan skripsi. Ia berjanji kembali setelah wisuda. Janji itu menggantung, menua, lalu pelan-pelan aus di ujung sinyal yang sering putus sambung.
.
Surat yang Tak Pernah Dikirim
Setiap malam, Kumitir menulis surat—bukan di kertas, melainkan di folder laptop bernama “Surat yang Terlambat.” Ia menabung dengan cara paling kuno: kalimat.
“Rara, kamu bilang aku hujan yang tak pandai membaca kapan reda. Tapi hujan tak pernah memilih genting mana yang akan ia bunyikan.”
Dalam surat lain:
“Rara, aku tidak takut pada sepi. Aku takut pada suara-suara di kepalaku yang pandai menyamar menjadi logika.”
Ia tak mengirim satu pun. Bukan karena malu, melainkan karena merasa surat-surat itu bukan lagi untuk Rara. Surat-surat itu adalah cermin untuk dirinya—cermin yang kadang retak, memantulkan orang yang tak ingin ia tatap terlalu lama.
Di siang yang lain, jokotole menepuk bahunya di pantry kantor. “Kita ini, Tir, suka memanggil takdir seperti taksi. Maunya datang cepat, harganya pas, tujuan jelas. Padahal, ya mungkin kita perlu berjalan kaki.”
Kumitir tertawa kecil. “Kalau berjalan, kita basah.”
“Basah itu bukti kau melewati hujan, bukan diam di bawah atap orang.”
.
Senin yang Membaca Keputusan
Biasanya, Jakarta mengumumkan perubahan di hari Senin. Pagi itu, di timeline, muncul foto Rara memakai kebaya putih, berdiri di bawah pohon sawo kecik halaman kecil di Jogja. Di sampingnya, seorang pria bermata sabar, tersenyum dengan sikap yang mengesankan rangkulan dunia. Keterangan foto sederhana: “Bismillah.” Namanya patrawira.
Dada Kumitir terasa menjadi kotak surat yang menampung terlalu banyak amplop. Tak ada air mata. Hanya suara mirip bunyi pintu kayu yang dilepas engselnya—pelan, tapi telak.
Malam itu, ia menghapus folder “Surat yang Terlambat.” Tidak dibaca ulang. Tidak dipindahkan. Dihapus.
Namun ada yang tak terhapus.
Hening.
.
Kota sebagai Kamar Raksasa
Kumitir pindah ke Bintaro, menyewa unit studio dekat stasiun agar MRT dan KRL menyambung perjalanannya ke mana saja. Ia mengajar kelas menulis di komunitas sabtu-pagi, memandu anak-anak SMA menuliskan jurnal diri, menemani ibu-ibu pekerja kantoran mengurai kalimat untuk blog kecil bisnis kue kering. Ia menabung dalam metode yang lebih modern: e-wallet, investasi reksa dana, catatan keuangan pada aplikasi yang rajin mengirim notifikasi “hebat, kamu konsisten!”.
Saban sore, ia joging di jalur hijau. Menyapa pedagang siomai, membeli tempe mendoan di gerobak, berhenti di jembatan kecil yang memandang kali. Ia menjaga makan, mengurangi kopi, memperbaiki tidur.
Namun ada ruang yang tetap dingin, walau matahari berpihak: dadanya.
Di jam-jam lengang, ia membuka peta, menandai tempat-tempat yang pernah dilewati bersama Rara: halte Dukuh Atas, bangku kayu di Taman Ayodya, warung soto belakang kantor, lobi gedung SCBD yang selalu dingin. Ia menamai titik-titik itu sebagai “museum berbayang”—tempat yang tidak akan ia datangi dulu, agar tubuhnya berhenti terkejut tiap kali ingatan memotret ulang.
.
Wiraraja dan Seni Melepaskan
Suatu dini hari, saat ia kebetulan menginap semalam di kos lama—menemani jokotole memperbaiki aplikasi di kantor yang tiba-tiba ngadat—wiraraja memintanya duduk di teras. Hujan tipis menggoyang daun belimbing. Ayam kate menyingkapkan sayap.
“Kau tahu kenapa kunci itu selalu berujung tajam?” tanya wiraraja sambil menyodorkan teh.
“Supaya bisa membuka?”
“Supaya mengingatkan kita: membuka sering kali melukai. Tapi tanpa itu, kita tak keluar dari ruangan.”
Wiraraja bercerita tentang istrinya yang wafat dua puluh tahun lalu. Tentang pagi-pagi ketika ia masih memanggil nama yang sudah tak mengisi kursi makan. Tentang langkah yang akhirnya bisa diteruskan bukan karena lupa, melainkan karena belajar menjinjing pelan.
“Jangan bergegas sembuh. Sebab tergesa hanya menukar luka.”
Kumitir menyimak, merasakan teh menuruni kerongkongan seperti doa.
“Pak,” katanya kemudian, “Kalau luka jadi alamat, apakah kita harus pindah?”
“Tidak. Kita cukup menambah pintu.”
.
Peta Baru: Dari Menghindar ke Mengelola
Kumitir mulai merapikan hidup seperti orang yang akhirnya memutuskan memasang rak buku sendiri. Ia menyusun ulang jam kerja—membatasi lembur, menolak proyek yang menyedot batin tanpa memberi ruang bernafas. Ia ikut program peer counseling di komunitas: belajar mendengar tanpa mengadili, belajar bertanya tanpa menusuk. Di kelas menulisnya, ia menawarkan modul “Surat untuk Diri”—sejenis terapi tinta yang mengajak orang mengirimkan keberanian kepada masa kini.
Di satu sesi, hadir anak muda bernama prabaswara—mahasiswa teknik yang baru kehilangan ayah. Juga seorang ibu bernama sekar wungu yang baru bercerai, datang dengan mata yang tak lagi percaya pada cermin. Mereka menuliskan hal-hal paling jujur yang sekali waktu diinjak realitas: “Aku takut.” “Aku marah.” “Aku ingin rehat.”
Kumitir menyadari: barangkali tugasnya bukan menjadi besar, melainkan menjadi berguna. Bukan menonton hujan dari balik jendela, melainkan meminjamkan payung pada orang yang melintasi gang yang sama.
.
Tentang Kabar yang Datang Pelan
Rara berkabar beberapa bulan kemudian. Bukan foto pesta, bukan pamflet penggalangan dana—melainkan pesan pendek: “Terima kasih.” Hanya itu.
Kumitir membaca dengan tenang. Jemarinya menari sebentar di atas keyboard, lalu berhenti. Ia menutup layar. Ia memahami: ada kalimat yang paling baik dijawab oleh diam yang mendoakan.
Di malam itu, ia menulis di buku kecil yang selalu ia bawa:
“Yang selesai bukan kenangan—melainkan cara kita menatapnya.”
Ia menutup buku, mematikan lampu, dan membiarkan hujan menyanyikan bait-bait yang mampu ia terima, bukan ia kendalikan.
.
Pameran Kecil, Kota Besar
Enam bulan kemudian, kelas menulisnya mengadakan pameran kecil di kedai kopi pinggir jalan utama Bintaro. Di dinding, tergantung belasan surat yang dilaminasi: ada surat untuk diri berumur tujuh tahun, surat untuk ibu yang tak sempat pamit, surat untuk tubuh yang sabar memikul jam kerja, surat untuk Jakarta yang tegas namun murah hati dalam menjadikan orang dewasa.
Jokotole datang membawa poster yang ia desain serba putih, huruf sans-serif rapi, judulnya sederhana: Hening di Tengah Hiruk. Wiraraja menyelipkan amplop berisi uang saweran untuk snack tamu, lalu berkeliling membaca, alisnya naik turun seperti orang memantau pagar.
“Ini kotamu,” ucap jokotole, menepuk bahu Kumitir.
“Bukan. Ini kota kita. Yang meminjamkan trotoar dan lampu merah agar kita belajar berhenti.”
Di pojok ruangan, seorang remaja memegang suratnya erat-erat, menangis tanpa malu. Ibunya memeluk dari samping. Barista menurunkan volume musik, membiarkan keheningan yang bekerja seperti benang.
.
Rencana yang Tidak Dibuat
Dalam perjalanan pulang malam itu, Kumitir menumpang KRL, berdiri di dekat pintu dengan ransel menempel punggung. Ia tak lagi memikirkan “seandainya” seperti dulu; ia sibuk mengingat nama-nama orang yang datang dan tersenyum. Di stasiun Palmerah, ia melihat seorang musisi jalanan menyanyikan lagu lawas tentang pulang. Ia membuka dompet, menyelipkan lembaran kecil ke kotak gitar.
“Bang,” katanya, “Lanjutkan.”
Ia pulang bukan untuk menutup cerita, melainkan untuk berjaga-jaga kalau besok ada yang mengetuk pintu—entah tetangga butuh tang, atau murid butuh kalimat pertama, atau dirinya sendiri butuh diajak duduk tanpa kata-kata.
.
Kota yang Belajar Berdoa
Jakarta—dengan lampu-lampu yang tak pernah habis dan ambisi yang sering menubruk tubuh—diam-diam pandai berdoa. Doa Jakarta dijalankan di garis zebra, di antrean loket, di atap rumah yang bocor, di mulut anak sekolah yang hafal jalur bus lebih fasih daripada isi buku teks. Doa Jakarta bukan soal meminta; lebih soal memelihara jarak aman antara harapan dan kecewa.
Di suatu subuh, Kumitir berdiri di balkon, menatap pendar jingga yang pelan memisahkan malam. Ia menulis satu kalimat di ponsel—kalimat yang kelak ditempel di papan pengumuman kelas menulisnya:
“Bahagia bukan tentang di mana kamu berada, tapi tentang pengetahuan bahwa kamu ada—diakui oleh dirimu sendiri.”
Ia tersenyum. Menghaluskan helai rambut yang kena angin. Menggantungkan baju kerja. Hari akan panjang, tapi hatinya sudah cukup tidur.
.
Menamai Pintu
Surat undangan dari masa lalu tak lagi membuatnya menyalakan api. Ia menaruhnya seperti orang menaruh peta kota lama—berguna suatu hari, mungkin untuk rute sejarah. Ia menamai pintu-pintu barunya: Membiarkan, Mengikhlaskan, Mengelola. Ada satu pintu yang ia cat biru muda, bertuliskan Mengundang: mengundang remaja yang bingung, ibu yang lelah, ayah yang diam, dan dirinya sendiri yang kadang memerlukan tawa tanpa alasan.
Di dinding, poster pameran itu tergantung: Hening di Tengah Hiruk. Huruf-hurufnya tak lagi seperti peringatan, melainkan ajakan untuk duduk lebih lama.
Dan pada malam yang tenang, ketika kota menyerahkan napasnya pada pohon-pohon, Kumitir menulis kalimat yang tidak lagi ditujukan kepada siapa pun, kecuali kepada hidup itu sendiri:
“Terima kasih karena pernah menyakitiku dengan cara yang mengajarkan.”
.
Catatan Reflektif – Solusi yang Bisa Dikerjakan
-
Jurnal harian 10 menit: tulis tiga hal—apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan, apa langkah kecil besok.
-
Museum berbayang: tandai tempat yang memicu luka; beri jeda 40–60 hari sebelum kembali ke sana, lalu datangi dengan teman.
-
Peer listening: temukan komunitas mendengar; jadwalkan sesi dua minggu sekali.
-
Batas kerja: tetapkan jam offline harian; hormati tubuh yang ingin tidur.
-
Surat untuk diri: tulis surat tanpa nama penerima; baca ulang sebulan kemudian.
-
Bersedih dengan tata tertib: izinkan menangis, tapi beri durasi; setelahnya, lakukan satu perbuatan baik kecil—menyiram tanaman, mengembalikan buku, menata meja.
-
Ritual pulih: pilih satu kebiasaan fisik (jalan 20 menit, merapikan ranjang) dan satu kebiasaan batin (doa singkat, napas 4–4–6) setiap hari.
.
.
.
Jember 9 Juli 2025
.
.
#Cerpen #SastraIndonesia #Jakarta #Kehilangan #Pemulihan #MenakMadura #KelasMenengah #SelfHealing #KompasMingguVibes #HeningDiTengahHiruk
.
Kutipan yang Menyatu dengan Cerita
-
“Yang paling berisik dari patah hati adalah pertanyaan yang tak butuh jawaban.”
-
“Kita tidak menyembuhkan luka; kita mengelolanya agar tak menguasai hari.”
-
“Keikhlasan bukan menyerah—ia cara kita mengakui kenyataan tanpa memusuhi harapan.”
-
“Hening adalah ruangan yang melatih kita mendengarkan diri.”