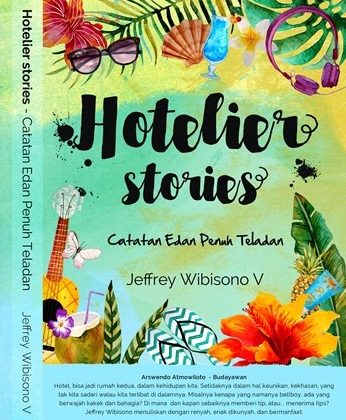Jatuh Tempo: Ketika Angka Menagih Jiwa
“Utang itu bisa dihitung dengan angka. Tapi kepercayaan—ia dihitung dengan luka.”
.
Namanya Panji. Di kartu nama, ia hanya menulis dua baris: nama, lalu jabatan yang terdengar sederhana tapi berat—founder sebuah perusahaan rintisan pendidikan. Ia bukan anak konglomerat. Ia anak kota yang belajar jadi “orang jadi”: kuliah malam, magang siang, merintis usaha dari meja lipat, lalu naik kelas perlahan—seperti lift tua yang sering berhenti di lantai yang tidak direncanakan.
Di Jakarta, naik kelas itu selalu menuntut bukti. Bukan hanya bukti kerja, tapi bukti gaya: apartemen yang punya jendela besar, kopi yang diseduh dengan alat mahal, mobil yang tak berisik saat pintu ditutup, dan, yang paling menyiksa: bukti bahwa hidupmu “aman”.
Padahal, aman adalah kata yang paling sering dipalsukan oleh orang kota.
Pagi itu, Panji menatap sebuah poster digital yang melintas di ponselnya—dikirim ke grup keluarga: Jangan pernah sepelekan utang. Ia menggeser layar, setengah ingin menertawakan, setengah ingin menangis. Kalimat-kalimatnya mengingatkan pada pengajian masa kecil, pada nasihat ibu saat ia masih memakai sepatu sekolah yang ujungnya selalu basah oleh hujan.
Ia menutup ponsel. Lalu membuka laptop. Lalu menutup laptop lagi.
Di meja, ada angka-angka yang tak mau tidur: jatuh tempo. Ada nama-nama yang tak mau dilupakan: investor, vendor, teman lama yang kini jadi kreditor.
Dan ada satu nama yang paling membuat dadanya terasa sempit: Sekartaji.
Sekartaji adalah orang yang paling tahu cara Panji berpura-pura. Ia membaca Panji seperti membaca buku yang sudah dihafal. Ia tak perlu bertanya panjang. Cukup melihat cara Panji meletakkan kunci mobil—terlalu pelan—untuk tahu ada sesuatu yang sedang retak di dalam rumah.
Sekartaji bekerja sebagai konsultan brand untuk perusahaan-perusahaan mapan. Jadwalnya rapi, bicaranya jernih, keputusannya nyaris selalu tepat. Ia percaya pada estetika, pada ketepatan, pada keputusan yang diambil tanpa drama. Tetapi menikah dengan Panji membuatnya mengerti bahwa hidup tidak selalu bersedia rapi. Hidup kadang sengaja mengacak isi laci hanya untuk melihat siapa yang akan tetap menyusun ulang.
Malam sebelumnya, Sekartaji menunggu di ruang makan. Lampu kuning hangat memantul di permukaan meja marmer yang, ironisnya, dibeli dengan skema cicilan “tanpa bunga” selama dua tahun.
Panji datang dengan senyum yang terlalu resmi, seperti front office hotel menyambut tamu VIP sambil menyembunyikan fakta bahwa kamar belum siap.
“Kamu capek?” tanya Sekartaji.
“Lumayan.”
“Kenapa belakangan kamu sering bilang ‘lumayan’?”
Panji diam. Ia menaruh tas. Ia duduk. Ia memutar cincin kawin pelan-pelan.
Sekartaji menatapnya seperti menatap pintu yang tak kunjung dibuka.
“Panji,” suara Sekartaji turun, “kita ini pasangan. Jangan bikin aku jadi penonton.”
Kata penonton itu menampar. Panji pernah jadi penonton dalam hidupnya sendiri: menonton ayahnya menahan malu karena utang koperasi, menonton ibunya menjual perhiasan satu-satu, menonton rumah kecil mereka dipenuhi suara orang menagih yang sopan tapi tajam.
Panji bersumpah dulu: ia tidak akan mengulang itu.
Dan sumpah itu—malam ini—seperti lelucon yang disampaikan pelan-pelan oleh nasib.
“Aku… ada masalah cashflow,” kata Panji akhirnya.
Sekartaji tidak terkejut. Ia hanya menghela napas, seperti orang yang sudah lama mencium bau hangus tapi tetap berharap itu hanya aromaterapi.
“Seberapa besar?”
Panji menyebut angka.
Sekartaji tidak langsung bicara. Ia memejamkan mata. Lalu membuka lagi. Matanya tidak merah, tapi seperti kehilangan cahaya.
“Ini bukan cashflow,” katanya. “Ini lubang.”
Panji ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa semua dimulai dari niat baik: memperbesar platform, menambah kelas untuk siswa daerah, meng-hire mentor terbaik, menyewa kantor yang “representatif” agar klien percaya, membayar iklan agar brand terlihat hidup.
Tapi Sekartaji memotong dengan tenang:
“Niat baik tidak membayar jatuh tempo.”
Kalimat itu sederhana. Justru karena sederhana, ia terasa seperti palu.
.
Lubang itu bernama Klana.
Klana bukan orang jahat. Ia hanya orang yang percaya bahwa hidup adalah kompetisi—dan siapa yang lambat harus rela disalip. Ia dulu teman Panji di salah satu komunitas bisnis. Rambutnya selalu rapi, arlojinya selalu sama: brand Swiss yang membuat pergelangan tangan seperti punya gengsi sendiri. Klana bicara cepat, tertawa cepat, mengambil keputusan cepat—seperti pasar saham yang tidak pernah minta izin sebelum naik atau jatuh.
Ketika Panji mencari dana tambahan, Klana datang seperti pahlawan di film, membawa “solusi”.
“Gini, Ji,” kata Klana di sebuah lounge hotel di Sudirman, di antara bunyi sendok yang halus dan musik jazz yang dibuat untuk menghibur orang-orang yang lelah jadi orang penting. “Kamu butuh dana cepat. Aku bisa. Tapi bukan dana kaku. Kita bikin skema. Kamu tetap jalan, brand tetap naik, tim tetap kerja.”
Panji menatap gelas airnya. Ia tahu kata “skema” di kota ini sering berarti: jalan pintas yang terlihat seperti jalan tol.
“Bunganya?” tanya Panji.
Klana tersenyum. “Aku nggak suka kata ‘bunga’. Kita sebut saja… fee.”
“Fee berapa?”
Klana menyebut angka yang membuat Panji berpikir dua kali. Tetapi Klana melanjutkan, seperti salesman yang tahu cara menyentuh titik lemah pelanggan.
“Kamu kan orang baik. Kamu punya misi. Kita bantu misi itu. Nanti kalau sudah stabil, lunasin. Simpel.”
Simpel.
Kata itu yang membuat banyak orang masuk ke masalah besar dengan langkah ringan.
Panji menerima.
Dan di sinilah utang mulai berubah bentuk: dari angka menjadi rasa takut. Dari angka menjadi insomnia. Dari angka menjadi kalimat-kalimat pendek yang ia ucapkan kepada Sekartaji: “aku aman kok”, “tenang aja”, “ini bagian dari growth.”
Di kantor, Panji tetap jadi Panji yang hebat: memimpin meeting, memberi motivasi, mengajak tim percaya pada visi. Ia bahkan memulai kebiasaan baru: setiap Senin pagi, ia menyapa tim dengan kalimat-kalimat yang terdengar seperti mantra.
“Yang penting konsisten.”
“Yang penting proses.”
“Yang penting kita jaga energi.”
Padahal energi yang ia jaga adalah energi kepura-puraan.
Suatu hari, Umarmaya datang ke kantor Panji. Umarmaya lebih tua sepuluh tahun, seorang mentor bisnis yang sudah kenyang menghadapi orang-orang muda yang ingin melompat lebih cepat dari umur mereka. Wajahnya tenang seperti sopir taksi bandara yang sudah melihat terlalu banyak drama penumpang.
Umarmaya duduk di ruang rapat, memandang whiteboard penuh target yang ditulis dengan spidol mahal.
“Ini bagus,” katanya pelan. “Tapi kamu kelihatan kurus.”
Panji tertawa kecil. “Lagi banyak kerjaan.”
“Kerjaan atau beban?”
Panji diam. Umarmaya tidak memaksa. Ia hanya berkata, “Kamu boleh sukses, Panji. Tapi jangan sukses dengan cara yang membuat kamu kehilangan muka di depan orang yang kamu sayangi.”
Panji menunduk.
Ia ingin bercerita. Tetapi ia takut. Di kota, takut sering memakai jas: rapi, wangi, terlihat profesional. Tetapi di dalamnya—kecil, gemetar, dan selalu siap lari.
.
Jatuh tempo pertama datang seperti hujan yang terlihat dari jauh: kamu tahu ia akan sampai, tapi kamu tetap berharap angin mengubah arah.
Klana mengirim pesan: “Ji, reminder ya. Besok.”
Panji membalas: “Siap, bro.”
Padahal ia belum siap.
Ia memutar otak: menunda pembayaran vendor, meminta tim menunggu reimburse, menekan pengeluaran kecil yang sebenarnya tidak kecil bagi orang yang bergaji bulanan. Panji mulai menukar satu rasa sakit dengan rasa sakit yang lain.
Ia membayar Klana dengan uang yang seharusnya untuk vendor.
Vendor menagih.
Ia membayar vendor dengan uang yang seharusnya untuk gaji.
Tim mulai bertanya pelan-pelan.
Panji mulai jadi orang yang alergi terhadap notifikasi.
Di rumah, Sekartaji melihat perubahan itu lebih cepat daripada Panji menyadarinya. Suatu malam, Sekartaji menemukan Panji duduk di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota seperti menatap ribuan mata yang sedang menilai hidupnya.
“Kamu takut?” tanya Sekartaji.
Panji ingin bilang tidak. Tapi mulutnya tidak sanggup.
Sekartaji duduk di sampingnya. “Aku bukan polisi. Aku istrimu. Tapi kalau kamu terus-terusan menyembunyikan ini, kamu bukan melindungi aku. Kamu sedang menenggelamkan kita.”
Panji menahan napas.
“Masalahnya bukan cuma uang,” lanjut Sekartaji. “Masalahnya kamu mulai terbiasa bohong.”
Kalimat itu membuat Panji merasa seperti berdiri di depan cermin yang tidak bisa dibohongi.
“Bohong kecil,” kata Sekartaji, “itu seperti bocor kecil di kapal. Kamu bisa menertawakan dulu. Tapi laut tidak pernah peduli kamu menertawakan apa.”
Panji menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis tanpa suara. Bukan karena ia lemah, tetapi karena tubuhnya akhirnya menyerah.
Di sela tangis yang tertahan, ada kalimat-kalimat yang keluar seperti pecahan kaca:
“Aku cuma pengin… kamu bangga.”
Sekartaji memegang tangannya.
“Aku bangga pada kamu sejak kamu masih belum punya apa-apa,” katanya. “Yang aku takutkan adalah kamu menggadaikan dirimu sendiri demi terlihat punya apa-apa.”
.
Keesokan harinya, Klana datang ke kantor. Ia tidak mengabari. Ia muncul seperti tagihan: tidak butuh undangan.
Klana duduk di ruang Panji, melihat sekitar, melihat laptop, melihat foto tim, melihat sertifikat-sertifikat yang dipajang.
“Kantor kamu oke,” katanya. “Sayang kalau ini berhenti.”
Panji menelan ludah. “Aku lagi berusaha.”
Klana tersenyum tipis. “Aku suka orang yang berusaha. Tapi aku lebih suka orang yang bayar.”
Panji merasakan panas di tengkuk. “Aku telat sedikit. Seminggu.”
Klana mengetuk meja pelan. “Seminggu di dunia bisnis itu lama, Ji.”
Panji ingin marah, tapi ia tidak punya hak. Utang mengubah posisi manusia. Utang bisa membuat orang yang dulu setara jadi terasa seperti atasan dan bawahan.
Klana berdiri. Ia merapikan kancing jasnya.
“Gini aja,” kata Klana. “Aku kasih opsi. Kamu jual sebagian saham ke aku. Nanti utang kamu anggap beres. Kamu tetap jalan. Aku masuk, bantu. Win-win.”
Panji membeku.
Itu bukan win-win. Itu pengambilalihan yang dibungkus kata manis.
“Aku pikir dulu,” kata Panji.
Klana menatap lama, lalu tertawa kecil.
“Kamu boleh pikir. Tapi jatuh tempo nggak bisa diajak diskusi.”
Klana pergi, meninggalkan aroma parfum yang mahal dan rasa takut yang lebih mahal.
.
Di sinilah Panji mengerti: utang bukan sekadar transaksi. Utang adalah ujian karakter.
Panji kemudian bertemu Jayengrana, seorang teman lama yang kini jadi pengacara. Mereka bertemu di kafe kecil di kawasan Blok M—bukan kafe fancy, tetapi kafe yang punya rasa manusia: kursi kayu yang sedikit goyah, musik yang tidak terlalu keras, barista yang menyapa dengan mata, bukan dengan prosedur.
Panji bercerita. Jayengrana mendengarkan, lalu berkata pelan:
“Yang paling berbahaya dari utang itu bukan bunganya. Tapi kebiasaan menunda kejujuran.”
Panji menunduk. “Aku malu.”
“Malu itu normal,” kata Jayengrana. “Tapi jangan jadikan malu sebagai alasan untuk membiarkan masalah membesar. Ada dua jalan: kamu hadapi sekarang, atau kamu menunggu sampai masalah menghadapi kamu.”
Panji mengangguk.
Jayengrana memberi saran praktis, tidak romantis:
-
Catat semua utang dengan jujur—bukan hanya angka, tapi jatuh tempo, konsekuensi, dan siapa yang harus kamu jaga martabatnya.
-
Stop pengeluaran yang hanya untuk citra. Yang tidak menyelamatkan cashflow, potong.
-
Komunikasi duluan kepada pihak yang kamu berutang sebelum mereka menagih. Di kota, orang lebih menghargai kejelasan daripada alasan.
-
Negosiasi restrukturisasi: cicilan, penjadwalan ulang, atau skema pembayaran bertahap.
-
Jangan menambah utang untuk menutup utang kecuali ada rencana terukur dan transparan.
Panji mendengar itu seperti orang yang baru diberi peta setelah tersesat lama.
Tetapi yang paling sulit bukan langkah-langkah itu. Yang paling sulit adalah langkah pertama: mengaku.
Malam itu, Panji pulang lebih cepat. Sekartaji sedang membaca di sofa. Panji duduk, dan berkata tanpa basa-basi:
“Aku mau beresin ini. Tapi aku butuh kamu. Aku nggak mau jadi orang yang pura-pura lagi.”
Sekartaji menutup bukunya. “Oke. Kita beresin.”
Di kata “kita”, Panji merasa seperti diselamatkan.
.
Mereka mulai dengan hal yang paling menyakitkan: membongkar gaya hidup.
Mereka membatalkan membership gym yang jarang dipakai. Menunda liburan yang sudah direncanakan. Menjual satu barang mewah yang selama ini hanya jadi simbol—jam tangan yang dulu dibeli Panji untuk “hadiah” ketika closing funding pertama.
Panji membawa jam itu ke toko. Ketika uangnya cair, ia menatap jumlahnya dan sadar: gengsi yang ia rawat bertahun-tahun ternyata bisa berubah jadi angka yang jauh lebih kecil daripada rasa takut yang ia tanggung.
Sekartaji membuat spreadsheet. Panji membuat daftar vendor. Mereka duduk bersama seperti tim kecil yang sedang menyusun strategi perang—perang melawan kebiasaan lama.
Panji mulai menelepon satu per satu.
Ada vendor yang marah. Ada yang dingin. Ada yang kecewa.
Tetapi ada juga yang berkata, “Mas, saya cuma butuh kejelasan. Kalau Anda jujur dari awal, saya nggak akan serumit ini.”
Kalimat itu—jujur dari awal—membuat Panji ingin menampar dirinya sendiri, tapi ia menahan. Ia memilih bekerja.
Puncaknya adalah Klana.
Panji bertemu Klana di tempat yang sama: lounge hotel. Kali ini, Panji tidak memesan apa pun selain air putih. Ia datang bukan sebagai orang yang minta waktu, tapi sebagai orang yang membawa keputusan.
“Aku nggak jual saham,” kata Panji.
Klana tersenyum miring. “Berani juga.”
“Aku restrukturisasi. Aku bayar bertahap. Ini rencanaku.” Panji menggeser map berisi jadwal pembayaran.
Klana membuka, membaca sekilas, lalu menutup lagi.
“Kamu tahu kan aku bisa bikin ini rumit?” tanya Klana.
Panji mengangguk. “Aku tahu.”
“Terus?”
Panji menatap Klana, dan untuk pertama kalinya ia tidak menunduk.
“Aku mungkin telat. Aku mungkin salah. Tapi aku nggak mau jadi pencuri yang mencuri kepercayaan orang lain.”
Klana terdiam sebentar. Di wajahnya, ada sesuatu yang bergerak—bukan iba, bukan marah, tapi semacam pengakuan yang tidak diucapkan.
Klana mengetuk map itu pelan.
“Kalau kamu ingkar, aku kejar,” katanya.
Panji mengangguk. “Itu hak kamu. Tapi kalau kamu setuju, aku akan bayar. Pelan-pelan. Sampai lunas.”
Klana menatap lama, lalu berkata, “Oke.”
Itu bukan kemenangan besar. Itu hanya pintu kecil yang dibuka.
Tapi kadang hidup tidak butuh pintu besar. Hidup butuh satu pintu saja—asal kamu berani melangkah.
.
Bulan-bulan setelah itu berjalan seperti musim hujan: tidak romantis, tetapi jujur.
Panji bekerja lebih keras, tapi dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar “tampak sukses.” Ia mengejar stabil. Ia mulai memotong program yang tidak menghasilkan. Ia fokus pada layanan yang benar-benar dibutuhkan. Ia berani menolak proyek yang hanya “bagus di portofolio” tapi membunuh cashflow.
Ia juga mengumpulkan tim dan berkata jujur, untuk pertama kalinya tanpa slogan:
“Kita sempat salah kelola. Aku minta maaf. Ini rencana beresnya. Aku nggak janji mulus. Tapi aku janji transparan.”
Sebagian orang memilih pergi. Itu menyakitkan. Tetapi yang bertahan menjadi tim yang lebih nyata. Mereka bukan lagi penonton motivasi, mereka jadi rekan kerja yang mengerti bahwa profesionalisme bukan berarti hidup tanpa retak—profesionalisme adalah keberanian memperbaiki retak tanpa pura-pura tidak ada.
Sekartaji melihat Panji pelan-pelan kembali menjadi manusia. Bukan manusia yang selalu menang, tapi manusia yang berani bertanggung jawab.
Suatu malam, ketika cicilan tahap ketiga sudah dibayar, Panji dan Sekartaji berjalan di trotoar yang basah. Lampu jalan memantul di genangan, membuat kota seperti berkilau palsu—seperti biasanya.
Panji berhenti, lalu berkata, “Aku dulu pikir utang itu cuma angka.”
Sekartaji menatapnya.
Panji melanjutkan, “Ternyata utang itu… latihan.”
“Latihan apa?” tanya Sekartaji.
“Latihan jadi manusia yang nggak lari.”
Sekartaji tersenyum kecil. “Akhirnya kamu pulang.”
Pulang. Kata itu hangat.
Panji menghela napas panjang, seperti orang yang baru saja keluar dari ruangan sempit.
“Maaf ya,” katanya.
Sekartaji mengangguk. “Maaf bukan akhir. Maaf itu pintu.”
Panji menatap langit Jakarta yang nyaris tak pernah benar-benar gelap karena lampu kota. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai. Utang masih ada. Pembayaran masih panjang. Tapi ada sesuatu yang berbeda: ia tidak lagi sendirian di balik topeng.
Dan ia belajar satu hal yang tidak diajarkan di sekolah bisnis mana pun:
Kepercayaan adalah mata uang yang paling sulit dicari ketika hilang—tetapi paling bernilai ketika dijaga.
Di rumah, sebelum tidur, Panji membuka ponselnya lagi. Poster “Jangan pernah sepelekan utang” muncul di grup keluarga. Kali ini ia tidak menggeser cepat. Ia membaca pelan.
Bukan karena takut azab semata.
Tapi karena akhirnya ia mengerti: utang, ketika diremehkan, tidak hanya mengganggu rezeki. Ia mengganggu ketenangan. Ia mengganggu harga diri. Ia mengganggu cinta—yang paling sering hancur bukan karena kurang uang, melainkan karena kurang jujur.
Panji menutup ponsel. Menatap Sekartaji yang sudah terlelap.
Dan dalam hati ia berjanji—lebih sunyi daripada sumpah mana pun:
Ia akan melunasi bukan hanya angka.
Ia akan melunasi kepercayaan.
.
.
.
Malang, 16 February 2026
.
.
#JanganSepelekanUtang #EtikaKeuangan #Kepercayaan #Keluarga #KrisisBisnis #BangkitLagi #LiterasiKeuangan #CerpenIndonesia #KompasMingguVibes #HidupPerkotaan